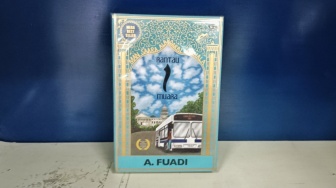Pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai yang enggan mengomentari isu kewajiban lapor polisi dalam KUHP dengan alasan “saya belum baca” patut menjadi alarm serius. Hal ini bukan semata karena isu tersebut sedang dipersoalkan publik.
Melainkan karena KUHP adalah jantung dari pengaturan Hak Asasi Manusia dalam negara hukum. Ketika seorang Menteri HAM menyatakan belum membaca KUHP, yang terdengar bukan kehati-hatian, melainkan kelalaian. Seorang Menteri HAM belum membaca KUHP adalah tindakan yang tidak bertanggungjawab.
Pagar Pertama Agar Kekuasaan Tidak Berubah Menjadi Kesewenang-wenangan
KUHP bukan sekadar kumpulan pasal pidana. Ia adalah instrumen negara yang langsung menyentuh hak paling mendasar warga negara: hak atas kebebasan, hak atas rasa aman, hak atas perlakuan yang adil, hingga batasan negara dalam menghukum warganya.
Setiap pasal pidana pada dasarnya adalah pembatasan HAM, sehingga harus dirumuskan secara ketat, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional.
Karena itu, mustahil memisahkan KUHP dari HAM.
Lebih janggal lagi, pernyataan “belum baca” datang setelah RKUHP melalui proses panjang dan melelahkan. Rancangan KUHP dibahas sejak 2019, menuai banyak kontroversi, diskusi publik, kritik akademik, dan tekanan masyarakat sipil.
Ia disahkan pada 6 Desember 2022, mulai berlaku 2 Januari 2024, dengan masa transisi tiga tahun. Artinya, negara (termasuk Kementerian HAM) memiliki waktu yang sangat panjang untuk memahami, mengkaji, dan menyiapkan sikap resmi.
Wibawa Kementerian dan Akal Sehat Negara Hukum
Dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan, keterlibatan kementerian terkait bukan pilihan, melainkan kewajiban prosedural. Kementerian HAM hampir pasti terlibat dalam sedikitnya lima tahapan penting.
- Pertama, rapat koordinasi antar-kementerian dalam pembahasan RKUHP. Ini adalah prosedur wajib dalam harmonisasi regulasi nasional.
- Kedua, adanya permintaan pertimbangan tertulis dari Kementerian Hukum dan HAM selaku leading sector kepada kementerian lain, termasuk Kementerian HAM, untuk menilai dampak HAM.
- Ketiga, keterlibatan pemerintah termasuk perwakilan kementerian dalam rapat Panitia Kerja atau Panitia Khusus DPR, yang notulensinya tercatat secara resmi.
- Keempat, Naskah Akademik RKUHP yang secara hukum wajib memuat kajian dampak HAM sesuai Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kelima, rangkaian uji publik dan FGD sejak 2019 yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Dengan rangkaian proses sepanjang itu, klaim “belum baca” menjadi sulit diterima sebagai alasan yang wajar. Dalam konteks jabatan publik, “belum baca” bukanlah sikap netral. Ia dapat dimaknai sebagai ketidaksiapan, ketidakpedulian, atau penghindaran tanggung jawab.
HAM Bukan Aksesoris Kebijakan yang Bisa Dibahas Nanti
KUHP sendiri memiliki fungsi fundamental. Menetapkan perbuatan pidana, menentukan jenis dan berat sanksi, serta memberi kepastian hukum bagi masyarakat dan aparat penegak hukum.
Ia menjadi pedoman moral dan sosial tentang apa yang dilarang negara dan bagaimana negara menghukum. KUHAP kemudian melengkapinya dengan memastikan proses penegakan hukum berjalan adil dan prosedural. Keduanya tak terpisahkan dari prinsip HAM.
Karena itu, Kementerian HAM seharusnya menjadi benteng terakhir, bukan penonton yang terlambat masuk ruang diskusi. Publik tidak menuntut komentar instan, tetapi menuntut tanggung jawab dan kompetensi. Dalam isu sepenting pembatasan kebebasan warga negara, seorang Menteri HAM tidak cukup berkata “belum baca”.
Jika Penjaga HAM Sendiri Absen dari Tanggung Jawab Membaca dan Memahami Hukum Pidana
Yang dibutuhkan publik hari ini sederhana. Pertanggungjawaban hukum pidana atas nama Hak Asasi Manusia. Jika tidak, maka fungsi Kementerian HAM patut dipertanyakan. Bukan oleh oposisi, tetapi oleh akal sehat demokrasi itu sendiri. Publik berhak menyimpulkan satu hal. Yang tidak bekerja bukan pasalnya, melainkan negara.
Pada akhirnya, masalahnya bukan sekadar satu pasal atau satu pernyataan “belum baca”. Masalahnya adalah mentalitas kekuasaan yang menganggap Hak Asasi Manusia sebagai urusan sekunder, bukan fondasi utama hukum pidana.
Ketika KUHP, yang merupakan kitab yang memberi negara kuasa memenjarakan warganya. Justru diakui belum dibaca oleh Menteri HAM, maka yang terancam bukan hanya kredibilitas jabatan, tetapi keselamatan prinsip negara hukum itu sendiri.
Negara tidak boleh mengatur kebebasan warganya dengan hukum yang tidak dipahami oleh penjaga HAM-nya. Jika membaca KUHP saja belum menjadi prioritas, publik berhak bertanya. Siapa sebenarnya yang sedang dijaga oleh hukum negara? Hak asasi manusia, atau kenyamanan kekuasaan?