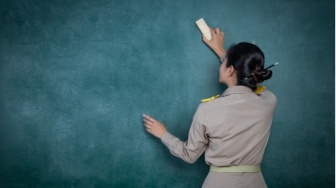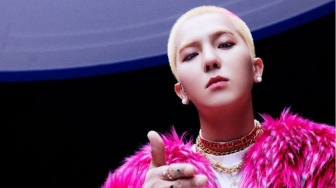Sekolah, dalam persepsi yang diwariskan secara turun-temurun, adalah institusi tempat manusia muda dibentuk menjadi pribadi yang “berpendidikan”. Namun, dari mana kita mengukur pendidikan itu? Apakah dari seberapa banyak rumus yang bisa dihafal, seberapa tinggi nilai rapor, atau dari seberapa patuh siswa mengikuti perintah?
Pertanyaan itu perlu kita ajukan ulang, sebab sekolah hari ini lebih tampak seperti ruang produksi massal yang hanya peduli pada hasil, bukan proses manusiawi di dalamnya. Kita belajar membaca, menulis, berhitung, tetapi tidak belajar mendengar, berdialog, dan memahami.
Kita hafal nama-nama menteri, tetapi gagap menyikapi ketidakadilan yang terjadi di sekitar rumah sendiri. Yang lebih mengkhawatirkan, kita terbiasa menerima kebenaran sebagai sesuatu yang final, bukan sebagai medan tanya yang harus terus diuji.
Pengetahuan yang diajarkan di sekolah selama ini sering dianggap sebagai sesuatu yang netral, obyektif, dan bebas nilai. Namun dalam Pedagogy of the Oppressed (1970), Paulo Freire menegaskan bahwa pendidikan tidak pernah netral; ia selalu berpihak. Ia bisa berpihak pada pembebasan atau pada penindasan.
Ketika siswa hanya dianggap sebagai “bejana kosong” yang harus diisi oleh guru, maka pendidikan menjelma menjadi proses penjinakan, bukan pembebasan. Kita tak pernah diajak mempertanyakan: mengapa sejarah nasional hanya mengangkat tokoh-tokoh tertentu? Mengapa tokoh pemberontak selalu dicitrakan sebagai musuh, padahal dalam beberapa konteks mereka justru berjuang melawan ketimpangan?
Pengetahuan yang diajarkan di sekolah, dengan demikian, adalah hasil seleksi wacana yang sangat ideologis. Kita belajar tentang negara, tapi tidak tentang rakyat. Kita belajar struktur pemerintahan, tapi tidak pernah diajak memahami bagaimana ketidakadilan struktural bekerja dalam kehidupan sehari-hari.
Hal yang paling kosong dari sekolah kita adalah ketiadaan ruang untuk memanusiakan manusia. Dalam Democracy and Education (1916), John Dewey menekankan bahwa pendidikan seharusnya menjadi proses sosial yang demokratis, di mana peserta didik bukan hanya diajari isi pengetahuan, tetapi juga diberi pengalaman untuk hidup secara bermakna dalam komunitas.
Namun dalam praktiknya, sekolah lebih banyak melatih kepatuhan ketimbang kemandirian berpikir. Kita diajarkan teori moral dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, tetapi tidak pernah diajak berdialog tentang pengalaman tidak adil yang mungkin dialami oleh siswa sendiri, entah karena latar belakang sosial, agama, atau bahkan warna kulit.
Kita disuruh menyanyikan lagu wajib setiap hari Senin, tetapi tidak pernah diajak merenungi makna kemerdekaan dalam konteks ketimpangan akses pendidikan itu sendiri. Padahal, kemanusiaan tidak bisa diajarkan melalui diktat, ia tumbuh lewat pengalaman, lewat ruang untuk gagal, dan terutama lewat proses refleksi.
Kritik terhadap sistem pendidikan yang kaku dan represif sudah lama disuarakan oleh para pemikir besar. Ivan Illich dalam Deschooling Society (1971) secara radikal mengkritik keberadaan sekolah modern yang menurutnya justru menciptakan ketergantungan, stratifikasi, dan kesenjangan sosial yang semakin tajam.
Illich menyebut bahwa sekolah telah menjelma menjadi lembaga yang membatasi kreativitas dan membonsai imajinasi. Dalam konteks Indonesia, hal ini terasa nyata. Banyak siswa cerdas yang justru kehilangan semangat belajarnya di sekolah karena terlalu sering disalahkan saat bertanya.
Mereka menjadi “pintar diam”, karena bertanya dianggap sebagai bentuk pembangkangan. Padahal, dalam masyarakat demokratis, keberanian untuk bertanya dan mempertanyakan adalah fondasi dari kehidupan bernegara yang sehat. Sayangnya, ruang kritis itu jarang ada di sekolah kita.
Karl Popper dalam The Open Society and Its Enemies(1945) menekankan pentingnya budaya kritik dalam membangun masyarakat terbuka. Namun dalam dunia pendidikan kita, kritik justru sering dianggap ancaman. Anak-anak yang mencoba menyuarakan keresahannya dianggap pembangkang.
Organisasi siswa seperti OSIS pun kerap dikendalikan dari atas oleh guru atau kepala sekolah, sehingga kehilangan makna partisipasi sejati. Diskusi dibatasi, tema dibatasi, bahkan keberanian untuk berbeda pun dibungkam atas nama ketertiban.
Dalam suasana seperti itu, anak-anak tumbuh menjadi generasi yang tahu cara menjawab soal ujian nasional, tetapi tidak tahu bagaimana bersikap saat melihat kecurangan, ketidakadilan, atau bahkan kekerasan di sekitarnya. Mereka hafal pasal-pasal hukum, tetapi ragu menyuarakan suara nuraninya.
Maka wajar jika banyak lulusan sekolah kita yang gagap menghadapi realitas. Mereka tahu teori demokrasi, tetapi tidak mampu berdialog dengan teman yang berbeda pilihan politik. Mereka tahu konsep toleransi, tetapi ikut menyebarkan ujaran kebencian di media sosial.
Mereka tahu hukum gravitasi Newton, tetapi tidak tahu cara merespons teman sekelas yang sedang berduka karena kehilangan orang tua. Kecerdasan akademik tidak selalu berbanding lurus dengan kecerdasan emosional dan sosial. Sekolah gagal membangun sense of humanity yang utuh karena terlalu fokus pada kognisi dan melupakan afeksi.
Apa yang bisa kita lakukan? Perbaikan tentu tidak bisa dilakukan secara instan. Tapi ada beberapa hal yang bisa menjadi awal. Pertama, kurikulum nilai seharusnya tidak lagi berbasis hafalan, melainkan pengalaman. Anak-anak perlu mengalami sendiri makna kerja sama, empati, dan tanggung jawab melalui aktivitas nyata, bukan sekadar narasi di buku teks.
Kedua, guru harus diberi ruang untuk menjadi fasilitator dialog, bukan sekadar pelaksana administrasi pembelajaran. Hubungan pedagogis perlu ditata ulang agar lebih setara dan saling belajar.
Ketiga, sistem penilaian perlu lebih lentur, agar tidak hanya mengukur keberhasilan dari hasil ujian, tetapi juga dari proses belajar dan tumbuh sebagai manusia. Keempat, siswa perlu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di sekolah, agar mereka merasa memiliki dan belajar tentang demokrasi secara langsung, bukan sekadar dalam teori.
Ki Hajar Dewantara, dalam karya-karyanya pada tahun 1920-an hingga 1940-an, sudah menekankan pentingnya pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan, katanya, adalah proses membentuk watak dan kecerdasan dalam rangka memajukan kehidupan bangsa.
Tapi kemerdekaan dalam pendidikan hari ini terlalu sering dimaknai sebagai kebebasan memilih jurusan atau sekolah, bukan kebebasan berpikir dan bersuara. Kita perlu kembali pada semangat pendidikan yang membebaskan, seperti yang ditekankan oleh Freire, Dewey, dan juga oleh pendiri pendidikan nasional kita sendiri.
Sekolah mestinya menjadi ruang aman untuk gagal, ruang yang menyemai rasa ingin tahu, bukan rasa takut. Ia seharusnya menjadi tempat manusia menemukan dirinya, bukan kehilangan dirinya demi standar nilai yang impersonal. Jika pendidikan tidak memanusiakan, maka ia hanya menjadi alat untuk mereproduksi ketimpangan dan ketakutan. Maka pertanyaannya: sekolah mencetak apa? Lulusan yang siap kerja, atau warga yang siap berpikir kritis dan peduli pada sesama?
Kita boleh mengajarkan teori trigonometri, tetapi jangan lupakan pelajaran mendengarkan. Kita boleh menguji pemahaman soal konstitusi, tetapi jangan hilangkan pelajaran tentang rasa keadilan. Karena pada akhirnya, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang membuat manusia menjadi lebih manusia. Dan untuk itu, sekolah perlu lebih dari sekadar ruang kelas ia perlu menjadi ruang hidup.