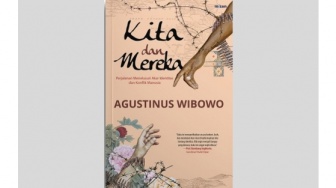Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sedang menjadi bahan perbincangan nasional, bukan hanya karena maraknya kasus keracunan, tetapi juga karena pertanyaan besar soal prioritas anggaran negara.
Di balik piring nasi gratis yang dibagikan kepada jutaan anak Indonesia, kini muncul suara lantang dari kelompok masyarakat sipil, akademisi, hingga praktisi pendidikan, yang mempertanyakan, apakah dana triliunan rupiah yang digelontorkan pemerintah seharusnya tetap dipertahankan untuk MBG, atau dialihkan ke sektor pendidikan yang sudah lama menjerit kekurangan?
Angkanya memang membuat banyak orang mengernyit. Dalam rancangan APBN 2026, pemerintah sudah menetapkan dana ratusan triliun rupiah untuk menjamin kelanjutan MBG. Dana sebesar itu mencakup biaya logistik, bahan makanan, distribusi, hingga pembangunan dan pengawasan ribuan dapur umum.
Di sisi lain, laporan Bank Dunia dan UNESCO terus mengingatkan bahwa Indonesia menghadapi masalah mendasar dalam kualitas pendidikan, seperti ketimpangan mutu guru, fasilitas belajar yang buruk, serta kurikulum yang kerap tertinggal dari kebutuhan zaman.
Masyarakat sipil pun mulai mengajukan argumen yang sulit diabaikan. Mereka menilai, anak yang kenyang memang bisa belajar hari itu, tetapi anak yang mendapat pendidikan bermutu akan memiliki kesempatan keluar dari lingkar kemiskinan seumur hidupnya.
Namun pemerintah punya logika sendiri. Mereka menekankan bahwa perbaikan gizi adalah fondasi yang tak kalah penting dari kurikulum dan fasilitas belajar. Data UNICEF menunjukkan sekitar 24% anak Indonesia mengalami stunting, dan masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan menambah guru atau merevisi kurikulum.
Anak dengan asupan gizi buruk akan kesulitan berkonsentrasi, tertinggal dalam perkembangan otak, dan pada akhirnya memiliki kemampuan belajar yang lebih rendah. Bagi pemerintah, MBG adalah investasi gizi yang sama pentingnya dengan investasi pendidikan.
Dilema ini semakin pelik ketika menilik realitas lapangan. Sejak peluncurannya, program MBG dihantui laporan keracunan di berbagai daerah.
Data dari CISDI mencatat lebih dari 7.100 kasus, sementara pemerintah bersikeras bahwa angka resmi hanya sekitar 4.600 kasus. Perbedaan data ini menimbulkan pertanyaan serius tentang transparansi, apalagi hingga kini belum ada dashboard pelaporan publik yang bisa diakses masyarakat.
Infrastruktur dapur pun jauh dari kata ideal. Dari 8.583 dapur penyedia MBG, hanya 34 yang memiliki sertifikat laik higiene. Bahkan di dapur bersertifikat pun, SOP kebersihan sering dilanggar.
Di tengah kondisi seperti itu, sulit untuk tidak mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran yang begitu besar. Apakah menambah sertifikat dapur akan menyelesaikan masalah, atau sekadar menambah lapisan birokrasi tanpa jaminan keamanan pangan?
Jika program dengan dana sebesar ini tidak mampu memastikan makanan aman bagi anak-anak, wajar bila publik mulai mendorong agar dana dialihkan ke sektor lain yang lebih siap menyerap dan memberi hasil nyata, seperti pendidikan.
Tetapi menghentikan atau memangkas MBG bukan perkara sederhana. Banyak pengamat melihat MBG sebagai program andalan pemerintahan Prabowo–Gibran, simbol keberpihakan pada rakyat kecil yang dijaga mati-matian.
Mengurangi porsi anggaran MBG, apalagi menghentikannya sementara, bisa dianggap sebagai langkah politis yang berisiko. Apalagi dana untuk program ini sudah dipatok dalam APBN 2026, membuat opsi pengalihan anggaran secara teknis dan politis semakin sulit.
Menurut Sobat Yoursay, apakah lebih baik anak-anak makan siang seadanya tetapi mendapat pendidikan berkualitas, atau kenyang dengan risiko keracunan sementara kualitas sekolah tetap tertinggal?
Dilema ini memang terasa bertentangan, meski kenyataannya jauh lebih kompleks. Anggaran negara jelas terbatas. Setiap rupiah yang digelontorkan untuk MBG berarti ada sektor lain, termasuk pendidikan, yang harus menunggu.
Perdebatan soal prioritas ini seharusnya tidak berhenti pada adu angka. Lebih dari sekadar memilih antara “makan” dan “sekolah,” isu ini menguji komitmen pemerintah dalam menata arah pembangunan.
Apakah kita ingin generasi yang sehat tetapi minim daya kritis, atau generasi yang cerdas namun rapuh fisiknya? Jawaban ideal tentu saja bukan memilih salah satu, tetapi menemukan keseimbangan. Namun keseimbangan hanya mungkin jika pemerintah berani menilai mana program yang benar-benar efektif dan mana yang sekadar populer di baliho kampanye.
Di balik janji gizi untuk masa depan, kita sedang menimbang pilihan antara politik pencitraan atau investasi jangka panjang. Jika pemerintah tetap menutup mata terhadap masalah keamanan pangan, sementara sektor pendidikan terus tertinggal, kita bisa saja berakhir dengan anak-anak yang kenyang hari ini, tetapi tetap lapar akan masa depan yang layak.