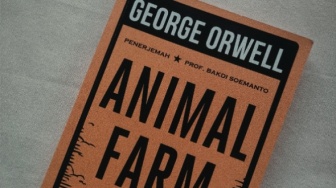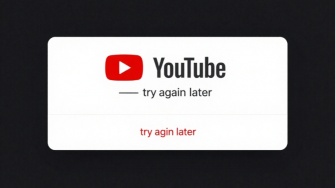Sobat Yoursay, mulai hari ini, 2 Januari 2026, Indonesia resmi memasuki babak baru dalam sejarah hukum pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) versi baru akhirnya berlaku penuh.
Pemerintah dan DPR menyebut momen ini sebagai tonggak penting, penanda berakhirnya hukum kolonial dan warisan Orde Baru yang selama puluhan tahun menjadi fondasi penegakan hukum. Pemerintah menganggap ini sebagai kabar baik. Tapi faktanya, banyak warga justru mengernyitkan dahi.
Dari Senayan, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menegaskan bahwa proses penyusunan KUHP dan KUHAP tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Pembahasannya disebut panjang, melelahkan, dan melibatkan partisipasi publik.
Pemerintah pun menyatakan aparat penegak hukum sudah siap, tanpa masa transisi, tanpa ruang abu-abu. Semua bisa langsung berjalan. Seolah hukum ini sudah matang, rapi, dan aman untuk dipakai.
Namun sobat Yoursay, sejak kapan hukum di Indonesia hanya soal kesiapan aparat? Yang sering tertinggal justru kesiapan warga sebagai subjek hukum.
Kita sedang bicara tentang aturan yang akan menyentuh kehidupan sehari-hari, dari cara orang berbicara, mengkritik, hingga berhadapan dengan negara. Ketika hukum pidana berubah, yang dipertaruhkan sudah pasti relasi kuasa antara negara dan warganya.
Di sinilah kekhawatiran mulai muncul. Amnesty International Indonesia, melalui Usman Hamid, mengingatkan bahwa KUHP dan KUHAP baru berpotensi mempermudah kriminalisasi terhadap warga yang kritis. Beberapa pasal dinilai melonggarkan kembali ruang pemidanaan terhadap kritik kepada pejabat dan institusi negara.
Sobat Yoursay tentu masih ingat bagaimana pasal-pasal karet bekerja di masa lalu. Pasal-pasal itu jarang dipakai untuk melindungi yang lemah, tapi sering hadir untuk menekan yang aktif bersuara. Kekhawatiran publik ini bukannya tanpa alasan. Kita punya sejarah panjang tentang hukum yang tampak netral, tapi bekerja selektif.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas sendiri mengakui adanya potensi penyalahgunaan. Ia menyebut pengawasan publik sebagai kunci agar penegakan hukum tetap proporsional.
Nah, jika sejak awal sudah diakui ada risiko, mengapa aturan ini tetap diberlakukan tanpa jeda? Mengapa beban pengawasan justru dilempar ke publik yang posisinya tidak seimbang dengan aparat?
Sobat Yoursay, pengawasan publik itu penting, tapi ia tidak bisa berdiri sendiri. Pengawasan publik membutuhkan ruang aman dan kebebasan berekspresi. Dan di sinilah lingkaran persoalan muncul. Bagaimana publik bisa mengawasi, jika kritik berpotensi dianggap pelanggaran? Bagaimana bisa warga bersuara, jika hukum pidana berdiri terlalu dekat dengan kepentingan kekuasaan?
Masalahnya, sobat Yoursay, kita hidup di mana kepercayaan publik terhadap penegakan hukum masih rapuh. Kasus-kasus besar sering tak tuntas. Ketimpangan perlakuan hukum masih terasa. Dalam situasi seperti ini, memberi aparat kewenangan baru tanpa memperkuat mekanisme akuntabilitas adalah perjudian besar.
KUHAP baru memang menjanjikan banyak hal, dari keadilan restoratif hingga sistem peradilan berbasis teknologi. Semua terdengar progresif. Tapi teknologi tidak otomatis membuat hukum adil. Dan restoratif tidak otomatis berpihak pada korban. Semuanya kembali pada siapa yang memegang kuasa dan bagaimana ia menggunakannya.
Kita tidak bisa hanya menunggu dan berharap semuanya berjalan baik. Hukum pidana adalah senjata paling tajam yang dimiliki negara. Di tangan yang tepat, ia melindungi. Namun di tangan yang salah, ia bisa melukai.
Sobat Yoursay, hukum pidana baru mungkin sudah resmi diberlakukan, namun pergantian wajah institusi bukanlah jaminan keadilan.
Fokus utama kita seharusnya tertuju pada watak penegakannya. Mengingat watak kekuasaan yang kerap menyimpang, satu-satunya cara untuk menjaganya adalah melalui kewaspadaan publik.
Jangan berhenti bersuara dan teruslah bertanya, karena tanpa kontrol masyarakat, hukum hanya akan menjadi alat kekuasaan semata.