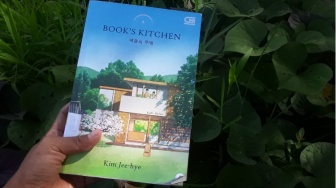Bagi sebagian laki-laki, Cinta justru muncul saat pasangannya tak lebih “tinggi” dari dirinya—baik secara karier, pendidikan, maupun status sosial. Fenomena ini dikenal dengan istilah “Men Marry Down”, dan kabarnya masih cukup masif di Indonesia.
Di saat perempuan menempuh pendidikan tinggi dan meraih posisi penting di dunia kerja, preferensi sebagian laki-laki justru belum sepenuhnya berubah. Mereka masih merasa lebih nyaman ketika berada dalam posisi “lebih unggul” dari pasangannya.
Sedikit kilas balik, kecenderungan ini tak lepas dari konstruksi budaya yang sudah mengakar lama. Dalam sistem patriarki, laki-laki kerap diajarkan untuk menjadi “pemimpin” dan penentu arah dalam hubungan.
Kecenderungan ini juga melekat karena munculnya keinginan laki-laki untuk selalu dominan serta menjadi “provider man” dalam hubungannya.
Ketika posisi itu tergeser, misalnya karena pasangan memiliki karier lebih cemerlang atau penghasilan lebih tinggi, sebagian pria bisa merasa identitas maskulinnya terancam.
Di sisi lain, masyarakat juga ikut memperkuat standar itu. Perempuan yang “terlalu sukses” sering kali dianggap menakutkan atau sulit didekati. Akibatnya, banyak perempuan berprestasi yang merasa harus “merendah” agar tidak terlihat menyaingi laki-laki di sekitarnya.
Lebih jauh, masyarakat sekitar juga beranggapan bahwa laki-laki selalu dilekatkan sebagai sosok pencari nafkah, memiliki karier yang bagus, serta berpendapatan tinggi.
Berbanding terbalik dengan perempuan. Masyarakat cenderung melekatkan perempuan sebagai sosok yang mendukung, melayani, merawat dan menuruti perintah laki-laki.
Namun, menariknya, fenomena men marry down ini tidak hanya terjadi karena faktor budaya semata, tetapi juga karena kombinasi antara ego, norma sosial, dan persepsi tentang keseimbangan kekuasaan dalam hubungan.
Bagi sebagian laki-laki, memiliki pasangan dengan status “lebih rendah” sering kali memberi rasa nyaman dan kontrol. Mereka merasa lebih dibutuhkan, lebih dominan, dan lebih mampu menjalankan peran tradisional sebagai pemimpin keluarga.
Sebaliknya, ketika perempuan berada di posisi yang lebih tinggi, entah secara ekonomi, pendidikan, atau pengaruh sosial. Relasi itu sering kali menimbulkan ketegangan tersendiri.
Tidak jarang, laki-laki merasa kehilangan “ruang” untuk menunjukkan fungsinya sebagai pelindung dan penyedia. Akibatnya, sebagian pria memilih pasangan yang dianggap “lebih sederhana” agar tidak perlu berhadapan dengan ancaman terhadap identitas maskulin mereka.
Hingga pada akhirnya, fenomena men marry down lebih dari sekadar soal cinta atau preferensi pribadi. Ini adalah cermin dan bentuk dari bagaimana masyarakat masih menilai seseorang, terutama laki-laki berdasarkan posisi, kuasa, dan peran tradisional.
Lebih jauh lagi, selama konsep maskulinitas masih diukur dari “siapa yang lebih unggul” bayang-bayang men marry down akan terus menghantui relasi modern.
Di sisi lain, perubahan mungkin memang sedang terjadi, tapi tidak secepat yang kita bayangkan. Butuh keberanian dari kedua sisi, perempuan yang tak lagi merasa harus merendah demi diterima, dan laki-laki yang cukup percaya diri untuk tidak merasa terancam oleh kesuksesan pasangannya.
Fenomena ini menyoroti bahwa hubungan seharusnya tidak dibangun atas dasar siapa yang lebih tinggi atau lebih berkuasa. Sebab, cinta yang sejati tidak lahir dari hierarki, melainkan dari relasi yang saling menghargai.
CEK BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS