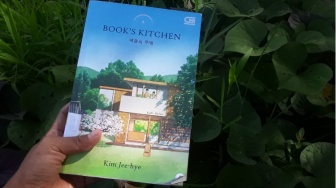Media sosial bukan hanya tempat berbagi informasi, tetapi juga mulai bertransformasi menjadi arena “pengadilan publik”. Ketika seseorang melakukan kesalahan, baik selebritas, influencer, pejabat, hingga orang biasa, netizen sering bergerak cepat untuk mengadili.
Bahkan tidak jarang ada yang mulai menggali jejak digital, membuat utas panjang, menyebarkan screenshot, hingga mengajak orang lain untuk unfollow, boikot, atau “menghukum” secara massal yang dikenal sebagai cancel culture.
Sementara itu, ada juga praktik call-out, yakni menegur perilaku seseorang secara terbuka di ruang publik sebagai bentuk edukasi sosial. Namun di balik niat “meluruskan moral”, ada celah di mana toxic call-out dan cyberbullying seolah-olah menjadi tindakan etis.
Pertanyaan besar pun muncul, apakah benar semua tindakan itu merupakan bentuk edukasi sosial? Atau justru bentuk baru dari tekanan massa dan kekerasan verbal yang “dilegalkan” lewat moralitas?
Cancel Culture: Dari Mengedukasi Jadi Menghakimi
Secara ideal, cancel culture muncul untuk meminta pertanggungjawaban seseorang usai melakukan tindakan tidak pantas, entah itu ujaran rasis, pelecehan, atau penipuan. Namun dalam praktiknya, budaya ini malah sering bergeser.
Tidak jarang cancel culture berujung pada ajakan untuk membenci seseorang secara massal dan serangan pribadi, bukan kritik perilaku. Bumbu berupa penggiringan opini tanpa fakta lengkap juga semakin banyak diungkap.
Pada akhirnya, tidak semua cancel culture bergeser menjadi hukuman sosial yang tidak seimbang dengan kesalahan dan berubah arah menjadi bentuk pelampiasan amarah kolektif dibanding proses edukasi.
Yang lebih mengkhawatirkan, masyarakat sering terburu-buru memvonis sebelum memahami konteks. Satu video berdurasi lima detik bisa jadi “bukti kuat” untuk menghancurkan reputasi seseorang tanpa kesempatan menjelaskan.
Call-Out Culture: Antara Teguran dan Toxic Policing
Call-out awalnya dimaksudkan untuk memberi koreksi saat seseorang menyampaikan informasi salah atau menunjukkan perilaku yang tidak sensitif dengan tujuan mengingatkan secara terbuka.
Namun, di era media sosial yang serba kompetitif dan cepat, call-out culture sering berubah menjadi ajang pamer moralitas, konten viral untuk engagement, serangan terbuka agar pelaku malu di ruang publik, sampai pembuktian “saya lebih benar daripada kamu”.
Toxic call-out tidak lagi bertujuan mendidik, melainkan untuk mempermalukan. Pada titik ini, call-out culture bukan edukasi, melainkan bullying berkedok moralitas.
Mengapa Cancel Culture dan Call-Out Culture Mudah Menjadi Toksik?
Disadari atau tidak, pada akhirnya cancel culture dan call-out culture mudah menjadi perilaku toksik yang semakin sering muncul di media sosial. Ada beberapa alasan mengapa kedua fenomena ini rentan keluar jalur.
1. Viralnya Konten Negatif Memberi Reward Sosial
Kontroversi selalu menarik perhatian. Semakin keras serangan netizen, semakin cepat konten itu viral. Engagement naik, views bertambah, dan orang merasa “diterima” dalam kelompok moral digital.
2. Tidak Ada Mekanisme Klarifikasi yang Seimbang
Dalam dunia nyata, ada proses hukum lewat mediasi atau dialog. Sementara di media sosial, siapa paling cepat bersuara, dialah yang dianggap benar.
3. Netizen Sering Mengikuti Arus
Banyak orang ikut mengecam hanya karena melihat temannya melakukannya atau banyak konten yang menyudutkan sering masuk algoritma internet. Mereka enggan mengecek fakta dan bahkan tidak memahami konteks.
4. Budaya Screenshot Menghidupi Toxicity
Apa pun bisa dipelintir berkat maraknya budaya screenshot yang semakin menghidupkan toxicity. Satu kalimat yang diambil dari konteks utuh bisa diubah menjadi bukti “kesalahan besar” yang mendukung penghakiman sosial.
5. Kebutuhan Membuktikan Diri sebagai “Warga Baik”
Kebanyakan netizen ingin terlihat sebagai orang beretika, peduli moral, dan tidak toleran terhadap kesalahan. Ironisnya, proses “menunjukkan kebaikan” ini justru sering dilakukan dengan cara tidak baik, termasuk dengan terlibat dalam budaya cancel culture.
Dampak Psikologis: Bukan Sekadar Drama Internet
Baik cancel culture maupun toxic call-out bisa meninggalkan dampak besar pada korban. Di antaranya, gangguan kecemasan, kehilangan pekerjaan, reputasi rusak permanen, takut tampil di media sosial, hingga trauma akibat hujatan massal.
Yang paling tragis, tidak sedikit kasus di dunia yang berujung pada tindakan ekstrem karena tekanan massal yang terlalu besar. Saat “edukasi” berubah menjadi amukan publik, tidak ada lagi ruang untuk memperbaiki diri kecuali hukuman tanpa ampun.
Kalau Tidak Cancel Culture, Lalu Harus Apa?
Cancel culture yang tujuannya mulai bergeser lewat perilaku toksik yang mengarah pada cyberbullying seolah tidak bisa menjadi solusi utama untuk memberi hukuman pada pelaku yang menodai norma.
Bukan tidak boleh dilakukan, hanya saja cancel culture harus tetap berfokus pada hukuman sesuai kesalahan tanpa melebar ke ranah privat. Dahulukan juga fact-check sebelum bereaksi dan beri ruang untuk klarifikasi.
Kalau tujuannya untuk edukasi dan memperbaiki perilaku pelaku, upayakan juga untuk menghargai proses belajar manusia yang pernah salah dan ingin berubah menjadi lebih baik.
Tidak kalah penting, pastikan untuk tetap fokus pada perubahan sistem, bukan menghancurkan individu karena “menghabisi” seseorang tidak selalu menyelesaikan masalah yang lebih besar.
Fokus Edukasi, Bukan Eksekusi
Cancel culture dan toxic call-out pada dasarnya muncul dari niat baik untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan bermoral. Namun, ketika dilaksanakan tanpa empati dan tanpa proses yang sehat, hasilnya justru menjadi bentuk baru dari bullying.
Internet seharusnya menjadi ruang diskusi, bukan gelanggang eksekusi. Ingat, edukasi tidak sama dengan mempermalukan. Sebab, kalau ingin dunia digital lebih sehat, kita perlu berhenti menjadikan moralitas sebagai senjata.