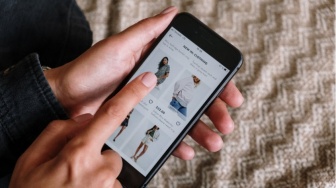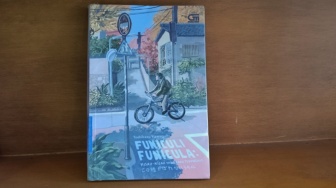Baru-baru ini, kita dihebohkan dengan aksi perempuan nelayan di Demak yang tergabung di Puspita Bahari. Mereka berpartisipasi dan ikut dalam aksi Kampanye Global 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 HAKTP) pada 25 November-10 Desember 2025.
Dalam kesempatan itu, Puspita Bahari (organisasi perempuan nelayan di Kabupaten Demak), melakukan aksi lewat Parade 16 Perahu Perempuan Nelayan dan Rembuk Pesisir. Mereka kompak untuk menyampaikan langsung pengalaman dan harapan mereka akibat eksploitasi pesisir yang merusak kehidupan mereka.
Pada dasarnya, aksi itu bukan sekedar protes yang fotogenik namun mereka hendak menyerukan jeritan panjang yang selama ini tenggelam akibat kebijakan yang tak pernah melihat ke arah mereka,
Tak bisa dipungkiri, perempuan di pesisir memiliku beban besar dalam kehidupan. Perempuan pesisir bertanggung jawab untuk ikut melaut, mengolah hasil tangkapan, sekaligus menjaga rumah tangga. Semua tanggung jawab itu dilakukan setiap hari tetapi bersamaan dengan itu ada ketidakadilan struktural yang terjadi.
Ketidakadilan Struktural yang Menggerus Nelayan Perempuan
Seperti yang telah diuraikan, perempuan nelayan punya tantangan yang berlapis-lapis. Tak Cuma dari statusnya, beban ekonomi, dan lingkungan kerja yang berat, namun mereka harus menghadapi pembangunan pesisir yang minim perspektif gender.
Penulis mengambil contoh yang paling dekat adalah Setiap bulan, banjir rob di Jalur Pantura Demak tetap muncul. Padahal, pemerintah telah menyiapkan infrastruktur penanganan, tol sekaligus tanggul laut.
Salah satu tujuan proyek ini, dipersiapkan berhasil menghalangi penyebab rob di sepanjang pesisir Semarang dan Demak. Namun hingga kini rob masih menggenang bahkan berpindah lokasi.
Peristiwa ini adalah salah satu peristiwa bagaimana perempuan nelayan harus menghadapi dampak dari kerusakan ekologis dan pembangunan yang ekstratif. Sekali lagi, yang paling terdampak adalah perempuan.
Berkaca dari hal ini, ketidakadilan ini tidak muncul begitu saja namun harus diakui ia lahir dari kebijakan yang tak pernah memposisikan perempuan sebagai subjek utama. Masalah lain adalah tak banyak perempuan yang berani untuk bersuara tentang ketidakadilan struktural ini.
Hukum Indonesia yang Hanya Indah di Atas Kertas
Dari segi hukum, secara normatif kita punya banyak aturan yang melindungi perempuan nelayan. Hak-hak mereka jelas terjamin dan negara punya kewajiban untuk melindungi mereka sebagai pekerja maupun sebagai warga negara.
Pertama, UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
UU ini jelas ditetapkan untuk memberikan payung hukum demi menjamin hak, kepastian usaha, kesejahteraan, serta perlindungan bagi para nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam di Indonesia, termasuk mengatur kelembagaan dan pengakuan pekerjaan mereka.
Kedua, Pasal 28D dan 28G Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak atas perlindungan hukum dan rasa aman bagi semua warga negara, termasuk perempuan.
Ketiga, Konvensi CEDAW (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women), yang secara jelas mewajibkan negara untuk mengapus diskriminasi terhadap perempuan pedesaan, termasuk perempuan yang di sector tradisional seperti perikanan.
Melihat lengkapnya hukum yang dimiliki Indonesia secara kertas. Berarti, negara punya kewajiban yang cukup jelas untuk memenuhi hak-hak perempuan termasuk perempuan nelayan. Namun, di lapangan aturan ini berhenti sebagai dokumen yang tidak pernah menyentuh perempuan pesisir.
Ketidakpastian hukum terhadap perempuan di lapangan nyatanya masih banyak terjadi. Para perempuan nelayan masih harus bergelut di lapangan ketika tidak dianggap identitasnya sebagai nelayan, tak dilibatkan dengan dalam perencanaan ruang pesisir, tidak adanya jaminan keselamatan kerja, dan ruang kerja yang berubah ketika alam di rubah menjadi proyek pembangunan yang menyebabkan banyak kerusakan.
Saatnya Negara Mendengar Suara Perempuan Pesisir
Berdasarkan dengan uraian yang telah dibuat, penulis menyimpulkan bahw perempuan nelayan punya tuntutan yang tidak rumit. Para Perempuan Nelayan hanya ingin suaranya di dengar. Negara harus berani memulai untuk mendengarkan dan memberikan perempuan pengakuan.
Aksi lingkaran perahu di Demak hanya satu contoh dari banyaknya perempuan pesisir yang berusaha. Perlindungan pesisir harus dilakukan oleh negara secepat mungkin.
Negara harus memastikan para nelayan baik laki-laki ataupun perempuan harus mempunyai ruang aman untuk bekerja dan hidup. Laut yang menjadi sumber pendapatan utama mereka harus dilindungi oleh negara agar para perempuan tetap Berjaya.
Penulis berpendapat bahwa sudah saatnya negara datang bukan sebagai pendengar dan penonton yang baik, melainkan sebagai pelindung rakyatnya. Khususnya bagi mereka, para perempuan nelayan.
CEK BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS