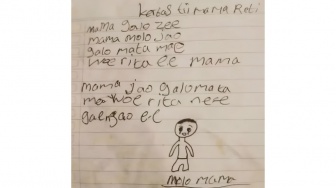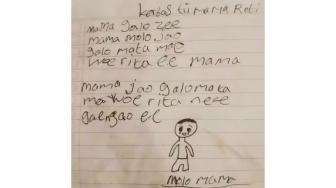Sobat Yoursay, pernah dengar diskusi buku Reset Indonesia yang dibubarkan aparat di Madiun?
Sekilas terlihat sepele. Tak ada demo. Tak ada kerusuhan. Hanya sekelompok orang yang ingin membahas isi buku.
Tapi justru di situlah masalahnya. Yang dipertaruhkan bukan satu acara, melainkan kebebasan berpikir.
Reset Indonesia bicara soal tanah yang dikuasai segelintir orang, generasi muda yang kian jauh dari rumah layak, masyarakat adat yang tersingkir oleh pariwisata premium, hingga warga Labuan Bajo yang kesulitan air bersih saat hotel-hotel mewah memamerkan kolam renang.
Ia juga mencatat perlawanan seorang nelayan yang menolak tambang emas demi lautnya. Semua itu bukan rahasia negara. Semua itu nyata, terjadi, dan dialami warga Indonesia sendiri.
Peristiwa pembubaran ini bahkan terjadi sebelum diskusi dimulai. Aparat pemerintah kecamatan dan kepolisian datang, meminta panitia menghentikan kegiatan, dan tidak membuka ruang dialog.
Alasan yang kemudian muncul berkisar pada persoalan administratif, katanya surat pemberitahuan dianggap mendadak dan tidak sesuai.
Namun, fakta bahwa tidak ada penjelasan rinci di lokasi, ditambah adanya larangan personal terhadap salah satu penulis, membuat publik bertanya-tanya.
Apakah benar ini hanya soal izin, atau ada ketakutan terhadap isi pembicaraan?
Sobat Yoursay, dalam negara demokrasi, kebebasan berpikir dan berekspresi bukanlah hadiah dari negara, melainkan hak warga. Diskusi buku, bedah gagasan, atau forum tukar pikiran adalah bagian dari hak tersebut.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 bahkan menegaskan bahwa diskusi termasuk dalam bentuk penyampaian pendapat yang tidak memerlukan izin khusus.
Artinya, ketika sebuah diskusi dibubarkan tanpa dasar hukum yang jelas, yang dilanggar bukan hanya prosedur, tetapi juga prinsip dasar kebebasan sipil.
Masalahnya bukan pada setuju atau tidak setuju dengan isi Reset Indonesia. Buku itu berisi laporan jurnalistik tentang ketimpangan sosial, konflik agraria, marginalisasi masyarakat adat, dan ironi pembangunan.
Isinya bisa diperdebatkan, dikritik, atau bahkan dibantah dengan data lain.
Tapi membungkam diskusi justru menutup ruang untuk perdebatan itu sendiri. Ketika negara atau aparat memilih menghentikan pembicaraan, maka publik akan menganggap kalau berpikir kritis itu berisiko.
Inilah yang membuat peristiwa di Madiun terasa mengkhawatirkan.
Panitia dan peserta mungkin berpikir dua kali sebelum menggelar diskusi serupa di masa depan. Penulis dan akademisi bisa memilih diam agar tidak berurusan dengan aparat. Dan warga biasa bisa merasa bahwa membicarakan persoalan publik bukan urusan mereka.
Sobat Yoursay, kebebasan berpikir bukan hanya soal hak berbicara di media sosial atau menyampaikan kritik di kolom komentar. Ia juga soal ruang aman untuk berdiskusi secara langsung, bertatap muka, dan bertukar argumen.
Negara mungkin masih punya pemilu, parlemen, dan pidato resmi, tetapi tanpa kebebasan berpikir, semua itu menjadi formalitas belaka.
Yang lebih ironis, negara sering mendorong warganya untuk lebih kritis, lebih cerdas, dan lebih aktif. Pendidikan mendorong siswa untuk berpikir analitis dan kampus diminta melahirkan lulusan yang berani berpendapat.
Namun di lapangan, ketika berpikir kritis benar-benar dipraktikkan di ruang publik, responsnya justru represi. Kontradiksi ini menimbulkan kebingungan, seolah berpikir kritis itu dianjurkan, tapi hanya sampai batas tertentu.
Pembubaran diskusi Reset Indonesia juga menunjukkan betapa rapuhnya pemahaman aparat terhadap kebebasan berpikir. Alih-alih melihat diskusi sebagai bagian dari kehidupan demokratis, ia justru diperlakukan sebagai potensi gangguan.
Padahal, diskusi tidak serta-merta mengancam stabilitas. Justru dengan membiarkan gagasan diperdebatkan secara terbuka, negara bisa mengetahui keresahan warga tanpa harus menunggu ledakan konflik.
Sobat Yoursay, ada kecenderungan berbahaya ketika negara lebih nyaman mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dipikirkan.
Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa pembatasan kebebasan berpikir selalu berujung pada stagnasi dan ketidakpercayaan publik.
Reformasi 1998 lahir salah satunya karena kebebasan berpikir dan berbicara terlalu lama ditekan. Ironis jika setelah puluhan tahun, pola serupa kembali muncul dengan wajah yang lebih halus.
Yang perlu ditegaskan, melindungi kebebasan berpikir bukan berarti membiarkan kekacauan.
Negara tetap punya kewenangan menjaga keamanan dan ketertiban. Namun kewenangan itu harus dijalankan dengan proporsional dan berbasis hukum, bukan dengan pendekatan sepihak yang mematikan ruang dialog.
Diskusi bisa diawasi, bukan dibubarkan. Dan perbedaan pendapat bisa difasilitasi, bukan justru ditekan.