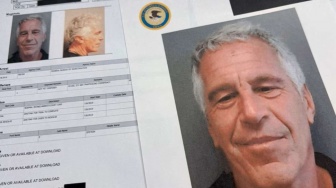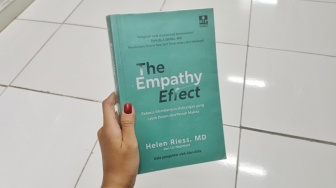Setiap kali abrasi menggerus rumah warga pesisir, narasi yang muncul hampir selalu sama bencana alam. Kata itu terdengar netral, seolah kerusakan pantai adalah peristiwa tak terhindarkan, datang begitu saja dari murka laut.
Namun, pelabelan ini justru menutupi persoalan yang lebih mendasar. Abrasi bukan semata urusan alam, melainkan hasil dari rangkaian keputusan manusia keputusan kebijakan yang abai, salah arah, dan kerap mengorbankan ekologi demi kepentingan jangka pendek.
Mangrove yang Hilang, Pesisir yang Runtuh
Laut memang bergerak, ombak memang menghantam, tetapi pantai tidak serta-merta hilang begitu saja. Selama berabad-abad, garis pantai bertahan berkat ekosistem alami yang bekerja sebagai benteng.
Mangrove, padang lamun, dan terumbu karang berfungsi meredam gelombang, menahan sedimen, dan menjaga keseimbangan pesisir. Ketika ekosistem ini rusak, laut hanya melakukan apa yang secara alami ia lakukan mengambil kembali ruangnya.
Sayangnya, hilangnya mangrove sering dianggap kerusakan biasa, bukan kesalahan struktural. Penebangan mangrove untuk tambak, permukiman, atau proyek infrastruktur kerap dilegalkan dengan dalih pembangunan dan peningkatan ekonomi.
Tata Ruang yang Membelakangi Ekologi
Dalam hitungan tahun, keuntungan diraih, tetapi dampaknya bertahan puluhan tahun. Ketika abrasi datang, masyarakat pesisir diminta beradaptasi, seolah mereka yang lalai menjaga alam, padahal keputusan tersebut sering diambil jauh dari ruang hidup mereka.
Masalah berikutnya adalah tata ruang pesisir yang abai terhadap daya dukung lingkungan. Perencanaan wilayah sering memandang pesisir sebagai lahan kosong yang siap dimanfaatkan, bukan sebagai ekosistem rapuh yang memiliki batas.
Zonasi dibentuk tanpa kajian ekologis yang memadai, atau jika ada, kerap diabaikan saat berhadapan dengan kepentingan investasi. Akibatnya, bangunan berdiri terlalu dekat dengan laut, aliran sedimen terganggu, dan keseimbangan pesisir runtuh perlahan.
Ketika abrasi terjadi, solusi yang ditawarkan pun sering bersifat tambal sulam. Tanggul beton dibangun sebagai simbol kehadiran negara. Namun, beton tidak menggantikan fungsi mangrove. Ia mungkin menahan ombak untuk sementara, tetapi juga mengubah arus dan memperparah abrasi di titik lain.
Alih-alih menyelesaikan masalah, pendekatan ini justru memindahkan kerusakan ke wilayah pesisir yang lain. Sekali lagi, kebijakan jangka pendek mengalahkan pemulihan ekologis jangka panjang.
Investasi menjadi faktor kunci lain yang mempercepat abrasi. Proyek reklamasi, pelabuhan, pariwisata, dan industri pesisir sering dipromosikan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi.
Namun, pertumbuhan bagi siapa? Dalam banyak kasus, masyarakat pesisir kehilangan ruang hidup dan perlindungan alamnya, sementara keuntungan mengalir ke segelintir pihak. Ketika investasi mengorbankan ekologi, abrasi bukan efek samping, melainkan konsekuensi yang dapat diprediksi.
Pelabelan abrasi sebagai bencana alam juga memiliki dampak politis. Ia mengaburkan tanggung jawab. Jika abrasi dianggap takdir, maka tidak ada yang perlu disalahkan. Tidak ada kebijakan yang perlu dievaluasi, tidak ada izin yang perlu ditinjau ulang.
Padahal, tanpa keberanian untuk mengakui bahwa abrasi adalah bencana kebijakan, kita hanya akan mengulang kesalahan yang sama, dengan korban yang terus bertambah.
Masyarakat pesisir sering kali berada di posisi paling rentan dalam situasi ini. Mereka kehilangan rumah, lahan, dan mata pencaharian, tetapi jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Suara mereka tenggelam oleh bahasa teknokratis dan janji investasi.
Ironisnya, mereka pula yang kemudian dituntut untuk paling cepat beradaptasi, seolah kerusakan bukan hasil dari kebijakan yang meminggirkan mereka.
Sudah saatnya cara pandang kita diubah. Mengatasi abrasi tidak cukup dengan proyek fisik dan bantuan darurat. Ia menuntut perubahan struktural seperti pemulihan mangrove sebagai prioritas, tata ruang pesisir yang berbasis ekologi, serta evaluasi serius terhadap investasi yang merusak. Lebih dari itu, masyarakat pesisir harus diposisikan sebagai subjek, bukan sekadar penerima dampak.
Abrasi akan terus terjadi selama kebijakan tetap memandang alam sebagai objek yang bisa dikompromikan. Menyebut abrasi sebagai bencana alam mungkin terasa lebih nyaman, tetapi kenyamanan itu dibayar mahal oleh mereka yang hidup di pesisir.
Mengakui abrasi sebagai bencana kebijakan adalah langkah awal yang tidak mudah, tetapi penting, jika kita benar-benar ingin menghentikan garis pantai yang terus mundur dan ketidakadilan yang menyertainya.