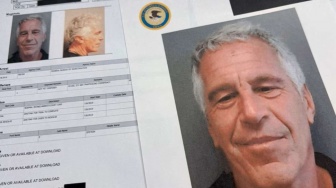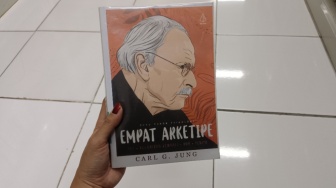Aku selalu mengira perubahan besar datang dengan suara gemuruh seperti petir yang membelah langit atau gelombang yang menghantam karang tanpa ampun.
Nyatanya, perubahan itu datang dalam bentuk yang paling sederhana, kalimat pendek dari ayahku, diucapkan dengan suara pelan di sebuah sore yang biasa saja.
Tidak ada tepuk tangan, tidak ada saksi, tidak ada firasat apa pun. Namun kalimat itu, yang tampak kecil dan nyaris sepele, diam-diam mengubah seluruh hidupku.
Aku tumbuh di rumah sederhana di pinggir kota, rumah yang catnya mudah mengelupas dan pagar besinya selalu berderit setiap kali dibuka.
Ayahku bukan orang berpendidikan tinggi. Tangannya kasar oleh kerja, punggungnya yang kekar kini sedikit membungkuk oleh waktu.
Namun, dari semua orang yang pernah kutemui, ayah adalah manusia dengan hati paling lapang, sabar dan selalu berpikir positif pada apapun.
Suatu hari, ketika aku masih duduk di bangku sekolah dasar, aku pulang dengan wajah kesal.
Temanku meminjam pensil baruku dan mengembalikannya dalam keadaan patah. Aku marah, merasa dirugikan, merasa dunia berlaku tidak adil kepadaku.
Dengan suara bergetar, aku mengadu pada ayah, berharap ia akan membelaku dan mengutuk ketidakadilan itu.
Ayah hanya tersenyum kecil.
Ia mengambil pensil itu, memperhatikannya sejenak, lalu berkata,
“Nak, berbuat baiklah pada siapa pun, bahkan pada orang yang tidak berbuat baik padamu. Kebaikan itu tidak pernah hilang. Ia akan terus berputar.”
Aku tidak sepenuhnya mengerti. Bagiku saat itu, kebaikan adalah transaksi, aku baik padamu, kau juga harus baik padaku.
Lebih dari itu terasa seperti kekalahan. Namun, ayah tidak memaksaku mengerti.
Ia hanya mengulang satu hal yang sama, berulang-ulang sepanjang hidupku, dalam berbagai versi dan momen jangan lelah menjadi orang baik.
Tahun-tahun telah berlalu.
Aku tumbuh dengan segala luka kecil yang biasa dialami manusia. Dikhianati teman, jatuh bangun mengejar mimpi hingga diabaikan lingkungan.
Ada masanya ketika aku lelah, ketika aku ingin membalas dunia dengan cara yang sama kerasnya. Namun setiap kali aku hampir menyerah pada kepahitan, wajah ayah muncul dalam ingatanku. Ia sosok yant tenang, sederhana, tanpa dendam.
Saat remaja, aku menjadi relawan di sebuah panti asuhan kecil. Tidak ada bayaran, tidak ada pujian. Aku hanya membersihkan, mengajar, dan mendengarkan cerita-cerita anak-anak yang hidupnya jauh lebih berat dari hidupku.
Awalnya aku melakukannya sekadar untuk mengisi waktu. Namun perlahan, aku menyadari sesuatu yang aneh setiap kali aku pulang dari sana, hatiku terasa lebih ringan, seolah aku telah menemukan sesuatu yang hilang tanpa pernah kusadari kehilangannya.
Ayah melihat perubahan itu.
“Kamu mulai mengerti,” katanya suatu malam.
Aku tersenyum, meski masih belum sepenuhnya paham apa maksudnya.
Ketika aku dewasa dan mulai bekerja, ajaran itu diuji dengan cara yang lebih kejam. Di kantor pertamaku, aku bukan siapa-siapa. Aku sering diberi tugas tambahan tanpa pengakuan, ide-ideku diambil orang lain, dan namaku jarang disebut.
Ada hari-hari ketika aku pulang dengan mata panas dan dada sesak.
Namun aku tetap memilih bersikap baik pada semua orang.
Aku membantu rekan kerja yang kesulitan, bahkan ketika mereka tidak pernah membantuku.
Aku menyelesaikan tugasku dengan jujur, meski jalan pintas selalu menggoda. Aku menolak ikut dalam gosip dan intrik yang bisa membuatku naik lebih cepat.
Banyak orang menganggapku bodoh dan tidak tahu teknologi.
“Dunia ini bukan tempat orang baik bertahan,” kata mereka.
"Jujur akan terus menyiksamu, sesekali boleh lakukan jalan pintas" kata mereka lagi.
Aku hampir mempercayainya.
Sampai suatu hari, atasan besar dari kantor pusat datang melakukan evaluasi. Tanpa kuduga, namakulah yang dipanggil. Bukan karena aku paling ambisius atau paling vokal, tetapi karen menurutnya aku, pekerja yang paling bisa dipercaya.
Aku terdiam lama saat itu, menyadari bahwa kebaikan yang kutanam diam-diam ternyata tumbuh, meski aku tidak melihatnya.
Ayah tersenyum saat aku menceritakannya.
“Kebaikan tidak pernah terburu-buru,” katanya. “Ia datang tepat waktu.”
Keberuntungan dalam hidupku mulai bermunculan dalam bentuk-bentuk yang tidak selalu besar, tetapi selalu bermakna.
Aku bertemu orang-orang yang membantuku tanpa pamrih, kesempatan datang di saat-saat genting, dan bahkan kegagalan pun selalu menyisakan pelajaran, bukan kehancuran.
“Jika suatu hari kamu merasa lelah,” katanya pelan, “ingat satu hal jangan biarkan dunia mengubah hatimu menjadi keras.”
Aku menangis. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar memahami betapa besar makna ajarannya.
Benar saja, kebaikan itu terus berputar. Setiap perbuatan pasti akan kembali kepada diri sendiri.
Aku telah membuktikannya, di masa paling gelap yang pernah kualami, semua kebaikan yang pernah kutanam meski sekecil remahan itu kembali padaku dalam bentuk paling manusiawi pelukan, doa, kehadiran orang-orang yang tidak membiarkanku sendirian. Aku sadar, aku tidak sedang beruntung. Aku sedang menuai.
Kini, setiap kali aku berbuat baik sekecil apa pun aku melakukannya bukan untuk imbalan.
Aku melakukannya karena itulah caraku menjaga ayah tetap hidup di dalam diriku. Dalam senyum orang asing yang kutolong, dalam kesabaran yang kupilih saat dunia memancing amarah, dalam kejujuran yang kupelihara meski sulit.
Aku belajar bahwa keberuntungan bukan tentang menang lotre atau takdir yang murah hati. Keberuntungan adalah memiliki hati yang tetap lembut di dunia yang keras. Keberuntungan adalah menemukan makna dalam hal-hal kecil.
Dan jika hari ini hidupku terasa penuh oleh kebaikan, aku tahu itu bukan kebetulan. Itu adalah gema dari satu kalimat sederhana, diucapkan ayahku bertahun-tahun lalu, satu kalimat kecil yang diam-diam mengubah seluruh hidupku.