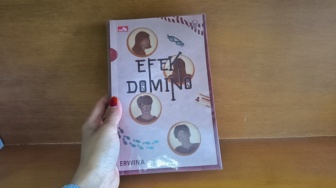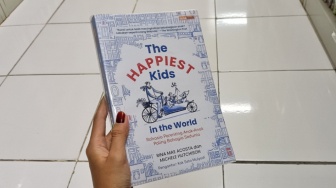Di saat dunia berlomba menyederhanakan layanan publik dan memperpanjang masa berlaku paspor hingga 10 tahun. Indonesia justru diajak melangkah mundur. Pelan, tapi pasti.
Ketika negara-negara maju berbicara efisiensi, integrasi data, dan kemudahan mobilitas warganya, kita malah mewacanakan kembali paspor 5 tahun dengan alasan yang nyaris tak relevan dengan praktik keamanan modern.
Ini bukan sekadar perbedaan kebijakan, tapi tanda kemunduran cara berpikir. Saat dunia maju dengan data dan teknologi, kita sibuk mengulang urusan yang seharusnya sudah selesai.
Ucapan asbun (alias asal bunyi) bukanlah hal yang normal bagi seseorang yang memegang jabatan kursi pemerintahan. Tapi di realita sekarang, kita justru kerap mendapati para menteri dan pejabat setaraf lembaga eksekutif dan legislatif bicara asal yang tak sepantasnya di ruang publik.
Dalam praktik global hari ini, satu hal sudah menjadi standar: paspor orang dewasa berlaku 10 tahun. Amerika Serikat, negara-negara Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, Australia dan masih banyak lagi jika di daftar, panjang dan konsisten. Bahkan di banyak negara, warga diberi opsi memilih masa berlaku 5 atau 10 tahun. Indonesia sendiri sejak 2022 sudah mengikuti arus global ini, sebuah langkah maju yang diapresiasi karena mempermudah warga dan menyelaraskan sistem administrasi dengan praktik internasional.
Namun publik dikejutkan oleh wacana baru dari seorang menteri yang justru ingin mengembalikan masa berlaku paspor Indonesia menjadi 5 tahun. Alasannya terdengar sederhana, bahkan problematik: “hanya orang tertentu yang diberkati Tuhan mukanya tidak berubah.” Pernyataan ini bukan hanya mengundang tanya, tetapi juga menunjukkan pemahaman yang dangkal tentang fungsi paspor modern.
Paspor bukan sekadar kartu identitas berbasis wajah. Ia adalah dokumen perjalanan yang didukung biometrik canggih: chip elektronik, sidik jari, pemindaian wajah berbasis algoritma, dan sistem verifikasi lintas negara. Dunia tidak lagi bergantung pada “muka berubah atau tidak berubah”. Jika demikian logika yang dipakai, maka hampir semua negara maju seharusnya sudah kembali ke paspor 3–5 tahun. Faktanya, tidak satu pun melakukannya.
Mengembalikan masa berlaku paspor menjadi 5 tahun berarti satu hal yang pasti: beban administratif meningkat drastis. Warga harus lebih sering mengurus paspor, antrean makin panjang, biaya publik meningkat, dan kapasitas layanan keimigrasian kembali tersedot hanya untuk pekerjaan berulang. Ini bukan efisiensi, melainkan kemunduran. Terlebih di negara dengan jumlah penduduk besar seperti Indonesia, kebijakan ini akan berdampak luas dan langsung ke kehidupan sehari-hari.
Pertanyaannya wajar muncul: untuk apa kebijakan ini dibuat? Jika alasannya keamanan, argumen tersebut lemah. Sistem keamanan paspor modern tidak bergantung pada masa berlaku pendek, melainkan pada teknologi dan integrasi data.
Jika alasannya pembaruan teknologi seperti paspor polikarbonat, maka solusinya jelas: percepat pengadaan dan transisi, bukan memaksa seluruh warga mengganti paspor lebih sering.
Keganjilan tidak berhenti di situ. Menteri lain bahkan melontarkan ide agar nomor paspor berlaku seumur hidup. Ini terdengar futuristik, tetapi justru bertentangan dengan praktik keamanan internasional.
Di banyak negara, nomor paspor memang bisa konsisten, namun akan diganti ketika ada perubahan signifikan—seperti data identitas, kewarganegaraan, atau risiko keamanan. Nomor yang sama selamanya justru meningkatkan risiko pemalsuan dan penyalahgunaan identitas, terutama jika terjadi kebocoran data.
Jika benar alasan utama kebijakan ini adalah keamanan, maka logikanya terbalik. Nomor paspor statis + masa berlaku pendek bukan kombinasi yang aman, melainkan membingungkan. Dunia bergerak ke arah efisiensi, integrasi data, dan pelayanan publik yang ramah warga. Indonesia justru diajak melangkah mundur, sendirian, dengan alasan yang sulit dipertanggungjawabkan secara teknis.
Bandingkan dengan Malaysia, yang paspornya dikenal kuat, efisien, dan diakui luas secara internasional. Atau dengan negara-negara lain yang fokus memperkuat sistem, bukan mempersulit warganya. Kebijakan publik seharusnya mempermudah hidup warga, bukan menambah urusan yang sebenarnya sudah selesai.
Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar masa berlaku paspor, tetapi kualitas pengambilan kebijakan. Ketika dunia bergerak maju, publik berhak bertanya: apakah negara sedang memperbaiki sistem, atau sekadar menciptakan proyek baru dengan bungkus keamanan? Jika jawabannya tidak jelas, maka kritik bukan hanya wajar, tetapi perlu.
CEK BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS