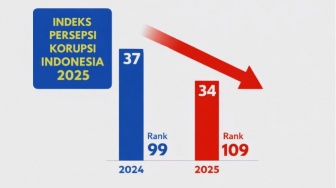Dulu, saya adalah orang yang paling takut membayangkan kematian orang terdekat. Dalam kepala saya, kehilangan berbentuk sesuatu yang sangat horor, sangat menakutkan.
Saya membayangkan diri saya akan meraung-raung di lantai, tidak nafsu makan berhari-hari, hingga mungkin kehilangan akal sehat karena dunia mendadak runtuh.
Saya juga sempat berpikir bahwa cara terbaik untuk sembuh dari duka adalah dengan “menghapus” jejak: jangan melihat fotonya, jangan memutar lagu kesukaannya, dan, kalau bisa, jangan menyebut namanya dulu agar luka tidak menganga kembali. Saya pikir, duka adalah sebuah garis linear: kita akan merasa sakit yang sangat dalam, lalu seiring berjalannya waktu, kita dipaksa lupa agar bisa melanjutkan hidup.
Namun, saat saya benar-benar berada di titik itu, ketika orang yang saya cintai pergi untuk selamanya, semua teori yang saya bangun di kepala ternyata meleset jauh.
Saat Kenangan Justru Menjadi “Oksigen”
Begitu duka itu menetap di rumah saya, yang muncul bukan hanya rasa sakit yang menyiksa, melainkan rindu yang luar biasa aneh. Kini, saya justru suka berlama-lama melihat fotonya. Saya juga gemar mendengarkan lagu yang dulu sangat ia sukai. Saya menikmati saat orang-orang bercerita tentangnya. Bagi saya, itu adalah cara untuk tetap merasa terhubung.
Dengan terus terhubung, saya merasa ia tetap di sini, dalam bentuk yang lain. Mengingat segala hal tentangnya, termasuk kepergiannya, ternyata tidak selalu membuat saya sedih. Kadang justru menghadirkan rasa hangat yang tak terduga. Rasa kehilangan dan sesak itu tetap ada, tetapi wujudnya berubah menjadi kenangan yang ingin saya putar berkali-kali. Karena kini, hal yang paling menyedihkan bagi saya adalah kemungkinan untuk melupakannya sama sekali.
Mengapa Duka Kita Tidak Pernah Sama?
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: mengapa respons duka seseorang bisa berbeda dengan yang lain?
Secara psikologis, apa yang saya alami sebenarnya sangat manusiawi. Continuing Bonds Theory (Teori Ikatan Berkelanjutan) yang diperkenalkan oleh Klaas, Silverman, dan Nickman mematahkan anggapan lama bahwa kita harus “melepaskan” (detachment) orang yang meninggal agar bisa sembuh.
Sebaliknya, teori ini menyatakan bahwa mempertahankan ikatan emosional melalui kenangan, benda, atau doa justru merupakan cara sehat untuk beradaptasi dengan kehilangan. Kita tidak sedang terjebak di masa lalu; kita hanya membawa cinta itu ke masa depan dalam bentuk yang baru.
Namun, setiap orang memiliki “warna” duka yang berbeda. Menurut J. William Worden dalam Grief Counseling and Grief Therapy, proses ini dipengaruhi banyak faktor, mulai dari cara seseorang meninggal, tingkat kedekatan emosional, hingga dukungan sosial yang tersedia. Ada yang membutuhkan waktu panjang dalam kesunyian.
Ada pula yang perlu berbicara terus-menerus untuk merasa lega. Semuanya valid. Tidak ada duka yang salah, dan tidak ada cara menangis yang paling benar.
Merayakan Kehadiran dalam Ketiadaan
Kini saya memahami bahwa duka tidak selalu tentang air mata yang terus-menerus. Kadang, duka adalah tentang cara kita mencintai seseorang yang sudah tidak bisa lagi kita sentuh. Kehilangan memang meninggalkan lubang di hati. Namun, kita tidak harus terkubur di dalamnya. Kita bisa memilih menjadikannya taman, tempat merawat kenangan indah yang pernah ada.
Pada akhirnya, kita belajar bahwa mencintai seseorang yang telah pergi bukan berarti berhenti melangkah. Kita hanya sedang belajar berjalan sambil membawa mereka dalam doa dan cerita yang tidak pernah benar-benar selesai.
Sebab, orang yang kita cintai tidak pernah benar-benar pergi selama namanya masih menetap dalam ingatan dan detak jantung kita.
Apakah kamu pernah merasakan duka yang justru membuatmu ingin terus mengenang, atau kamu tipe yang membutuhkan waktu dalam sunyi?