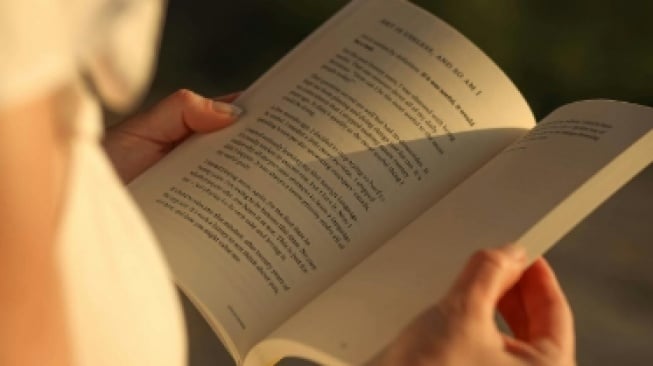Istilah "rabun membaca dan lumpuh menulis" bukan sekadar jargon puitis dari Taufik Ismail. Bagi penyair angkatan 66 ini, kalimat tersebut adalah sebuah diagnosis medis atas penyakit kronis yang diderita dunia pendidikan kita. Selama puluhan tahun, beliau dengan lantang menyuarakan keprihatinan tentang bagaimana sekolah-sekolah di Indonesia meluluskan generasi yang "buta" terhadap membaca buku dan "lumpuh" dalam menuangkan pikiran alias menulis.
Taufik Ismail pernah menulis membandingkan kewajiban membaca buku di SMA berbagai negara. Di saat siswa SMA di Amerika Serikat, Jerman, atau Jepang diwajibkan membaca 15 hingga 30 judul buku sastra hingga lulus, siswa di Indonesia secara kurikulum formal tercatat nol buku. Bisa dibandingkan hasil dari kurikulum kita ini.
Membaca dan menulis adalah dua sisi dari satu koin. Seseorang yang tidak membaca tidak akan memiliki "tabungan" kosakata, struktur kalimat, maupun kedalaman ide untuk menulis. Inilah yang disebut Taufik Ismail sebagai "lumpuh menulis".
Ketika tangan dipaksa menulis tanpa asupan bacaan yang cukup, maka yang lahir adalah berbagai kekacauan tulisan. Kita hari ini melihat kekacauan tulisan dalam berbagai bentuk. Plagiarisme yang begitu marak, bahkan di kalangan akademisi. Karena tidak punya ide sendiri, menyontek menjadi jalan pintas. Tulisan yang dangkal, di mana hanya menyentuh permukaan, tanpa analisis atau emosi yang kuat. Menulis dianggap sebagai beban berat, bukan sarana berekspresi.
Mengapa opini ini relevan sekarang? Meski Taufik Ismail sudah menyuarakan hal ini sejak era 90-an, relevansinya justru menguat di era digital. Memang benar, hari ini orang "membaca" lebih banyak lewat media sosial, namun yang dibaca adalah fragmen-fragmen pendek yang sering kali dangkal. Kita mengalami banjir informasi, namun kekeringan literasi mendalam .
Kondisi "rabun membaca" bertransformasi menjadi "gagal fokus", di mana kemampuan membaca buku tebal secara tuntas digantikan oleh skrol layar tanpa henti. Kritik Taufik Ismail adalah sebuah ajakan untuk melakukan revolusi di bangku sekolah. Kita tidak bisa mengharapkan bangsa yang besar jika generasinya hanya mengenal sastra lewat ringkasan di internet.
Solusinya sederhana namun menantang, kembalikan buku ke tangan siswa. Wajibkan kembali program wajib membaca buku dan resensi buku, seperti zaman kolonial dulu. Meski terdengar kuno, kurikulum ini banyak melahirkan tokoh yang gemar membaca dan tulisan berkualitas. Sebut saja Sukarno, Mohammad Hatta, Mohammad Natsir, Haji Agus Salim, Mohammad Yamin, dan lainnya.
Di tengah kondisi "rabun membaca dan lumpuh menulis", dunia pendidikan kita dihantam oleh gelombang AI seperti ChatGPT atau Gemini. Kehadiran teknologi ini bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi, AI bisa menjadi asisten yang luar biasa. Namun, jika tidak disikapi dengan kritis, AI justru berisiko memperparah masalah lemahnya literasi.
Esensi dari membaca adalah proses dialog internal. Saat kita membaca buku, otak bekerja mengolah simbol menjadi imajinasi dan pemahaman. Namun, kehadiran AI melalui fitur ringkasan otomatis (AI summarizer) menawarkan jalan pintas yang berbahaya.
Ketika seseorang meminta AI meringkas sebuah buku, ia tidak lagi sedang "membaca". Ia hanya sedang menelan kunyahan mesin. Bahayanya adalah hilangnya kemampuan untuk menangkap nuansa, nada, dan kompleksitas argumen. Jika proses ini terus berlanjut, "rabun membaca" akan berevolusi menjadi ketumpulan kognitif, di mana manusia hanya mampu menyerap informasi dalam bentuk butiran poin-poin tanpa kedalaman.
Menulis adalah cara kita menguji sejauh mana kita memahami sesuatu. Dalam proses menulis, kita dipaksa untuk jujur pada pikiran sendiri. AI, dengan segala kecanggihannya, mampu menghasilkan teks yang tata bahasanya sempurna dalam hitungan detik. Namun, teks tersebut tidak memiliki pengalaman empiris.
Otot berpikir yang tidak dilatih untuk merangkai kalimat akan menyusut . Kita menjadi terlalu bergantung pada prompt daripada ide orisinal. AI bekerja berdasarkan probabilitas statistik. Hal ini cenderung menghasilkan tulisan yang seragam, sehingga membunuh kreativitas dan gaya bahasa unik yang menjadi ciri khas kemanusiaan. Jika semua orang menggunakan AI untuk menulis pesan, esai, hingga opini, maka literasi tidak lagi menjadi sarana komunikasi antarmanusia, melainkan pertukaran data antar-mesin.
Ancaman terbesar AI bagi literasi adalah ilusi pengetahuan. Dengan bantuan AI, seseorang bisa menghasilkan karya tulis yang terlihat cerdas tanpa benar-benar memahami isinya. Ini adalah bentuk penipuan intelektual paling mutakhir. Kita menciptakan generasi yang merasa tahu segalanya karena bisa memproduksi teks apa pun, padahal isi kepalanya kosong.
Oleh karena itu, lebih baik membaca buku daripada membaca hasil AI. Jika hal ini terus tidak diperhatikan, hasil pendidikan Indonesia bisa makin parah. Semoga para pemangku kepentingan sadar dengan masalah ini.