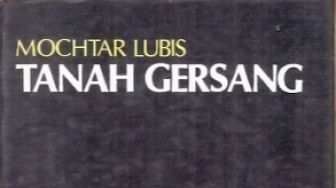Di koridor jembatan penyeberangan yang menghubungkan stasiun kereta dengan pusat perbelanjaan mewah, Pak Damar terlihat bagai makhluk aneh. Di kiri dan kanannya, iklan-iklan raksasa memamerkan jam tangan seharga rumah dan wajah model yang terlalu sempurna untuk menjadi nyata.
Sementara itu, Pak Damar, dengan kemeja flanel yang warnanya sudah memudar menjadi abu-abu dan celana kain yang bolong di lutut, duduk bersila memeluk sebuah gitar akustik tua. Suara gitarnya kadang diabaikan, dianggap tak berarti.
Pak Damar buta sejak lahir. Baginya, dunia bukan tentang cahaya dan bayangan, melainkan tentang tekstur suara. Baginya, jembatan penyeberangan ini adalah sebuah aula konser raksasa di mana setiap orang yang lewat adalah instrumen musik yang sedang dimainkan oleh nasib. Permainan yang kadang dibenci oleh orang lain, meski suara permainan itu sangat indah. Ia tidak butuh melihat wajah untuk mengetahui siapa yang sedang berjalan di depannya. Ia membaca langkah kaki.
Langkah kaki menjadi bahasa paling jujur di dunia. Seseorang bisa memalsukan senyum di wajahnya atau menyemprotkan parfum mahal untuk menutupi bau keringat kemiskinan, tetapi mereka tidak bisa memalsukan cara kaki mereka menghantam bumi. Sore itu, jam pulang kantor sedang mencapai puncaknya. Pak Damar mendengar simfoni yang riuh.
Ada langkah-langkah sepatu pantofel yang terburu-buru, bunyinya tajam dan berwibawa. Tuk, tuk, tuk. Itu adalah langkah orang-orang yang merasa waktu adalah uang, namun sebenarnya mereka adalah budak dari jam tangan mereka sendiri. Kasihan. Ada juga langkah sepatu kets anak muda yang menyeret, bunyinya malas dan santai. Shreek, shreek. Jalan tanpa tekanan dan merasa bebas, padahal mereka sekumpulan orang yang belum merasa bertanggung jawab terhadap hidup mereka. Biarlah.
Lalu, di antara ribuan langkah yang tumpang-tindih itu, telinga Pak Damar menangkap sebuah musik yang unik. Wajah Pak Damar yang tadinya tersenyum menikmati musik, tiba-tiba berubah menjadi serius. Itu adalah langkah sepatu hak tinggi milik seorang wanita. Namun, suaranya tidak memiliki irama stakato yang tegas seperti biasanya wanita karier yang percaya diri. Langkah ini goyah. Ada jeda yang terlalu lama di antara setiap pijakan.
Pijakannya berat di bagian tumit, menandakan pemiliknya sedang membawa beban emosional yang luar biasa, seolah-olah seluruh gravitasi dunia sedang menekan pundaknya. Langkah itu berhenti tepat tiga meter di dekat Pak Damar di atas jembatan. Hening.
Pak Damar tidak segera memetik gitarnya untuk meminta receh. Ia justru meletakkan telapak tangannya di atas senar, membungkam dengung gitarnya. Ia ingin mendengarkan hening yang dibawa wanita itu. Keheningan itu terasa dingin, seperti kabut yang muncul sebelum badai. Pak Damar mendengar helaan napas yang gemetar, jenis napas yang ditarik dalam-dalam dan ditahan agar seseorang tidak meledak dalam tangisan di depan umum.
Jemari Pak Damar mulai bergerak. Ia tidak memainkan lagu pop yang sedang viral. Ia memetik nada-nada yang rendah dan lambat, sebuah melodi yang merambat seperti air yang tenang. Suaranya yang serak dan parau mulai melantunkan sebuah bait yang ia ciptakan sendiri di kepalanya dalam sekejap.
“Jangan berpikir terlalu cepat, Nona. Bumi tidak akan lari ke mana-mana. Jika hatimu gundah gulana, ingat harga nyawa lebih dari kencana. Masalah bisa jadi hanya fatamorgana.”
Suara petikan gitar itu bergema di antara dinding-dinding beton jembatan. Wanita itu tetap diam, namun Pak Damar bisa merasakan pergeseran udara. Ia mendengar suara tas tangan yang diletakkan di lantai semen dengan kasar. Isak tangis itu akhirnya pecah. Awalnya pelan, lalu berubah menjadi sedu sedan yang menyesakkan. Di tengah belasan orang yang berjalan melintasi mereka tanpa peduli, di sana, di atas jembatan yang bergetar karena arus lalu lintas di bawahnya, dua orang asing terhubung melalui sebuah lagu.
“Kenapa Bapak tahu saya mau melompat dari jembatan?” tanya wanita itu di sela tangisnya. Suaranya terdengar seperti kaca yang baru saja pecah. “Saya baru saja keluar dari rumah sakit. Ibu saya... mereka bilang umurnya tidak lama lagi. Dan saya bahkan tidak punya uang untuk membayar obatnya bulan depan. Saya ingin menyerah, saya sudah tidak kuat lagi.”
Pak Damar tersenyum, sebuah senyum yang tulus meski matanya tetap menatap hampa ke depan. “Saya tidak tahu urusanmu, Nak. Tapi kaki tidak pernah berbohong. Langkahmu tadi terdengar seperti seseorang yang menyerah. Dan jembatan ini, meski tinggi, bukan tempat yang baik untuk itu.”
Pak Damar kembali memetik gitarnya. Kali ini, ia mengubah nadanya menjadi lebih terang dan riang. Ia berpindah ke kunci mayor yang memberikan kesan harapan. Melodinya mendaki, sedikit demi sedikit, seolah-olah sedang menuntun seseorang keluar dari lubang yang gelap. Cahaya.
“Tolong Nona dengarkan,” kata Pak Damar sambil terus bermain. “Dunia ini sering kali terasa gelap. Itu hanya sekejap. Cahaya pasti datang mendekap. Harapan datang dengan berderap. Kau sangat kuat dan sigap. Hatimu hanya terlelap. Sejatinya senyummu bagai permata berkilap.”
Wanita itu terdiam cukup lama. Pak Damar mendengar suara tisu yang ditarik dari dalam tas, suara napas yang mulai teratur, dan akhirnya, suara ritsleting tas yang ditutup. Ia langsung dalam keadaan tenang. Lega.
“Terima kasih, Pak,” bisik wanita itu. Pak Damar mendengar bunyi koin yang jatuh ke dalam kotak gitarnya, disusul oleh bunyi kertas yang halus—selembar uang yang nilainya cukup besar untuk makan Pak Damar selama seminggu.
“Simpan uangmu, Nak,” kata Pak Damar lembut. “Beli sesuatu yang hangat untuk ibumu. Doamu jauh lebih berharga untuk senar gitar saya daripada uang itu.”
Wanita itu sempat ragu, namun ia mengambil kembali uangnya. Sebelum pergi, ia menyentuh lengan Pak Damar sekilas. “Siapa nama Bapak?”
“Hanya seorang pengamen yang tidak ingin ada musik yang berhenti terlalu cepat,” jawabnya sambil tersenyum.
Wanita itu berdiri. Pak Damar mendengarkan langkah kakinya lagi. Kali ini, bunyinya berbeda. Masih pelan, namun setiap pijakannya kini memiliki ritme. Tidak ada lagi seretan yang ragu. Langkah itu terdengar seperti seseorang yang telah menemukan kembali dirinya. Bahagia.