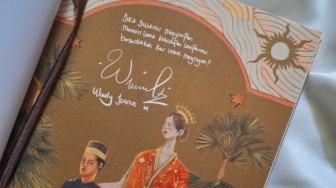Ayah di Indonesia itu makhluk unik. Ia jarang benar-benar pergi, tetapi juga jarang benar-benar ada. Pagi hari berangkat sebelum anak bangun, pulang saat anak sudah menguap. Lengkap secara administrasi, sah secara biologis, tetapi absen secara emosional. Kalau ayah adalah sinyal Wi-Fi, batangnya penuh, tetapi koneksinya putus-putus.
Sejak lama, ayah diposisikan sebagai tulang punggung keluarga. Sebuah metafora yang terdengar gagah, padahal implikasinya sadis. Tulang punggung itu tugasnya menopang, bukan dipijat. Kalau pegal, ya, salah sendiri. Maka, ayah pun bekerja dan terus bekerja karena berhenti sebentar saja bisa dianggap gagal menjalankan kodrat.
Mayoritas ayah Indonesia hidup di sektor informal. Mereka bukan pekerja kantoran dengan jam pulang yang bisa diprediksi dan cuti yang bisa direncanakan. Mereka adalah pedagang, buruh harian, sopir, tukang, dan segala profesi yang satu hari libur artinya satu hari tidak makan. Dalam hidup seperti ini, waktu bersama anak bukan soal niat baik, melainkan soal keberanian mengambil risiko ekonomi.
Lalu, datanglah negara dengan ide brilian bernama Gerakan Ayah Mengambil Rapor. Judulnya keren, kesannya progresif, dan sangat layak dijadikan bahan siaran pers. Negara tampak seperti baru menemukan fakta mengejutkan: “Oh, ternyata ayah juga orang tua.” Sayangnya, penemuan ini datang tanpa bonus kebijakan pendukung.
Bagi ayah kelas menengah, mengambil rapor cuma soal parkir dan tanda tangan. Bagi ayah sektor informal, itu adalah dilema eksistensial: datang ke sekolah atau tetap mencari nafkah. Negara, dengan santainya, menganggap kehadiran sebagai kewajiban moral tanpa pernah menghitung ongkos riilnya. Padahal, bagi ayah-ayah ini, satu jam absen bisa berarti satu piring nasi lenyap dari meja.
Akhirnya, fatherless pun disederhanakan menjadi soal ayah yang kurang peduli. Padahal, banyak ayah justru terlalu peduli pada satu hal: bertahan hidup. Mereka diperas oleh sistem ekonomi yang tidak ramah keluarga, lalu diminta tetap hangat, komunikatif, dan reflektif di rumah. Ayah dituntut menjadi figur emosional setelah seharian diperlakukan seperti mesin produksi. Kalau gagal, ya, salah ayahnya.
Budaya ikut menyumbang keruwetan. Maskulinitas tradisional mengajarkan ayah untuk kuat, diam, dan tidak ribet urusan perasaan. Ayah yang terlalu dekat dengan anak sering dianggap aneh. Ayah yang rajin ke sekolah dicurigai tidak laku di pasar kerja. Maka, ayah memilih strategi aman: kerja lebih keras, bicara lebih sedikit, dan berharap cinta bisa dipahami lewat transfer bulanan.
Sekolah pun tidak kalah eksklusif. Dunia pendidikan kita sejak lama menganggap pengasuhan sebagai wilayah ibu. Grup WhatsApp wali murid penuh ibu-ibu, rapat dijadwalkan di jam kerja, dan bahasa komunikasinya domestik maksimal. Ayah tidak benar-benar diajak masuk, lalu dengan mudah dicap “kurang peduli”. Ini semacam soft rejection yang dilakukan dengan senyum dan kop surat resmi.
Dalam lanskap seperti ini, Gerakan Ayah Mengambil Rapor lebih mirip pengakuan canggung negara atas kegagalannya sendiri. Negara baru ingat ayah ketika dampak fatherless mulai kelihatan: anak rapuh secara emosi, relasi keluarga kering, dan generasi tumbuh dengan rindu yang tidak sempat diucapkan. Namun, pengakuan tanpa perubahan kebijakan hanya akan jadi seremoni tahunan.
Ayah datang ke sekolah, difoto, dipuji sebagai ayah inspiratif, lalu kembali ke realitas yang sama—tanpa cuti, tanpa perlindungan, tanpa jaminan. Negara puas karena sudah “peduli”. Ayah tetap realistis karena besok harus bekerja lagi.
Padahal, ayah Indonesia tidak kekurangan cinta. Mereka hanya kekurangan waktu, tenaga, dan sistem yang tidak menganggap keluarga sebagai beban. Anak-anak kita tidak kehilangan ayah; mereka kehilangan ayah yang sempat duduk, mendengar, dan hadir tanpa terburu-buru. Selama negara masih mengira kehadiran ayah adalah urusan niat pribadi, bukan soal struktur, fatherless akan terus dipelihara secara rapi.
Dan barangkali, itulah tragedi paling ironis: ayah bekerja mati-matian agar anaknya hidup layak, tetapi anak tumbuh tanpa cukup waktu untuk benar-benar hidup bersama ayahnya.