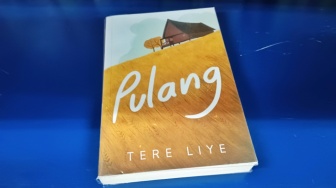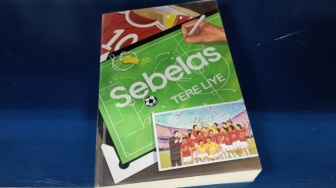Sejak bangku sekolah kita dijejali doktrin moral bahwa kepentingan umum harus selalu didahulukan di atas kepentingan golongan, apalagi kepentingan pribadi. Kalimat itu terdengar luhur, nyaris sakral, seolah menjadi fondasi etika bernegara.
Namun ketika kita dewasa dan melihat praktik kekuasaan dari dekat, ajaran itu justru terasa seperti ironi yang pahit. Sebab di ruang-ruang pengambilan keputusan, kepentingan publik sering kali hanya dijadikan slogan, sementara kebijakan nyata disusun dengan kalkulasi siapa yang paling diuntungkan di lingkaran elite.
Yang diajarkan di sekolah hidup sebagai teori, tetapi yang dipraktikkan di negara ini justru sebaliknya: kepentingan golongan berkuasa mendahului segalanya, dan masyarakat luas diminta menerima hasilnya dengan dalih pembangunan dan nasionalisme.
Kepentingan Umum sebagai Alibi: Membaca Ulang Moral Bernegara
Berpuluh tahun setelah reformasi dikumandangkan, satu pertanyaan mendasar masih menggantung di udara publik Indonesia. Untuk siapa sebenarnya negara ini dijalankan?
Pertanyaan itu mengemuka bukan tanpa alasan. Dalam praktik bernegara, konflik kepentingan justru tampak menjadi hal yang lazim, bahkan seolah dinormalisasi. Regulator merangkap pelaku.
Pengambil kebijakan duduk di dua kursi sekaligus. Sebagai pengatur dan sebagai pemain. Inilah simpul persoalan yang membuat publik semakin sulit percaya bahwa regulasi lahir murni demi kepentingan rakyat.
Kepentingan Umum di Buku Teks, Kepentingan Elite di Meja Kekuasaan
Fenomena ini dapat dilihat di banyak sektor strategis. Di sektor pertambangan, misalnya. Pejabat yang terlibat dalam perumusan kebijakan justru memiliki atau terafiliasi dengan perusahaan tambang.
Di sektor pangan, pengambil keputusan soal harga minyak goreng atau tata niaga sawit kerap beririsan dengan kepemilikan perkebunan besar. Dalam situasi seperti ini, garis antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi menjadi kabur. Regulasi yang seharusnya menjadi alat perlindungan rakyat berubah menjadi instrumen legitimasi bisnis.
Masalahnya bukan sekadar etika, tetapi struktur kekuasaan. Ketika regulator sekaligus pelaku, maka regulasi berpotensi disusun bukan untuk mengoreksi pasar, melainkan mengamankan posisi pemain tertentu.
Negara kehilangan fungsi dasarnya sebagai wasit yang adil. Yang tersisa hanyalah arena di mana segelintir elite saling berbagi keuntungan, sementara rakyat menjadi penonton yang menanggung dampaknya. Dari harga kebutuhan pokok yang melonjak hingga kerusakan lingkungan yang tak tertanggulangi.
Atas Nama Kepentingan Umum, Negara Justru Melayani Segelintir Orang
Kondisi ini membuat publik wajar bertanya: proyek nasional yang ditetapkan pemerintah, apakah benar demi kepentingan bangsa dan negara? Atau justru demi kepentingan kelompok pemilik modal yang memiliki akses langsung ke pusat kekuasaan?
Istilah “proyek strategis nasional” kerap terdengar megah, tetapi di lapangan sering kali menyisakan konflik agraria, penggusuran, dan ketimpangan sosial. Ketika proyek besar dijalankan tanpa partisipasi bermakna masyarakat, kecurigaan bahwa proyek tersebut hanya menguntungkan segelintir pihak menjadi sulit ditepis.
Hubungan mesra antara pejabat dan investor memperkuat dugaan itu. Dalam banyak kasus, pejabat publik tidak sekadar menjadi pengambil kebijakan, tetapi juga mitra bisnis. Baik secara langsung maupun melalui keluarga dan kroninya.
Pola ini melahirkan oligarki ekonomi-politik, di mana kekuasaan dan modal saling menopang. Negara akhirnya lebih responsif terhadap kepentingan investor dibanding suara warga yang terdampak.
Kepentingan Rakyat Hanya Slogan: Potret Konflik Kepentingan di Negara Ini
Dampaknya sangat nyata. Ketika konflik kepentingan dibiarkan, kualitas kebijakan publik menurun. Regulasi menjadi tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Penegakan hukum selektif.
Keadilan sosial hanya menjadi jargon dalam pidato, bukan realitas dalam kehidupan sehari-hari. Lebih berbahaya lagi, praktik ini merusak kepercayaan publik terhadap negara. Rakyat yang kehilangan kepercayaan akan apatis, dan apatisme adalah racun bagi demokrasi.
Padahal, prinsip tata kelola yang baik menuntut pemisahan tegas antara regulator dan pelaku. Di banyak negara, konflik kepentingan dianggap pelanggaran serius, bukan kelaziman.
Transparansi kepemilikan, larangan rangkap jabatan, dan mekanisme pengawasan independen menjadi fondasi utama. Tanpa itu, demokrasi hanya akan menjadi prosedur kosong yang dibajak oleh elite.
Negara untuk Siapa? Dan Sampai Kapan Praktik ini Dibiarkan?
Pertanyaannya kini bukan lagi apakah konflik kepentingan itu ada, karena jawabannya jelas. Melainkan sampai kapan praktik ini dibiarkan?
Jika negara terus dijalankan dengan logika bisnis segelintir orang, maka kepentingan rakyat hanya akan menjadi catatan kaki dalam dokumen kebijakan. Dan pada titik itu, yang runtuh bukan hanya kepercayaan publik, tetapi juga makna negara itu sendiri.