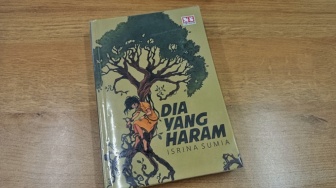Anggapan bahwa anak-anak generasi terdahulu lebih sehat meskipun tumbuh di lingkungan keluarga perokok perlu ditelaah secara kritis. Faktanya, konteks sosial, peran keluarga, dan pemahaman medis pada masa lalu sangat berbeda dengan kondisi saat ini.
Pada era sebelumnya, struktur keluarga cenderung lebih hierarkis dan berbasis pembagian peran yang kaku. Pengasuhan bayi dan balita hampir sepenuhnya berada di tangan ibu, nenek, atau kerabat perempuan. Ayah berperan sebagai pencari nafkah dan relatif minim keterlibatan fisik dalam pengasuhan sehari-hari. Dalam konteks ini, meskipun ayah merokok, intensitas kontak dekat antara anak dan sumber asap rokok relatif terbatas.
Kondisi tersebut sangat kontras dengan pola pengasuhan modern. Saat ini, keterlibatan ayah dalam pengasuhan dipandang sebagai nilai positif dan bahkan ideal. Ayah hadir secara fisik dan emosional: menggendong, menenangkan, menyuapi, dan bermain bersama anak. Namun perubahan ini membawa konsekuensi kesehatan yang perlu disadari, terutama jika kebiasaan merokok tetap dipertahankan tanpa modifikasi perilaku.
Ilmu kesehatan modern telah mengidentifikasi bahwa bahaya rokok tidak hanya berasal dari asap yang terhirup secara langsung (secondhand smoke), tetapi juga dari residu beracun yang menempel pada pakaian, rambut, kulit, dan permukaan benda (thirdhand smoke). Nikotin dan zat karsinogenik lain dapat bertahan lama di lingkungan rumah dan berisiko masuk ke tubuh bayi melalui inhalasi, sentuhan, atau bahkan oral ketika bayi memasukkan tangan ke mulut.
Bayi dan balita merupakan kelompok paling rentan terhadap paparan ini. Sistem pernapasan dan imunitas mereka belum berkembang sempurna, sehingga risiko gangguan kesehatan meningkat, mulai dari infeksi saluran pernapasan, asma, radang telinga tengah, hingga gangguan perkembangan paru-paru jangka panjang.
Lalu, mengapa muncul persepsi bahwa anak-anak zaman dulu “lebih sehat”?
Pertama, adanya bias survivorship dan keterbatasan data. Kasus penyakit kronis, gangguan pernapasan, atau kematian dini pada anak di masa lalu tidak selalu tercatat secara sistematis. Yang dikenang adalah mereka yang tumbuh dewasa dengan kondisi relatif baik, sementara yang sakit atau meninggal kerap luput dari ingatan kolektif.
Kedua, faktor lingkungan dan gaya hidup. Anak-anak dahulu lebih banyak bergerak di luar ruangan, terpapar sinar matahari, dan mengonsumsi makanan yang minim olahan. Aktivitas fisik tinggi dan pola makan sederhana berperan besar dalam menjaga kesehatan dasar, sehingga sebagian dampak negatif lingkungan termasuk rokok tidak selalu tampak secara kasat mata.
Ketiga, kompleksitas risiko di era modern. Anak-anak hari ini tidak hanya berhadapan dengan asap rokok, tetapi juga polusi udara, paparan bahan kimia rumah tangga, makanan ultra-proses, serta gaya hidup sedentari dan paparan layar berlebihan. Ketika rokok hadir di tengah akumulasi faktor risiko ini, dampaknya menjadi lebih signifikan.
Dengan demikian, bukan berarti rokok “lebih aman” di masa lalu, melainkan bentuk dan intensitas paparannya berbeda. Meningkatnya peran ayah dalam pengasuhan harus diiringi dengan peningkatan tanggung jawab terhadap kesehatan anak.
Pendekatan yang relevan bukanlah kembali pada pola asuh lama, melainkan mengadaptasi kebiasaan hidup yang lebih sehat. Prinsip rumah bebas asap rokok, larangan merokok di kendaraan keluarga, serta kebiasaan membersihkan diri sebelum berinteraksi dengan anak merupakan langkah minimal. Secara ideal, penghentian kebiasaan merokok tetap menjadi pilihan paling aman.
Pada akhirnya, kehadiran ayah dalam pengasuhan adalah kemajuan sosial yang patut diapresiasi. Namun kehadiran tersebut baru benar-benar bermakna ketika disertai kesadaran ilmiah dan komitmen untuk melindungi anak dari risiko kesehatan yang dapat dicegah. Cinta orang tua tidak cukup diungkapkan lewat kedekatan, tetapi juga melalui keputusan hidup yang bertanggung jawab.