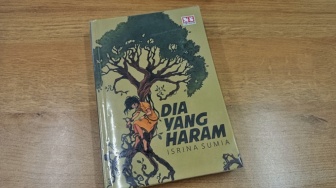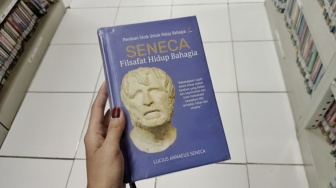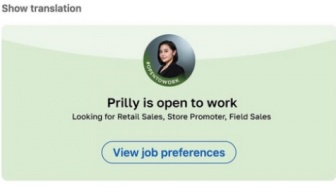Masalah kekurangan guru di sekolah-sekolah Indonesia, terutama di daerah, bukan isu baru. Ironisnya, persoalan ini terus berulang di tengah fakta bahwa jumlah lulusan Sarjana Pendidikan justru melimpah. Dua realitas yang seharusnya saling mengisi ini malah berjalan berlawanan arah. Di antara keduanya, muncul satu simpul masalah yang tak kunjung terurai, guru honorer.
Pola persoalannya hampir seragam. Kepala sekolah mengajukan kebutuhan guru ke dinas pendidikan karena kekosongan tenaga pengajar. Namun, jawaban yang diterima sering kali sama: tidak ada respons cepat.
Alasannya klasik, guru lebih memilih bertugas di kota daripada di daerah atau sekolah pinggiran. Akibatnya, sekolah dibiarkan kekurangan tenaga pendidik, sementara proses belajar mengajar tetap harus berjalan.
Potret Kusut Tata Kelola Pendidikan Nasional
Dalam kondisi terdesak, kepala sekolah akhirnya merekrut guru honorer. Honor mereka dibayarkan dari Dana BOS, dengan kesepakatan awal bahwa gaji yang diterima jauh dari kata layak. Guru honorer menerima karena tak banyak pilihan: lapangan kerja terbatas, sementara kebutuhan hidup terus berjalan. Di sinilah masalah mulai menumpuk.
Secara struktural, kepala sekolah bukan pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat pegawai. Ia hanya pemimpin satuan pendidikan, bukan pengambil kebijakan kepegawaian. Namun dalam praktiknya, kepala sekolah dipaksa keadaan untuk “mengangkat” guru honorer demi menyelamatkan proses pendidikan.
Ketika persoalan administrasi dan kesejahteraan muncul, pemerintah daerah cenderung tutup mata dengan alasan tidak pernah mengangkat guru tersebut secara resmi.
Akibatnya, beban finansial sepenuhnya jatuh ke sekolah. Dana BOS yang seharusnya digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran, perawatan sarana, dan peningkatan mutu pendidikan terkuras untuk menggaji honorer.
Kepala Sekolah Terjepit, Guru Honorer Tersandera Sistem
Kepala sekolah pusing memutar anggaran, guru honorer menuntut hak kenaikan gaji yang manusiawi, sementara pemerintah daerah merasa tidak memiliki tanggung jawab penuh. Siklus ini terus berulang dari tahun ke tahun.
Di sisi lain, ribuan bahkan jutaan lulusan pendidikan menunggu kesempatan mengajar. Mereka memiliki kompetensi akademik, semangat, dan idealisme, tetapi terhambat oleh sistem rekrutmen yang tidak adaptif.
Negara seakan gagal menjembatani kebutuhan sekolah dengan ketersediaan tenaga pendidik. Dari tiga masalah besar ini, kekurangan guru di sekolah, pemerintah menutup mata, dan surplus lulusan pendidikan. Maka lahirlah lahirlah masalah penghubung bernama guru honorer.
Ketika Sekolah Kekurangan Guru, Negara Justru Lepas Tangan
Guru honorer berada di posisi paling rentan. Mereka mengisi kekosongan struktural, tetapi tidak mendapatkan perlindungan struktural. Mereka dibutuhkan, namun tidak diakui sepenuhnya.
Mereka mengajar generasi bangsa, tetapi hidup dalam ketidakpastian status dan penghasilan. Dalam jangka panjang, kondisi ini berbahaya bagi mutu pendidikan nasional.
Solusi parsial seperti penambahan formasi atau kebijakan afirmasi terbukti belum cukup. Masalah ini membutuhkan perubahan sistemik. Salah satu gagasan yang layak dipertimbangkan adalah menarik pengelolaan guru dan sekolah dari fragmentasi daerah ke satu badan khusus berskala nasional, misalnya Badan Pendidikan Nasional.
Dengan pengelolaan terpusat, rekrutmen guru dan tenaga kependidikan dapat dilakukan secara rutin setiap tahun berdasarkan kebutuhan riil sekolah. Distribusi guru bisa diatur lebih adil dan merata, dengan insentif yang jelas bagi penempatan di daerah. Status dan kesejahteraan guru menjadi tanggung jawab negara secara langsung, bukan dilempar ke sekolah atau kepala sekolah.
Tanpa reformasi menyeluruh, Indonesia akan terus terjebak dalam paradoks: sekolah kekurangan guru, lulusan pendidikan menganggur, dan guru honorer terus menjadi korban sistem.
Pendidikan tidak bisa dikelola dengan pola darurat yang diwariskan dari tahun ke tahun. Jika guru adalah kunci kualitas bangsa, maka sistem yang mengelola mereka harus dibangun dengan keseriusan yang sama.