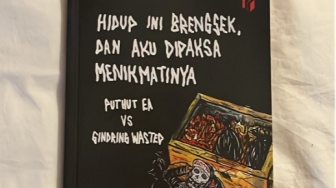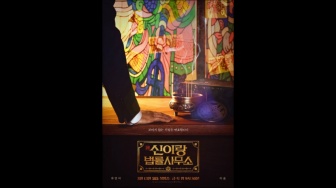Budaya patriarki yang masih mengakar kuat di masyarakat telah membentuk relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam lingkup keluarga. Dalam konstruksi sosial yang mapan, laki-laki kerap ditempatkan pada posisi dominan sebagai pencari nafkah utama sekaligus pemegang otoritas, sementara perempuan dilekatkan pada peran domestik dan pengasuhan. Pembagian peran yang tidak setara ini tidak hanya membebani perempuan, tetapi juga membawa dampak jangka panjang terhadap tumbuh kembang anak.
Di banyak keluarga, tanggung jawab ayah seolah berhenti pada pemenuhan kebutuhan ekonomi. Urusan pengasuhan anak, pekerjaan domestik, hingga pengelolaan emosi keluarga dianggap sebagai wilayah eksklusif ibu. Pola asuh semacam ini telah dinormalisasi lintas generasi, seakan menjadi kodrat yang tak perlu dipertanyakan. Padahal, di balik pembagian peran yang timpang tersebut, tersembunyi persoalan serius yang kerap luput dari perhatian, yakni ketidakhadiran sosok ayah secara emosional dalam kehidupan anak.
Fenomena ini dikenal dengan istilah fatherless. Kondisi fatherless tidak semata merujuk pada ketiadaan ayah akibat perceraian atau kematian, melainkan juga pada situasi ketika ayah hadir secara fisik, tetapi absen secara emosional. Anak tumbuh dalam satu rumah dengan ayahnya, namun relasi yang terbangun dangkal, minim interaksi, dan miskin kelekatan emosional. Ketidakhadiran semacam ini sering kali tidak disadari sebagai persoalan, bahkan dianggap wajar dalam tatanan sosial yang patriarkal.
Ironisnya, ketika anak menunjukkan perilaku bermasalah, sorotan publik hampir selalu tertuju pada ibu. Ibu dianggap gagal mendidik, kurang sabar, atau tidak kompeten dalam mengasuh. Sementara absennya peran ayah nyaris tak pernah dipersoalkan. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa relasi kuasa patriarki tidak hanya merugikan perempuan, tetapi juga menutup ruang refleksi atas peran ayah dalam pengasuhan anak.
Dampak Fatherless terhadap Tumbuh Kembang Anak
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan ayah dalam pengasuhan memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan anak. Studi dari University of Florida melalui publikasi The Impact of Fathers on Children’s Well-Being menegaskan bahwa kehadiran ayah berperan penting dalam perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak. Anak-anak yang memiliki hubungan dekat dengan ayah cenderung memiliki rasa percaya diri lebih tinggi, kemampuan sosial yang lebih baik, serta regulasi emosi yang lebih matang.
Kehadiran ayah tidak sekadar melengkapi peran ibu, melainkan menjadi figur yang unik dan tak tergantikan. Ayah berkontribusi dalam membangun kemandirian anak, memperluas perspektif berpikir, serta memberikan rasa aman secara emosional. Relasi yang hangat dengan ayah membantu anak tumbuh menjadi pribadi yang positif, sehat secara psikologis, dan mampu membangun hubungan sosial yang kuat di kemudian hari.
Sebaliknya, ketidakhadiran ayah secara emosional berisiko menimbulkan berbagai persoalan psikologis. Anak dapat mengalami kesulitan mengelola emosi, merasa tidak berharga, hingga mengalami gangguan relasi saat dewasa. Pengabaian emosional ini kerap berlangsung senyap, tanpa disadari sebagai bentuk kekerasan. Padahal, pengabaian terhadap kebutuhan afeksi dan kelekatan merupakan salah satu bentuk kekerasan emosional yang dampaknya tidak kalah serius dibanding kekerasan fisik.
Mendobrak Normalisasi Patriarki dalam Pengasuhan
Sayangnya, fenomena fatherless di Indonesia belum menjadi isu yang diprioritaskan. Minimnya regulasi, kampanye publik, maupun diskursus kebijakan yang menyoroti pentingnya kehadiran ayah secara emosional menunjukkan bahwa persoalan ini masih dianggap sepele. Wacana pengasuhan anak masih didominasi narasi yang menempatkan ibu sebagai aktor utama, bahkan satu-satunya, dalam parenting.
Normalisasi absennya peran ayah merupakan konsekuensi dari budaya patriarki yang memisahkan peran publik dan domestik secara kaku. Ayah diposisikan sebagai pencari nafkah, sementara pengasuhan dianggap pekerjaan domestik yang bernilai rendah dan tidak membutuhkan keterlibatan laki-laki. Akibatnya, ketika ayah tidak hadir dalam kehidupan emosional anak, hal tersebut tidak dipandang sebagai masalah, apalagi sebagai bentuk pengabaian terhadap hak anak.
Padahal, jika ditelisik lebih jauh, ketidakhadiran ayah secara emosional merupakan persoalan struktural yang diwariskan lintas generasi. Anak-anak yang tumbuh tanpa figur ayah yang hadir secara emosional berisiko mereproduksi pola yang sama ketika dewasa. Inilah yang menjadikan fatherless sebagai kekerasan emosional yang sistemik, berlangsung secara turun-temurun dalam struktur sosial yang saling berkaitan.
Sudah saatnya narasi lama tentang peran ayah didobrak. Peran ayah dalam keluarga tidak boleh disempitkan hanya pada kewajiban ekonomi. Ayah perlu hadir sebagai figur yang terlibat aktif dalam kehidupan anak, mendengarkan cerita mereka, memberikan dukungan emosional, terlibat dalam aktivitas sehari-hari, serta menjadi teladan dalam membangun relasi yang sehat.
Membangun pengasuhan yang setara bukan hanya tentang keadilan gender, tetapi juga tentang masa depan generasi. Anak berhak mendapatkan kehadiran kedua orang tuanya, baik secara fisik maupun emosional. Untuk itu, diperlukan upaya kolektif, mulai dari keluarga, masyarakat, hingga negara, untuk menggeser paradigma pengasuhan yang timpang menuju relasi yang lebih adil, setara, dan manusiawi.
Tanpa perubahan mendasar dalam cara pandang kita terhadap peran ayah, fenomena fatherless akan terus menjadi persoalan laten yang membayangi tumbuh kembang anak Indonesia. Menghadirkan ayah secara utuh dalam pengasuhan bukanlah tuntutan berlebihan, melainkan kebutuhan mendasar demi membangun keluarga yang sehat dan masyarakat yang lebih beradab.