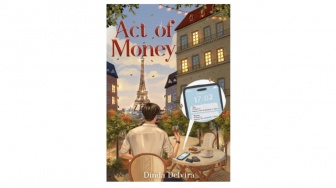Di balik setiap teks yang kita baca, entah itu artikel, novel, esai, atau unggahan media sosial, selalu ada keputusan yang tidak terlihat, yaitu pilihan bahasa. Pilihan ini tidak sekadar teknis, tetapi juga psikologis, sosial, bahkan eksistensial. Bagi penulis, bahasa bukan hanya alat komunikasi, melainkan ruang tarik-menarik antara harga diri dan target pasar.
Menggunakan bahasa yang sederhana sering dianggap sebagai pilihan pragmatis: lebih mudah dipahami, lebih luas jangkauannya, dan lebih inklusif. Namun, di tingkat personal, keputusan ini tidak selalu mudah. Banyak penulis merasa harus "turun level" secara simbolis; bukan dalam kualitas, melainkan dalam persepsi. Ada ketakutan dianggap kurang intelektual, kurang berkelas, atau kurang "sastra".
Padahal, menyederhanakan gagasan justru membutuhkan penguasaan materi yang matang dan kemampuan meramu ide secara jernih. Bahasa yang membumi tidak lahir dari ketidaktahuan, melainkan dari pemahaman yang sudah diolah dengan mendalam.
Di sisi lain, bahasa yang tinggi, sastrawi, dan kompleks sering memberi rasa legitimasi. Ada kepuasan personal saat mampu merangkai kalimat yang indah, metaforis, dan kaya diksi. Bahasa semacam ini sering diasosiasikan dengan kualitas, kedalaman, dan intelektualitas.
Namun, pilihan ini juga membawa konsekuensi: jangkauan pembaca yang lebih sempit, segmentasi yang lebih eksklusif, dan risiko keterputusan dengan pembaca awam. Tidak semua orang memiliki latar literasi, referensi, dan kebiasaan membaca yang sama. Di titik inilah dilema muncul: apakah menulis untuk mengekspresikan diri atau untuk menjangkau pembaca? Apakah bahasa menjadi representasi identitas pribadi atau strategi komunikasi? Ini bukan soal benar atau salah, melainkan soal orientasi.
Pertarungan Harga Diri dan Tuntutan Pasar
Harga diri penulis sering melekat pada gaya bahasa. Bahasa menjadi simbol kompetensi, kedalaman, bahkan martabat intelektual. Sementara itu, target pasar menuntut keterbacaan, aksesibilitas, dan kejelasan. Dua kepentingan ini tidak selalu sejalan. Yang satu bergerak ke arah ekspresi dan idealisme, sedangkan yang lain ke arah distribusi dan jangkauan.
Dalam dunia perbukuan, dilema ini sangat nyata. Penulis dan penerbit harus memikirkan:
- Siapa yang akan membaca;
- Bagaimana latar pendidikan mereka;
- Bagaimana kebiasaan literasi mereka; serta
- Seberapa kompleks bahasa yang bisa diterima tanpa menciptakan jarak.
Bahasa sederhana membuka pasar yang luas, tetapi sering dianggap "kurang prestisius". Bahasa kompleks memberi citra intelektual, tetapi membatasi segmentasi.
Akhirnya, banyak karya lahir sebagai hasil kompromi: tidak terlalu sederhana, tetapi tidak terlalu tinggi; tidak sepenuhnya populer, tetapi juga tidak sepenuhnya elitis. Ini bukan kelemahan, melainkan strategi. Penulisan menjadi praktik negosiasi antara idealisme personal dan realitas pembaca.
Hal yang sering luput disadari, dilema ini bukan hanya teknis, melainkan juga emosional. Ada pertarungan batin di dalamnya: antara ingin setia pada gaya sendiri dan ingin relevan bagi orang lain; antara kebutuhan ekspresi diri dan kebutuhan komunikasi sosial; serta antara identitas sebagai penulis dan fungsi sebagai komunikator.
Bahasa sebagai Alat Navigasi
Dalam konteks ini, bahasa bukan lagi sekadar medium, melainkan medan tawar-menawar. Harga diri ingin diakui, target pasar ingin dipahami, dan penulis berdiri di tengah-tengahnya. Mungkin titik temunya bukan pada memilih satu dan menyingkirkan yang lain, melainkan pada kesadaran konteks. Bahasa yang tepat adalah bahasa yang sesuai dengan tujuan.
Untuk edukasi, bahasa perlu inklusif. Untuk sastra, ia bisa lebih ekspresif. Untuk pasar luas, ia perlu adaptif. Untuk ekspresi personal, ia bisa lebih bebas. Dengan begitu, bahasa tidak lagi menjadi simbol pertarungan, melainkan alat navigasi; bukan arena pembuktian diri, melainkan jembatan komunikasi; bukan medan gengsi, melainkan ruang dialog.
Di sanalah dilema penulis menemukan bentuk paling jujurnya. Ini bukan tentang memilih sederhana atau rumit, melainkan tentang menentukan siapa yang ingin diajak bicara dan untuk tujuan apa.