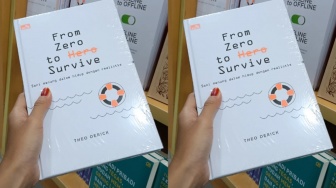Nama B. J. Habibie sering dikenang sebagai simbol kecerdasan dan transisi demokrasi Indonesia. Namun ada satu warisan politiknya yang jarang dibahas secara serius: cara ia memaknai kekuasaan tanpa balas budi koalisi.
Habibie memimpin dalam kondisi politik yang rapuh, tanpa basis partai dominan, tanpa koalisi besar yang solid, dan tanpa kekuatan parlemen yang mutlak. Akan tetapi, justru di situlah letak signifikansinya.
Secara politik, masa pemerintahan Habibie (1998–1999) berdiri di tengah fragmentasi kekuasaan. DPR hasil Pemilu 1997 masih didominasi Golkar lama, sementara tekanan publik menuntut reformasi sistemik. Dalam konteks ini, Habibie tidak membangun pemerintahan berbasis politik balas jasa.
Kabinet Reformasi Pembangunan yang ia bentuk justru memprioritaskan figur teknokrat, profesional, dan transisional, bukan distribusi kursi berdasarkan utang koalisi.
Fakta sejarah mencatat, dalam waktu singkat pemerintahannya, Habibie menghasilkan lebih dari 60 undang-undang penting yang menjadi fondasi reformasi, termasuk:
- UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- UU Otonomi Daerah (UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999)
- UU Pers No. 40 Tahun 1999
Data ini menunjukkan bahwa kekuasaan tidak digunakan untuk konsolidasi elite, tetapi untuk rekonstruksi sistem. Ini bukan romantisme, tapi fakta legislasi.
Habibie juga menyetujui referendum Timor Timur (1999)—sebuah keputusan politik besar yang sangat tidak populer secara domestik, tetapi penting secara demokratis.
Ini menunjukkan satu hal: kebijakan tidak selalu tunduk pada kepentingan politik jangka pendek, tetapi pada pertimbangan institusional dan etika politik global.
Bandingkan dengan pola kekuasaan hari ini. Data dari Transparency International Indonesia menunjukkan bahwa indeks persepsi korupsi Indonesia masih stagnan dalam satu dekade terakhir, berkisar di skor 34–38 (skala 0–100). Ini menunjukkan bahwa reformasi struktural belum menyentuh akar sistemik kekuasaan.
Sementara itu, laporan Komisi Pemberantasan Korupsi berulang kali menunjukkan bahwa kasus korupsi politik paling dominan berasal dari:
- pengadaan barang/jasa,
- proyek infrastruktur,
- suap perizinan,
- dan jual beli jabatan.
Ini adalah pola klasik politik balas budi: jabatan sebagai kompensasi, proyek sebagai hadiah, kebijakan sebagai alat transaksi.
Riset dari World Bank juga menunjukkan bahwa negara dengan sistem patronase politik tinggi cenderung memiliki:
- kualitas birokrasi rendah,
- efektivitas kebijakan publik lemah,
- ketimpangan sosial tinggi,
- dan kepercayaan publik yang rendah terhadap negara.
Artinya, masalah ini bukan sekadar moralitas elite, tapi struktur kekuasaan.
Dalam sistem koalisi transaksional, pemimpin tidak sepenuhnya merdeka. Ia terikat oleh “utang politik”. Kebijakan bukan lagi soal kepentingan publik, tapi soal menjaga keseimbangan kepentingan elite. Negara berubah dari institusi publik menjadi arena distribusi akses.
Di sinilah bahaya terbesar muncul. Bukan karena satu figur tertentu, tapi karena sistem memberi ruang pada figur tanpa kapasitas. Mereka naik bukan karena kompetensi, tapi karena kompatibilitas dengan jaringan. Bukan karena visi, tapi karena loyalitas. Bukan karena integritas, tapi karena kepatuhan.
Habibie memberi contoh bahwa kekuasaan bisa dijalankan tanpa menjadikan koalisi sebagai utang moral. Tanpa menjadikan jabatan sebagai alat balas jasa. Tanpa menjadikan negara sebagai kompensasi politik. Ini bukan klaim moral, tapi rekam jejak kebijakan dan struktur kabinet.
Sayangnya, model ini tidak diwarisi secara institusional.
Hari ini, demokrasi tidak runtuh lewat kudeta. Ia lapuk secara administratif. Ia melemah lewat normalisasi transaksi. Ia rusak lewat kompromi tanpa batas. Ia hancur bukan oleh konflik terbuka, tapi oleh sistem yang menjadikan negara sebagai alat tawar-menawar.
Dan dampaknya bukan hanya kebijakan yang buruk, tapi:
- runtuhnya kepercayaan publik,
- matinya etika politik,
- melemahnya rasionalitas sosial,
- dan munculnya figur-figur tanpa kapasitas publik.
Habibie bukan figur tanpa cela. Tapi satu warisannya sangat jelas: politik tanpa balas budi adalah mungkin.
Karena begitu balas budi menjadi sistem, negara berhenti menjadi rumah bersama. Ia berubah menjadi ladang transaksi. Dan ketika itu terjadi, bangsa tidak dihancurkan oleh musuh luar, tetapi oleh mekanisme kekuasaannya sendiri.
Ini bukan nostalgia. Ini bukan romantisme masa lalu. Ini soal struktur kekuasaan hari ini. Karena sejarah selalu menunjukkan satu pola: bukan yang paling bijak yang naik, tetapi yang paling cocok dengan sistem.
CEK BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS