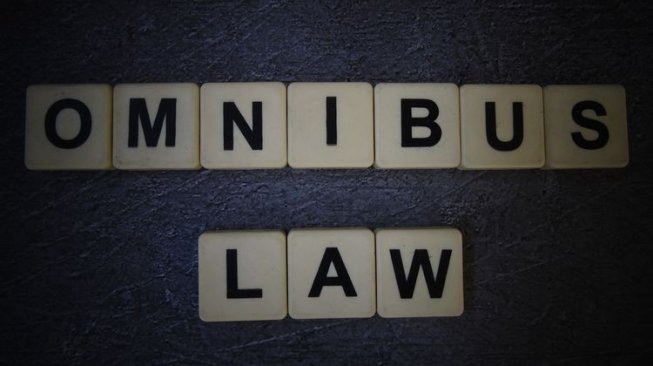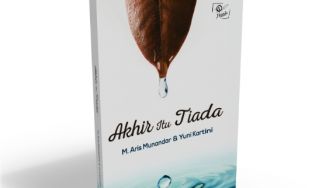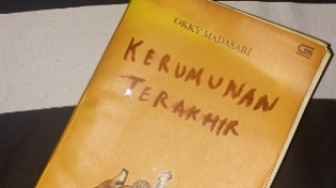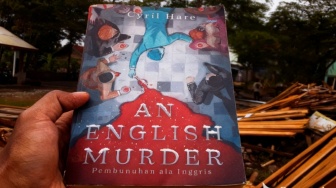Konsepsi Omnibus Law
Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) sontak menjadi perbincangan publik setelah dipublikasi beberapa bulan yang lalu.
Bukan sesuatu yang biasa, sebab RUU Cipta Kerja dibentuk dengan menggunakan metode omnibus law yang masih sangat asing ditelinga masyarakat Indonesia, walaupun sebenarnya metode tersebut sudah dikenal sejak lama dalam ilmu hukum.
Sehingga bukan sesuatu yang baru terdengar ditelinga kalangan akademisi hukum terkait omnibus law tersebut. Akan tetapi, yang menjadi problematika utamanya adalah masih minimnya pemahaman masyarakat terkait konsep omnibus law yang ditawarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui RUU Cipta Kerja.
Menurut Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, SH., MH. (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin) menjelaskan bahwa secara letterlijk, kata “omnibus” berasal dari bahasa latin yakni “omnibis” (banyak).
Dalam artian omnibus adalah hukum yang banyak dalam hal pengaturan yang dilakukan dengan lintas sektor dan bisa mencabut atau membatalkan ketentuan yang bertentangan. Sehingga konsep omnibus law adalah metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum.
Konsep tersebut dikenal juga dengan nama omnibus bill yang pada dasarnya sering digunakan dalam negara yang menganut common law system seperti Amerika Serikat pada saat membentuk sebuah regulasi (Sumber: makassar.terkini.id).
Secara sederhana dapat dipahami bahwasanya dalam konsep omnibus law, regulasi yang dibentuk senantiasa dilakukan untuk membuat undang-undang yang baru dengan membatalkan atau mencabut juga mengamandemen beberapa peraturan perundang-undangan sekaligus.
Tujuan utama konsep omnibus law ialah suatu undang-undang bertujuan untuk menyasar isu besar (sentral) yang memungkinkan dilakukannya pencabutan atau perubahan beberapa undang-undang sekaligus (lintas sektor) untuk kemudian dilakukan penyederhanaan dalam pengaturannya. Sehingga diharapkan tidak terjadi konkurensi antara norma yang satu dengan yang lainnya.
RUU Cipta Kerja Sebagai Produk Omnibus Law
Banyak kekhilafan terjadi di masyarakat dalam memahami isu omnibus law ini. Terdapat pemahaman masyarakat yang menganggap omnibus law dengan RUU Cipta Kerja merupakan hal yang sama, padahal keduanya sangat jauh berbeda.
Omnibus law merupakan metode pembentukan peraturan perundang-undangan yang dikenal melalui metode ilmiah, sedangkan RUU Cipta Kerja merupakan produk hukum yang dihasilkan dari metode omnibus law tersebut.
Penulis menganalogikan omnibus law ini sebagai metode penelitian Skripsi, sedangkan RUU Cipta Kerja merupakan hasil penelitian yang diuji oleh para dosen di kampus pada saat ujian Skripsi.
Sehingga yang patut diperdebatkan ialah substansi RUU Cipta Kerja yang merupakan produk hukum sebagai hasil metode omnibus law. Oleh karenanya harus ada satu pemahaman di dalam masyarakat bahwa antara omnibus law dengan RUU Cipta Kerja merupakan hal yang berbeda dalam konteks teoretis.
Munculnya ide RUU Cipta Kerja dengan menggunakan metode omnibus law adalah cikal bakal dari pidato Presiden Joko Widodo sebagai Presiden terpilih dalam Pemilihan Presiden tahun 2019 yang pada poin utamanya menyatakan bahwa Pemerintah akan mengajak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menerbitkan 2 (dua) undang-undang besar yakni UU Cipta Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.
Di mana kedua undang-undang tersebut akan menjadi omnibus law yakni satu UU akan merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU yang ada dengan tujuan tercipta penyederhanaan, pemotongan dan pemangkasan peraturan yang menghambat penciptaan lapangan kerja.
Menyikapi hal tersebut, sudah sepatutnya kita berpikir secara jernih agar tidak terjadi pola pikir yang apriori (berpraanggapan sebelum mengetahui) terhadap rencana Pemerintah. Oleh karena itu perlu dibaca dan dipahami substansi dari RUU Cipta Kerja yang ada sebagai salah satu produk hukum yang ditawarkan oleh Pemerintah.
Secara teori, penulis setuju dengan pembentukan undang-undang yang menggunakan metode omnibus law, karena selain terciptanya penyederhanaan dalam peraturan juga dapat menjadi solusi terhadap penyelesaian masalah konkurensi norma dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.
Meskipun demikian, yang perlu diperhatikan adalah substansi pengaturannya, sebab hal yang banyak dipertentangkan selama ini adalah banyaknya kepentingan politik yang acap kali tidak sesuai dengan kepentingan rakyat sehingga terjadilah penolakan besar-besaran dalam beberapa rancangan undang-undangan yang ditawarkan oleh Pemerintah dan DPR.
Beberapa Problematika Substansi RUU Cipta Kerja
Keberadaan RUU Cipta Kerja sebagai suatu bentuk kebijakan Pemerintah menimbulkan reaksi sosial dari beberapa kalangan seperti kaum buruh, organisasi masyarakat dan organisasi kepemudaan.
Reaksi tersebut muncul karena adanya beberapa substansi RUU Cipta Kerja yang menurut mereka tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat bahkan cenderung menghasilkan masalah yang baru.
Sejatinya dalam RUU Cipta Kerja akan merampingkan sekitar 79 undang-undang dan 1.239 pasal menjadi 15 bab dan 174 pasal yang mencakup 11 klaster dari 31 Kementerian dan lembaga terkait yaitu penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan UMKM, kemudahaan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah, serta kawasan ekonomi. Penulis akan menguraikan beberapa pasal dalam RUU Cipta Kerja yang diduga memiliki kecendurangan untuk menciptakan masalah baru.
Pertama, dihilangkannya frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).
Awalnya Pasal 88 UU PPLH berbunyi “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”
Tetapi dalam RUU Cipta Kerja Pasal 88 UU PPLH diubah menjadi “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya”.
Implikasinya adalah regulasi tersebut dapat menimbulkan kelemahan dalam penegakan hukum bagi pelaku perusak lingkungan hidup. Selain itu, efek penjeraan dan menakut-nakuti pun hilang bagi para pelaku tindak pidana lingkungan.
Kedua, ditambahkannya sanksi administratif bagi pelanggar baku mutu lingkungan hidup berupa baku mutu udara ambien, air dan air laut pada Pasal 98 ayat (1) UU PPLH. Awalnya Pasal 98 ayat (1) UU PPLH berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.
Tetapi dalam RUU Cipta Kerja Pasal 98 ayat (1) UU PPLH diubah menjadi “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”
Implikasinya adalah terdapat kelonggaran yang luar biasa bagi pelaku pelanggaran baku mutu lingkungan hidup, bahkan ketentuan tersebut cenderung lebih pragmatis dan tidak memberikan efek jera bagi pelaku.
Sudah seharusnya sanksi pidana merupakan yang utama diterakan (primum remidium) bagi pelaku pelanggar baku mutu lingkungan hidup sebagaimana asas keserasian dan keseimbangan dalam UU PPLH.
Ketiga, dihapusnya hak publik untuk melakukan gugatan administratif melalui pengujian terhadap izin lingkungan dan/atau izin usaha melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada Pasal 93 UU PPLH. Sebagaimana diketahui, bunyi Pasal 93 UU PPLH yaitu “Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara”.
Gugatan tersebut menurut ketentuan dalam UU PPLH dapat dilakukan apabila badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal, badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKLUPL, dan/atau badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.
Namun di dalam RUU Cipta Kerja ketentuan Pasal 93 UU PPLH dihapuskan. Hal ini tentunya bertentangan dengan asas partisipatif yang terdapat dalam UU PPLH, serta menghilangkan peran masyarakat dalam ikut serta melindungi lingkungan hidup.
Keempat, tidak memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan. Pasal 170 ayat (1), (2) dan (3) secara jelas menjelaskan bahwa “Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau mengubah ketentuan dalam Undang-Undang yang tidak diubah dalam Undang-Undang ini.” Lebih lanjut diterangkan pula bahwa “Perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”
Implikasi dari ketentuan tersebut adalah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang secara tegas termaktub bahwa Peraturan Pemerintah (PP) berada di bawah undang-undang. Dengan demikian PP tidak dapat membatalkan ataupun mengubah ketentuan yang ada dalam undang-undang, sebab PP adalah peraturan pelaksana dari undang-undang itu sendiri.
Kelima, dihilangkannya tanggung jawab kewajiban tanggung jawab terhadap kebakaran di areal konsesi pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (UU Kehutanan). Awalnya Pasal 49 UU Kehutanan berbunyi “Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya.”
Tetapi dalam RUU Cipta Kerja Pasal 49 UU Kehutanan diubah menjadi “Pemegang hak atau Perizinan Berusaha wajib melakukan upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan di areal kerjanya.” Implikasi dari ketentuan tersebut ialah hilangnya tanggung jawab mutlak para pelaku kebakaran hutan jika terjadi kebakaran, hal ini tentunya semakin melemahkan penegakan hukum bagi perusak hutan.
Frasa “upaya pencegahan dan pengendalian” dalam RUU Cipta Kerja tersebut tanpa disebutkan pun sudah menjadi tanggung jawab moral bagi setiap pemegang hak atau izin, sehingga yang perlu diatur adalah pertanggungjawaban pidana pelaku kerusakan hutan tersebut.
Keenam, dihilangkannya batasan konkrit terkait 1 (satu) Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) untuk tahap kegiatan Operasi Produksi pertambangan mineral logam dan batubara dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Awalnya dalam UU Minerba dijelaskana bahwa “luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan mineral logam diberikan dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.” dan “luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan batubara diberikan dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare”.
Tetapi dalam RUU Cipta Kerja ketentuan Pasal 83 huruf (c) UU Minerba diubah menjadi “Luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan Operasi Produksi pertambangan mineral logam dan batu bara diberikan berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Pusat terhadap rencana kerja seluruh wilayah yang diusulkan oleh pelaku usaha pertambangan khusus”.
Implikasi dari ketentuan tersebut ialah terjadinya ketidakpastian hukum dalam memberikan batasan luas 1 (satu) wilayah operasi pertambangan mineral logam dan batubara. Bahkan cenderung membuka peluang pemberian batas kegiatan operasi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebelumnya. Tentunya jika hal itu terjadi maka sangat merugikan lingkungan hidup.
Ketujuh, tidak dicantumkannya batas minimal istirahat panjang bagi pekerja/buruh dalam ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan).
Awalnya bunyi dari Pasal 79 ayat (2) huruf b UU Ketenagakerjaan yaitu “Istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 (dua) tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun.”
Tetapi dalam RUU Cipta Kerja, ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf b UU Ketenagakerjaan tidak lagi diatur secara jelas. Pasal 79 ayat (5) RUU Cipta Kerja hanya mengatur terkait cuti panjang yang diatur melalui perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, sehingga kekuatan mengikatnya sangat lemah dibandingkan jika diatur dalam undang-undang.
Selain itu, jika dilihat dari sudut pandang psikologis, sangat memungkinkan pekerja/buruh dalam membuat suatu perjanjian kerja mengalami tekanan psikologis sehingga dalam pengambilan keputusannya tidak sesuai kehendak yang sebenarnya dari pekerja/buruh, terutama dalam hal meminta kebijakan pemberi kerja untuk dicantumkan batasan waktu istirahat panjang.
Kedelapan, dihilangkannya kewenangan Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk memberikan izin bagi pemberi kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebagaimana dalam Pasal 42 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, serta dipermudahnya TKA karena setiap perusahaan sponsor TKA hanya membutuhkan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sedangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing setidaknya diatur 2 (dua) kewajiban pemberi kerja dan TKA yakni memiliki RPTKA dan Visa Tinggal Terbatas (Vitas). Pada awalnya, bunyi Pasal 42 ayat (1) UU Ketenagakerjaan adalah “Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.”
Namun dalam RUU Cipta Kerja, bunyi Pasal 42 ayat (1) UU Ketenagakerjaan diubah menjadi “Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing dari Pemerintah Pusat.” Dampaknya adalah tidak ada lagi mekanisme perizinan yang kompleks bagi TKA sebagaimana ketentuan UU Ketenegakerjaan sebelumnya.
Hal tersebut juga akan berimplikasi tidak digunakannya lagi Vitas dalam mekanisme perekrutan TKA sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Perpres No. 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing bahwa “Setiap TKA yang bekerja di Indonesia wajib mempunyai Vitas untuk bekerja.”
Dan “Vitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimohonkan oleh Pemberi Kerja TKA atau TKA kepada menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau pejabat imigrasi yang ditunjuk.”
Ketentuan tersebut sudah seyogianya akan sangat mempermudah masuknya TKA di Indonesia, sedangkan kompleksitas permasalahan tenaga kerja lokal masih belum terselesaikan.
Oleh karena itu, perubahan Pasal 42 UU Ketenagakerjaan melalui RUU Cipta Kerja tersebut haruslah dipertimbangkan kembali oleh Pemerintah, sebab akan berdampak pada ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.
Uraian di atas merupakan bagian terkecil dari banyaknya persoalan yang terdapat dalam RUU Cipta Kerja. Tentunya setiap RUU yang diusulkan pemegang kekuasaan harus bersesuaian dengan kepentingan rakyat sebagaimana asas hukum “solus publica suprema lex” (kepentingan rakyat berada di atas segala-galanya termasuk di atas undang-undang).
Namun, muncul sebuah pertanyaan mendasar, RUU Cipta Kerja sebenarnya untuk siapa? Sudah barang tentu yang mampu menjawab hal tersebut adalah RUU Cipta Kerja itu sendiri dengan segenap substansinya yang krusial.
Jangan sampai RUU Cipta Kerja hanya dibentuk untuk kepentingan kelompok tertentu dan melalaikan kepentingan rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di negeri insulinde ini.
Konstitusi Indonesia telah mengamanatkan adanya jaminan hak asasi manusia dan perlindungan terhadap segala yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia yang sifatnya mendasar seperti lingkungan hidup yang baik, upah yang layak, perlakuan yang sama di depan hukum serta hak untuk mengemukakan pendapat.
Kesemuanya itu haruslah dijamin oleh negara. Jika hal itu dilanggar maka masyarakat memiliki hak untuk menyuarakannya melalui media apapun.
Berdasarkan beberapa hal di atas, maka penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa RUU Cipta Kerja memiliki kecenderungan yang dapat menimbulkan masalah baru di masyarakat sehingga sebelum disahkan harus dilakukan penyesuain secara mutatis mutandis dan menilik setiap pandangan umum.
Sebab, undang-undang yang baik adalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tentunya progresif sebagaimana dikatakan oleh Prof. Satjipto Rahardjo bahwa “hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”.
Selain itu, masih adanya kekeliruan dalam memahami hierarki perundang-undangan dalam RUU Cipta Kerja dipandang merupakan kesalahan sangat fatal dalam ilmu hukum. Olehnya itu, harus dilakukan revisi yang sangat mendasar terhadap RUU Cipta Kerja agar tidak menimbulkan konkurensi norma dan melanggar hak rakyat yang bersifat mendasar.
Oleh: M. Aris Munandar, SH. / Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Dewan Pertimbangan Komisariat KAMMI Komisariat Sosial Humaniora Universitas Hasanuddin Periode 2019-2020