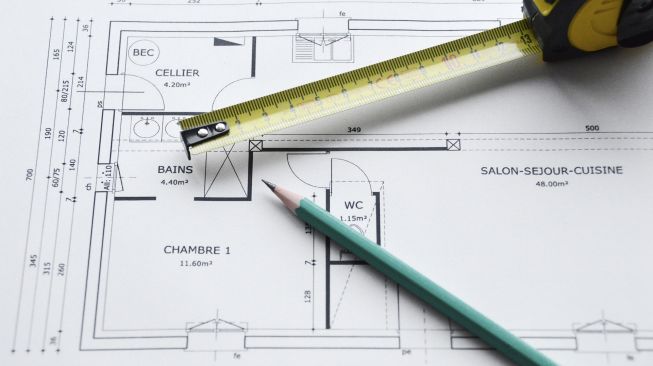Pengertian profesi arsitek berdasar pada UIA (International Union of Architects) Accord on Recommended International Standards of Professionalism in Architectural Practice and Recommended Guidelines, adalah seseorang yang memiliki kualifikasi secara profesional dan akademis dan secara umum terdaftar atau memiliki lisensi/sertifikat untuk melakukan praktik arsitektur di suatu area serta memiliki tanggung jawab untuk mengadvokasi perkembangan yang adil dan berkelanjutan, kesejahteraan dan ekspresi budaya dari suatu habitat masyarakat dalam wujud ruang, bentuk dan konteks sejarah.
Profesi arsitek erat kaitannya dengan pembangunan, baik skala makro maupun mikro. Arsitek berperan penting dalam penentuan dan perkembangan wajah suatu kota dengan membentuk lingkungan binaan yang mapan dan berkelanjutan. Terlebih jika kita berbicara tentang arsitektur, maka tanggung jawab arsitek bukan hanya pada konsep atau desain rancangan atas suatu bangunan, melainkan juga mengenai kekuatan dan kekokohan bangunan.
Payung Hukum Profesi Arsitek
Dalam praktiknya, profesi arsitek perlu mendapat payung hukum yang implementatif dan komprehensif dalam rangka melindungi keberadaan profesi arsitek dan hasil karyanya, serta mampu menghindari adanya pelayanan jasa perencanaan arsitektur yang dilakukan secara tidak bertanggungjawab (malpraktik), ilegal, dan merugikan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (UU Arsitek), merupakan wujud perlindungan hukum yang diberikan oleh negara bagi arsitek, pengguna jasa arsitek, hasil karya arsitektur serta masyarakat luas. UU Arsitek secara garis besar membahas mengenai arsitek baik lingkup kerjanya, persyaratan, hubungan dengan masyarakat, pembinaan, serta tata cara praktek bagi arsitek yang berasal dari luar Indonesia.
Perlindungan hukum terhadap profesi arsitek juga bertujuan untuk mendorong kreatifitas, kualitas, dan persaingan sehat antar-arsitek lokal maupun arsitek asing.
Melihat bahwa banyak arsitek asing yang melakukan praktik kerja di Indonesia, pemerintah lantas menempatkan arsitek asing sebagai subjek hukum yang juga diakomodir dalam UU Arsitek. Pengaturan mengenai arsitek asing dalam UU Arsitek tertuang dalam Pasal 18-20, bahkan dalam bab tersendiri.
Ketentuan dalam UU Arsitek, mewajibkan arsitek asing yang akan praktik di Indonesia memiliki sertifikat keahlian dan terdaftar (Registered) lembaga yang ditunjuk mewakili negara. Diberlakukannya ketentuan tersebut berangkat dari banyaknya arsitek asing yang menggarap proyek-proyek besar di Indonesia.
Sebagaimana dikutip dari laman Kompas.com, para pengembang besar sekaliber Lippo Group, Ciputra Group, Pakuwon Group, maupun Intiland Group, lebih memilih menggunakan jasa arsitek asing ketimbang lokal. Pasalnya, arsitek asing menawarkan sistem, profesionalitas, kecepatan, dan memahami perkembangan zaman. Hal tersebut tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi arsitek lokal yang belum memiliki kapasitas daya saing global.
Perubahan UU Arsitek melalui RUU Cipta Kerja
Pada pertengahan februari lalu, pemerintah beritikad melakukan reformasi hukum dengan mengajukan usulan rancangan Undang-Undang Cipta kerja atau lazim kita sebut saat ini sebagai RUU Omnibus Law. Omnibus law sendiri merupakan metode penyusunan undang-undang yang menggabungkan beberapa undang-undang sektoral menjadi satu kompilasi UU sebagai payung hukum (umbrella act).
Walaupun metode omnibus law tak lazim dilakukan di negara yang menganut civil law system seperti Indonesia, metode ini tetap dipilih oleh pemerintah dengan dalih dapat menyederhanakan banyak Undang-Undang sektoral yang tercerai berai dan berbelit.
Konsep Omnibus Law menyasar pada isu besar atau sentral yang memungkinkan untuk dilakukan pencabutan atau perubahan. Salah satu RUU yang menggunakan metode omnibus yakni RUU Cipta Kerja yang sampai saat ini belum memiliki titik terang untuk dilakukan pengesahan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan RUU Cipta Kerja mencakup 79 undang-undang, memuat 15 bab dan 174 pasal dengan menyasar 11 klaster, termasuk rancangan perubahan terhadap UU Arsitek yang tertuang dalam pasal 26 RUU Cipta Kerja.
Catatan Substansial Perubahan UU Arsitek
Namun demikian, terdapat permasalahan mendasar yang didapati penulis pada perubahan UU Arsitek dalam RUU Cipta Kerja, terutama berkaitan dengan pengaturan arsitek asing. Pertama, UU Arsitek sebelumnya mengatur bahwa kewenangan penerbitan lisensi berada di bawah tanggung jawab pemerintah provinsi. Sementara, perubahan UU Arsitek yang terdapat dalam RUU Cipta Kerja mengubah kewenangan tersebut menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
Menurut Ronny AB Wardhana, anggota tim penyusun rapermen PUPR tentang Arsitek, penerbitan lisensi profesi arsitek oleh Pemerintah Provinsi dilatarbelakangi oleh dua hal yaitu dikarenakan setiap daerah memiliki local wisdom-nya masing-masing.
Karakteristik adat dan budaya akan berpengaruh pada arsitektur kota tersebut serta melindungi arsitek lokal dari masuknya arsitek dari luar provinsi. Kewenangan penerbitan lisensi dibawah pemerintah provinsi merupakan bentuk semangat desentralisasi dan otonomi daerah. Keberlakuan otonomi daerah, secara khusus memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola sendiri daerahnya. Penerbitan lisensi profesi arsitek termasuk dalam kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi melalui UU Arsitek.
Pasca penerbitan RUU Cipta Kerja, kewenangan itu lalu diubah. Penerbitan lisensi ditarik kembali menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Apabila merujuk pada tujuan dibentuknya RUU Cipta Kerja, penyatuan berbagai UU dalam satu kompilasi UU bertujuan untuk mengharmonisasikan regulasi sehingga tidak berbelit.
Namun demikian, diambil alihnya kewenangan penerbitan lisensi arsitek dari pemerintah provinsi kepada pemerintah pusat, menimbulkan keraguan apakah akan tetap sesuai dengan tujuan\melindungi arsitek lokal dari masuknya arsitek luar dan menjaga orisinilatitas karakter adat dan budaya setempat atau justru sebaliknya.
Sementara dalam Naskah Akademik RUU Cipta Kerja, alasan pengalihan kewenangan tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit dan rigid. Menurut hemat penulis, pengalihan kewenangan sebenarnya dapat dikompromikan sepanjang sesuai dengan alasan-alasan yang jelas dan tidak mengancam keberadaan arsitek lokal.
Sebaliknya, apabila tidak terdapat alasan yang jelas atas hal tersebut, maka dapat menjadi preseden buruk terhadap semangat desentralisasi dan otonomi daerah yang selama ini digaungkan
Kedua, UU Arsitek telah mengatur mengenai sanksi administratif yang tercantum pada Pasal 38-42 bagi arsitek lokal maupun arsitek asing yang melanggar ketentuan UU. Jenis sanksi administratif terdapat dalam Pasal 38 UU Arsitek diantaranya yaitu peringatan tertulis; penghentian sementara Praktik Arsitek; pembekuan Surat Tanda Registrasi Arsitek; dan/atau pencabutan Surat Tanda Registrasi Arsitek. Namun, dalam RUU Cipta Kerja, Pasal 38 telah diubah perumusannya dan ditambahkan satu ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 38
(1) Setiap Arsitek yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 18 ayat (2), Pasal 19, dan Pasal 20 dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai oleh Organisasi Profesi Arsitek. ”
Sementara Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 telah dihapuskan. Ketentuan mengenai penerapan penjatuhan sanksi administratif terhadap pelanggar sebenarnya telah terabsorpsi ke dalam perubahan Pasal 38 tersebut di atas. Kendati demikian, rumusan baru pasal tersebut justru menghilangkan jenis-jenis sanksi administratif yang sebelumnya disebutkan secara eksplisit dalam UU Arsitek. Hilangnya jenis sanksi tentu dapat menimbulkan kebingungan kepada pihak yang diberi wewenang dalam menjatuhkan sanksi.
Ketiga, terkait dengan kewenangan penjatuhan sanksi administratif oleh Organisasi Profesi Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), Penulis tidak menemukan alasan mendasar pemberian kewenangan dalam NA RUU Cipta Kerja.
Di sisi lain, Pasal 42 UU Arsitek maupun RUU Cipta Kerja telah mengamanatkan bahwa tata cara pengenaan sanksi administratif akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah (PP). Akan tetapi, sejak disahkannya UU Arsitek hingga saat ini, penulis tak kunjung dapat mengakses PP tentang Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana diamanatkan UU Arsitek dan RUU Cipta Kerja.
Penulis hanya menemukan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2019 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah, yang dalam isinya termuat rencana penyusunan PP tentang Tata Cara Penerbitan Lisensi dan PP tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif dan yang Berwenang Mengenakan Sanksi Administratif. Artinya jika menggunakan penafsiran argumentum a contrario, maka sejak UU Arsitek diundangkan sampai pada tahun 2019, amanat pembentukan PP belum juga dilaksanakan
Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa perubahan kewenangan penerbitan lisensi profesi arsitek oleh pemerintah provinsi kepada pemerintah pusat dapat berpotensi menggerus semangat desentralisasi dan otonami daerah.
Hal tersebut diperkuat dengan kurang jelasnya alasan perubahan kewenangan dalam naskah akademik. Selain itu, adanya penghapusan pasal 39-41 dan pengabsorpsian ke dalam pasal 38 dalam RUU Cipta Kerja yang mengatur mengenai sanksi administratif justru tidak diuraikan dengan jelas jenis-jenis sanksi administratif yang diterima oleh arsitek lokal maupun arsitek asing ketika melakukan pelanggaran.
Terlebih, PP yang mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif yang diamanatkan oleh pasal 42 UU Arsitek maupun RUU Cipta Kerja belum dapat diakses. Situasi demikian tentu menjadi pekerjaan rumah dan momentum bagi pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah agar sanksi administratif dapat dijalankan serta menunjukan komitmennya dalam memberikan perhatian terhadap profesi arsitek saat ini.