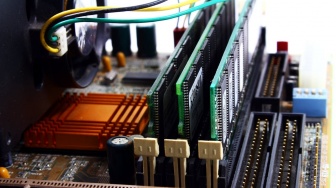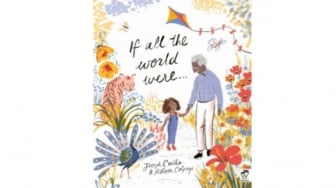Pernahkah Anda merasa tenggorokan gatal saat menunggu bus yang tak kunjung datang di pinggir jalan Jakarta? Atau mata perih karena harus menembus kabut asap kendaraan pribadi yang menderu-deru seperti parade ego di pagi hari? Jika ya, selamat, Anda baru saja merasakan aromaterapi perkotaan versi Indonesia: campuran karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan sedikit frustrasi sosial.
Transportasi di negeri ini tak ubahnya seperti sinetron kejar tayang: dramatis, tidak konsisten, dan bikin emosi. Di satu sisi, pemerintah menggelontorkan wacana transisi energi bersih dan kendaraan listrik (EV). Di sisi lain, SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum) masih seperti unicorn—katanya ada, tapi susah ditemui. Apalagi kalau Anda tinggal di luar Jakarta, selamat menikmati keajaiban: listrik belum tentu stabil, apalagi bisa ngecas mobil.
Emisi sektor transportasi di Indonesia menyumbang 202 juta ton CO pada tahun 2024. Itu 27% dari total emisi energi nasional. Dan jika tak ada langkah konkret, angka itu bisa melonjak tiga kali lipat pada 2060. Kita sedang menari di atas bom waktu iklim, dengan musik latar dari deru knalpot dan derita paru-paru.
Namun mengapa langkah dekarbonisasi sektor transportasi terasa seperti bersepeda menanjak tanpa rantai? Mari kita uraikan benang kusutnya: dari uang, udara, hingga jalan raya.
Transportasi Publik: Antara Mimpi Urban dan Mimpi Buruk Warga
Transportasi publik di kota besar kita ibarat tamu undangan yang datang terlambat ke pesta: niatnya baik, tapi bikin semua orang keburu pulang. Konektivitas antarmoda seperti KRL, MRT, LRT, dan TransJakarta masih belum sepenuhnya sinkron. Menyambung dari satu moda ke moda lain kadang lebih rumit daripada menyambung Wi-Fi di rumah kos.
Jakarta boleh bangga dengan MRT, tapi coba tanya warga Bekasi atau Depok yang masih harus naik ojek dulu untuk sampai ke stasiun terdekat. Di luar Jawa? Ceritanya lain lagi. Di Medan, Palembang, atau Makassar, transportasi publik masih kalah pamor dengan motor kredit 0% bunga.
Menurut Liu et al. (2023), kendaraan pribadi menyumbang 41–74% emisi karbon sektor transportasi di banyak kota dunia. Artinya, semakin tinggi ketergantungan pada mobil dan motor pribadi, semakin sesak paru-paru kota. Tapi mengapa orang tetap memilih kendaraan pribadi? Karena transportasi publik kita masih sering telat, penuh, dan bau keringat yang bisa menyaingi senjata kimia.
Ironisnya, mobil pribadi yang cuma diisi satu orang diberi karpet merah di jalan tol, sementara bus yang memuat puluhan justru terjebak macet di luar tol. Ini bukan sekadar soal infrastruktur, tapi juga filosofi mobilitas yang kebolak-balik: siapa yang mengangkut lebih banyak orang, justru harus lebih menderita.
Mobil Listrik: Listriknya Maju, Casnya Mundur
Subsidi motor listrik sempat ramai dibicarakan, kemudian ditangguhkan. Alhasil, penjualan EV menurun drastis dalam enam bulan terakhir. Pemerintah berdalih karena data pembelian tidak transparan, tapi masyarakat membaca sinyal lain: komitmen negara terhadap transisi energi masih se-flicker lampu jalan rusak.
EV (Electric Vehicle) memang menarik di atas kertas. Emisi lokalnya nol, suara mesinnya halus, dan katanya keren. Tapi pertanyaan paling esensial masih menggantung: "Ngecas di mana, bos?"
Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) jumlahnya masih bisa dihitung dengan jari. Bahkan di Jakarta, yang katanya kota futuristik, mencari SPKLU lebih sulit daripada mencari tempat parkir gratis. Belum lagi waktu pengisian yang masih lama. Bayangkan Anda harus menunggu satu jam untuk mengisi daya mobil, sementara di warung sebelah, motor bensin sudah pergi pulang tiga kali.
Bukan hanya itu, mayoritas listrik di Indonesia masih bersumber dari batu bara. Jadi kalau EV Anda ngecas pakai listrik dari PLTU, itu bukan "kendaraan ramah lingkungan" tapi "kendaraan bertenaga batubara."
Zhao et al. (2025) menyatakan bahwa urbanisasi dan peningkatan pendapatan mendorong kepemilikan mobil, dan pada akhirnya memperbesar jejak karbon. Tapi kalau infrastruktur EV tidak dibenahi, maka yang akan kita hasilkan bukan dekarbonisasi, melainkan "deceit-carbonisasi": terlihat hijau, tapi sesungguhnya abu-abu pekat.
Kebijakan Tanpa Orkestra: Simfoni Gagap Antar Sektor
Masalah besar dekarbonisasi transportasi di Indonesia adalah orkestrasi kebijakan yang tidak harmonis. Sektor transportasi jalan sendiri, sektor energi sibuk dengan PLTU baru, sementara sektor ekonomi masih menghitung subsidi BBM.
Padahal, kebijakan ini ibarat membangun rumah. Kalau atap dipasang duluan tapi fondasi belum siap, yang ada rumahnya ambruk saat hujan pertama turun.
Kementerian Perhubungan ingin mendorong EV, tapi Kementerian ESDM belum siap dengan jaringan pengisian daya. Sementara Kementerian Keuangan masih memelihara subsidi BBM yang besarnya bisa menyaingi APBN sebuah negara kecil. Pemerintah seperti sedang membangun jembatan bersama, tapi setiap kementerian membawa peta yang berbeda.
Dan jangan lupakan DPR—yang kadang lebih sibuk memikirkan revisi Undang-Undang yang tak mendesak ketimbang merumuskan undang-undang pendukung transisi energi. Hasilnya, rakyat kebingungan: apakah harus beli EV, tunggu subsidi, atau tetap setia pada motor Supra X?
Chen et al. (2023) mencatat bahwa emisi lebih tinggi di daerah dengan infrastruktur publik terbatas dan preferensi tinggi terhadap kendaraan pribadi. Ini membuktikan bahwa tanpa intervensi regulasi yang tegas dan terpadu, dekarbonisasi hanyalah jargon indah yang melayang seperti asap dari knalpot bus tua.
Dari BBM ke Oksigen: Potensi dan Harapan di Tengah Kabut
Jika transisi ke transportasi rendah karbon dijalankan dengan serius, manfaatnya bukan main-main. Mulai dari mengurangi subsidi BBM (yang sering bocor ke tangan yang salah), hingga membuka lapangan kerja baru di sektor teknologi dan energi terbarukan.
Bayangkan saja: anak-anak lulusan teknik elektro bisa bekerja mengembangkan baterai EV alih-alih jadi YouTuber prank. Atau pengusaha kecil bisa menjual layanan konversi motor bensin ke listrik dengan harga terjangkau. Industri ini punya potensi besar, tapi perlu ditopang oleh arah kebijakan yang tidak plin-plan dan seragam lintas sektor.
Menurut studi Bank Dunia, biaya kesehatan akibat polusi udara bisa mencapai USD 43 miliar per tahun pada 2030. Jika itu bisa ditekan dengan memperbaiki kualitas udara lewat transisi transportasi, maka kita bukan hanya menyelamatkan paru-paru rakyat, tapi juga anggaran negara.
Tapi tentu saja, perubahan ini tidak bisa hanya bertumpu pada teknologi. Harus ada perubahan budaya dan perilaku. Rakyat harus diyakinkan bahwa naik bus bukan tanda kemiskinan, tapi pilihan rasional dan etis. Bahwa EV bukan hanya gaya hidup elite, tapi solusi kolektif.
Dan yang paling penting: pemerintah harus menunjukkan keteladanan. Jika pejabat publik masih berkonvoi dengan mobil berbahan bakar premium yang dijaga mobil patwal, maka pesan dekarbonisasi tak lebih dari sandiwara karbonisasi.
Jalan Panjang Menuju Kota Tanpa Knalpot
Mengurai tantangan dekarbonisasi transportasi memang tidak mudah. Kita sedang berhadapan dengan sistem yang kompleks, tumpang tindih, dan kadang malas berubah. Tapi justru karena kompleks, perubahan tidak boleh ditunda.
Uang bukan masalah jika dialokasikan dengan bijak. Udara bukan milik satu kementerian, tapi hak semua warga. Dan jalan raya bukan hanya tempat kendaraan melintas, tapi cermin dari arah kebijakan negeri ini.
Kalau pemerintah serius, langkah kecil seperti membenahi integrasi antarmoda, menambah SPKLU, dan menghentikan subsidi BBM bisa membawa dampak besar. Tapi kalau tidak? Maka kita akan terus menghirup polusi sambil menunggu janji-janji hijau yang tak kunjung nyata.
Seperti kata pepatah masa kini: "Kalau hidupmu terasa berat, mungkin karena kamu tinggal di kota yang penuh karbon, bukan harapan."