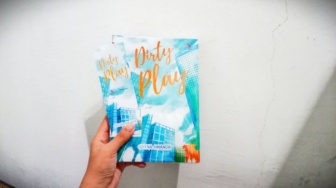Euforia merayakan hari kemerdekaan bukan hanya soal terbebas dari penjajahan kolonialisme. Di era digital seperti dewasa ini, kita belum selesai untuk terbebas dari kooptasi penindasan dalam kemasan yang berbeda.
Ada bentuk penjajahan baru yang diam-diam menggerogoti masa depan: eksploitasi manusia atas alam. Polusi udara yang kian pekat menyesaki kota, hutan yang menyusut dirampas ekskavator, laut yang penuh sampah plastik dan bibir pantai yang direklamasi, hingga cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi, semua menjadi tanda bahwa bumi kita sedang berteriak.
Bagi Generasi Z, atau mereka yang lahir setelah 1997, fenomena krisis iklim bukanlah sekedar teori yang hanya dicatat di buku pelajaran. Banjir bandang, kekeringan, dan kabut asap adalah pengalaman langsung yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Survei di Amerika Serikat menunjukkan sepertiga Gen Z khawatir harus pindah dari kota asal akibat dampak perubahan iklim.
Di Indonesia, sekitar 80% kesadaran kognitif Gen Z perkotaan terhadap isu ini sangat tinggi. Namun, kepekaan ini belum sepenuhnya sejalan dengan kemauan mengambil sikap dan bertindak. Korelasi antara pengetahuan dan komitmen aksi masih minim dan menandakan ada jarak antara rasa tahu dan rasa mau bergerak.
Jarak itu harus kita jembatani. Sebab, tanpa aksi, kesadaran hanya menjadi modal yang terbuang. Riset menunjukkan bahwa framing pesan yang terlalu fokus pada bencana dapat memunculkan rasa tidak berdaya, sementara framing positif yang menekankan solusi dan keberhasilan justru mendorong keterlibatan. Di sinilah pentingnya mengemas pesan lingkungan sebagai ajakan yang penuh harapan, bukan sekadar kabar buruk.
Gen Z memiliki dua modal besar antara literasi digital dan kapasitas berpikir kritis. Media sosial memberi mereka ruang untuk bersuara, menggalang dukungan, dan menyebarkan informasi.
Komunitas seperti Climate Rangers, dan Youth for Climate Change telah memanfaatkan ruang digital untuk edukasi dan kampanye. Namun, tantangannya adalah memastikan gerakan ini melampaui clicktivism dari sekadar share dan like menjadi aksi nyata di lapangan.
Perjuangan lingkungan juga adalah perjuangan keadilan. Keadilan iklim berarti kebijakan yang melindungi kelompok rentan: pelajar di pesisir yang sering kehilangan waktu belajar karena banjir, petani yang gagal panen akibat kekeringan, hingga penyandang disabilitas yang jarang dilibatkan dalam perencanaan kebijakan. Lebih dari 60 persen Gen Z di Jakarta menilai pemerintah belum serius menangani krisis iklim. Pelibatan generasi muda masih sering sekadar formalitas, bukan keterlibatan bermakna.
Kemerdekaan untuk bumi berarti kemerdekaan dari sistem ekonomi dan politik yang mengabaikan keberlanjutan. Bagi sebagian Gen Z, melawan dimulai dari dompet seperti memeriksa kebijakan lingkungan perusahaan sebelum membeli produk, menghindari fast fashion, mengurangi penerbangan, mengubah pola makan, atau beralih ke kendaraan listrik. Di dunia kerja, mereka bahkan siap meninggalkan perusahaan yang tidak punya strategi net-zero yang jelas.
Indonesia menargetkan menjadi negara maju pada 2045, ketika Gen Z berada di puncak produktivitasnya. Namun, laporan IPCC memperingatkan bahwa pada 2050 suhu bumi akan naik hingga 2,6 derajat celcius dibanding 1990, dan permukaan laut naik hingga 32 cm. Tanpa aksi serius, “Indonesia Emas” bisa berubah menjadi “Indonesia Panas” bukan hanya secara ekonomi, tetapi secara harfiah.
Maka, tugas kita hari ini adalah mengubah kesadaran menjadi keberanian. Keberanian untuk mengubah gaya hidup, menekan kebijakan publik, membangun solidaritas lintas generasi, dan tidak menyerah pada rasa putus asa.
Kemerdekaan yang diwariskan para pendiri bangsa harus kita isi dengan perjuangan baru yaitu memastikan bumi tetap layak huni untuk generasi mendatang. Karena pada akhirnya, merdeka untuk bumi berarti merdeka untuk masa depan. Dan masa depan itu adalah warisan yang tidak boleh kita gadaikan.