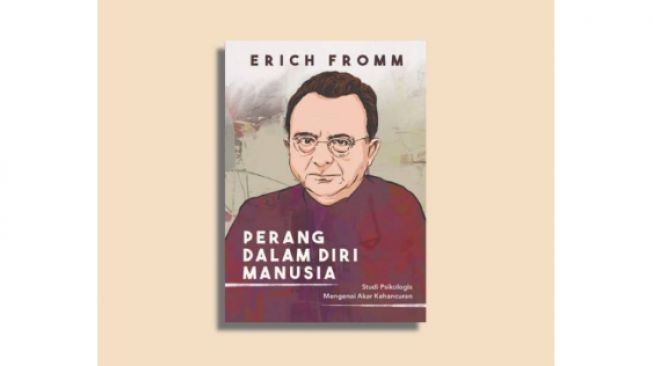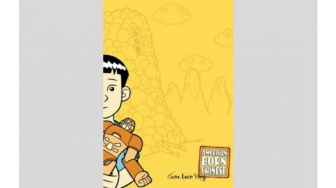Apa yang akan kita pikirkan ketika mendengar kata perang? Prosesi atau pemusnahan sekelompok orang atau konflik dua kubu yang merenggut jutaan korban? Melihat sejarah umat manusia di banyak bangsa dan negara, bayangan dua hal tadi mungkin menjadi hal yang terpikirkan sewaktu kita mendengar kata perang. Itu benar belaka. Namun, dua hal tadi akan lebih tepat kalau kita menyebutnya sebagai dampak dari peperangan. Sementara perang dalam artian lain, seperti perang dalam diri manusia, justru jarang kita singgung. Persoalan inilah yang diketengahkan oleh Erich Fromm di bab pertama bukunya, Perang dalam Diri Manusia (IRCiSoD, 2020).
Awalnya, buku ini sebenarnya sebuah jurnal yang berjudul “Sebab-Sebab Psikologis Perang”, lalu atas beragam pertimbangan setelah diadakan diskusi dengan pakar lainnya, judul itu berganti dengan “Perang Dalam Diri Manusia”. Dari sebuah jurnal, telaah itu kini hadir sebagai buku yang berisi telaah psikoanalis terhadap fenomena perang.
Hal yang disoroti Erich sebenarnya bisa dibagi menjadi dua bagian utama. Pertama, ia menelaah kecenderungan dua sifat manusia yang diibaratkan sebagai serigala dan domba. Mulanya, istilah ini datang dari seorang filsuf atau pemikir bernama Hobbes. Lelaki ini mengenalkan istilah “homo homini lupus” yang artinya manusia adalah serigala bagi manusia yang lainnya. Pemahaman ini kemudian menjadi pijakan awal bagi Erich untuk mengelaborasi temuannya. Di bagian kedua, ia mengetengah dua dikotomi dari kecenderungan hasrat umat manusia.
Dua Dikotomi
Pernahkah terpikirkan oleh kita, mengapa orang bisa begitu teganya membunuh sekelompok orang secara massal dalam sebuah perang? Tentu, pertanyaan ini bukan barang baru. Sebab, bertahun-tahun yang lampau, Erich Fromm pun penasaran akan hal ini. Ia lantas menelaahnya, mencari sebab-sebabnya dengan pondasi ilmu psikologi yang dimiliki.
Dari telaahnya, Erich menemukan dua orientasi manusia dalam koridor ini, yakni nekrofilia (Cinta kematian) dan biofilia (Cinta kehidupan). Secara singkat, dua dikotomi ini bisa dipahami sebagai ketertarikan sifat manusia untuk bertindak destruktif atau merusak, dan ketertarikan untuk bertindak konstruktif atau membangun. Kendati begitu, Erich tidak mengetengahkan dua dikotomi tersebut secara hitam-putih. Ia menggarisbawahi bahwa kebanyakan orang adalah percampuran tertentu orientasi nekrofilus dan biofilus, dan persoalannya adalah mana di antara dua kecenderungan ini yang dominan (Hal. 87).
Bila yang dominan adalah sisi nekrofilusnya, maka itu menjadi salah satu alasan mengapa setiap tindakannya melulu berhasrat merusak, menghancurkan, atau bahkan membunuh kelompok lain. Penjelasan ini tentu tidak begitu saja bisa ditelan mentah-mentah, sebab telaah Erich sebatas pada pandangan terkait kondisi perang demi perang yang terjadi sepanjang hidupnya. Ia berpendapat, kecenderungan nekrofilus ini tergambarkan dalam figur Hitler.
Di mata Erich, sosok Hitler digambarkan sebagai pribadi yang terpikat dengan perang, penghancuran, dan bau kematian manis yang baginya. Jika di tahun-tahun gemilang dia hanya ingin menghancurkan yang dirinya anggap musuh. Dalam perjalanannya, dia memperlihatkan bahwa kepuasan paling dalam adalah saat menyaksikan penghancuran total dan absolut; yaitu rakyat Jerman, orang-orang di sekitarnya, bahkan dirinya sendiri (Hal. 16)
Lebih jelas lagi, di mata orang-orang dengan sisi nekrofilus yang lebih dominan seperti Hitler ini, menghapus kehidupan kelompok lain bisa dipahami sebagai kesenangan.
Apakah benar demikian? Erich tidak menutup diri atas pelbagai tanggapan dari pakar lain. Sementara itu, sadar bahwa telaahnya tidak semestinya ditelan mentah-mentah, maka ia mengundang pakar lain untuk memberi ulasan atas telaah dalam makalahnya itu. Dua kritik utama lantas datang dari Hans. J. Morgenthau dan Paul Tillich.
Hans berpendapat, perang jangan dipahami secara psikologis, tetapi sebagai fenomena politik saja. Pandapat ini diperkuat dengan gagasan Paul bahwa perang disebabkan oleh perjumpaan struktur-struktur kekuasaan, agen sejarah dan dinamikanya. Akhirnya, ihwal perang tidak cukup dinilai dari sudut pandang sisi psikologis pelakunya saja.
Kendati begitu, telaah Erich bukan berarti tidak penting sama sekali, sebab ia mengharapkan akan dilakukannya penelitian lain di bidang psikologis dengan bukti-bukti empiris untuk menguatkannya. Dari situ, penemuan Erich bisa dipahami sebagai pijakan bagi penelitian-penelitian lain yang mengetengahkan persoalan kemanusian dari sisi psikologi dan psikoanalis sosial. Tindakan itu tentu patut dipertimbangkan, sebab memahami kompleksitas perilaku dalam sebuah perang sama artinya dengan mengupayakan terciptanya kedamaian umat manusia.