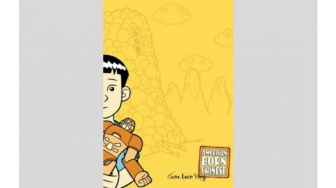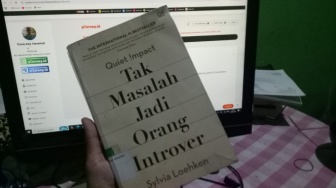Konflik di Wadas akhir-akhir ini menjadi sorotan baik di media sosial, laman berita maupun diskusi-diskusi di masyarakat, dan kalangan mahasiswa. Konflik di Wadas erat kaitannya dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bener yang akan dibangun. Masyarakat Wadas sendiri tidaklah menolak kehadiran bendungan tersebut, bahkan sebagian mendukungnya. Namun, permasalahan timbul ketika material yang akan digunakan untuk membangun bendungan tersebut diambil dari Desa Wadas. Konflik di desa Wadas bukanlah mengenai konflik penolakan warga Wadas terhadap pembangunan bendungan, melainkan konflik pengadaan tanah di Desa Wadas untuk penambangan andesit.
Penambangan andesit bertujuan sebagai bahan material pembangunan Bendungan Bener. Konflik yang terjadi di Desa Wadas merupakan konflik agrarian karena menyoal pengadaan tanah. Konflik Wadas menjadi polemic karena beberapa pihak seperti pemerintah dan pemangku kepentingan menganggap pengadaan ini sudah sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Selain itu, tindakan gegabah pemerintah yang mengerahkan aparat kepolisian guna merespon aksi protes warga, ditambah aparat tersebut melakukan aksi represif turut menambah permasalahan.
Dikutip dari jurnal berjudul Konflik Agraria di Desa Wadas: Pertimbangan Solusi, sikap pemerintah bersikukuh mempertahankan proyek penambangan ini dikarenakan: (1) Penambangan andesit menjadi penunjang pembangunan bendungan; (2) Pembangunan bendungan sendiri merupakan Proyek Strategi Nasional (PSN); (3) Bendungan akan digunakan untuk kepentingan umum terutama pengairan sawah guna mencapai ketahanan pangan. Warga Wadas menolak dengan beberapa alasan: (1) Kawasan Wadas belum pernah menjadi kawasan tambang; (2) merusak lingkungan dan dapat menyebabkan bencana seperti tanah longsor; (3) tidak sesuai dengan aturan mengenai tata kelola lingkungan.
Pakar hukum dan lingkungan UGM, I Gusti Agung Made menilai akar dari konflik Wadas adalah perbedaan cara pandang kedua belah pihak terkait tanah. Pemerintah menilai tanah di Wadas dari segi ekonominya, artinya hanya melakukan ganti rugi maka permasalahan selesai. Tetapi, warga Wadas tidak memandang demikian, Warga memandang tanah mengandung nilai sosial, budaya dan spiritual. Selain itu, antara penambangan dan pembangunan proyek ini sendiri juga merupakan dua hal yang seharusnya terpisah, bukan menjadi satu.
Masyarakat desa dengan kehidupannya yang sejahtera memang memiliki pemaknaan yang mendalam terhadap tanah. Secara hsitoris, untuk memberikan gambaran menganai cara pandang tanah maka akan digambarkan pemaknaan tanah oleh masyarakat mengalami perkembangan dari masa ke masa. Merujuk pada buku berjudul Negara dan Kekuasaan di Jawa Abad XVI-XIX pada masa feodalisme tradisional Jawa misalnya, tanah tidak terlalu dihargai, tetapi manusia yang menggarap tanah itu lah yang dihargai. Feodalisme berpandangan bahwa tanah tak akan menghasilkan kalau tak diolah oleh rakyat pekerja.
Cara pandang feodalisme ini kurang tepat untuk menganalisis pemaknaan masyarakat terutama masyarakat desa terhadap tanah mengingat pelaku dominan dalam feodalisme adalah golongan priyayi (tuan tanah, bangsawan, priyayi). Tanah dalam pandangan feodalisme juga dimiliki oleh para pembesar, bukan rakyat kebanyakan yang berstatus penggarap lahan. Namun, dalam sisi yang lain, feodalisme memberikan pandangan bahwa tanah memiliki ikatan ekonomi agraris (pertanian, dll) dengan masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kehidupan masyarakat desa meskipun di bawah feodalisme memiliki beberapa ciri khas yang unik seperti bersifat otonom, mandiri, tertutup dan demokratis.
Tanah meskipun dikuasai oleh tuan tanah, pada kenyataanya masyarakat desa lah yang memanfaatkanya. Tuan tanah hanya meminta sepersekian sebagai pajak. Jika ditilik dari gambaran masa feodalisme pun, masyarakat desa sejatinya memiliki ikatan pemanfaatan kuat dengan tanah guna memenuhi kebutuhannya. Masyarakat desa yang telah mampu bersifat mandiri, cenderung tertutup karena jarang berinteraksi dengan pihak di luar desa, dengan alasan kebutuhan mereka sudah terpenuhi.
Perubahan terjadi pada tahun 1870-an (UU Agraria 1870) dan awal Politik Etis. Dalam buku Ekonomi Politik Kolonialisme: Perspektif Kebijakan Ekonomi Politik Pemerintah Hindia Belanda dalam Mengelola Industri Gula Mangkunegaran pada Tahun 1870-1930 menjelaskan pada masa ini terjadi perubahan kepemilikan tanah di mana tanah-tanah milik bangsawan dialihkan kepemilikannya menjadi individu dan hak kelola desa. Meskipun, sebelum adanya perubahan ini pun hak kelola tanah juga lebih sering dikelola secara komunal. Perbedaan hanya terletak kepada pemilik tanah tersebut di mata hukum. Namun, pada masa ini pula perusahaan bercorak kapitalisme berkembang dan memanfaatkan keadaan.
Tanah yang tersedia di desa dengan jumlah penduduk tidak sebanding, pada akhirnya tanah yang dimiliki perindividu sangat kecil, belum lagi harganya menjadi lebih murah. Menyempitnya tanah garapan tidak sebanding dengan pajak yang harus dibayarkan dalam bentuk uang tunai, terpaksa pemilik tanah menjual tanahnya kepada perusahaan swasta dengan harapan dapat mendapatkan uang tunai dan bekerja sebagai buruh perusahaan. Peralihan hak tanah ini kemudian memberikan pandangan bagaimana kapitalisme memandang tanah, bukan dari segi manfaatnya bagi masyarakat desa, melainkan nilai ekonomisnya (harga tanahnya).
Secara kultur atau budaya, tanah memiliki ikatan kebudayaan tersendiri dengan masyarakat desa. Adanya ketergantungan warga Desa terhadap tanah sebagai sumber penghidupan membuat tanah menjadi sesuatu yang patut dipertahankan. Ada sebuah ungkapan Jawa yang dapat menggambarkan situasi ini. pepatah itu berbunyi sedumuk batuk senyari bumi ditohi pati artinya kurang lebih isteri dan tanah jika diganggu akan dilawan meskipun nyawa taruhannya. Hal ini selaras dengan kegigihan warga Wadas dalam mempertahankan hak nya atas tanahnya sendiri. Kultur masyarakat desa, tak terkecuali masyarakat Wadas menempatkan tanah sebagai sumber kehidupan. Mereka sangat tergantung dengan tanah dan selama puluhan tahun mereka hidup berkecukupan dengan mengandalkan hasil bumi.
Di sisi lain, masyarakat Wadas sama seperti masyarakat desa lainnya hidup dalam kesejahteraan yang cukup dengan kehidupan yang sederhana. Kultur berpikir mereka tentunya bertentangan dengan kultur pemikiran kapitalisme yang rasionalistik dan postivistik, di mana memandang manusia dapat mengendalikan alam sepenuhnya. Kultur jenis ini lah yang dibawa oleh pemerintah dalam penambangan andesit. Pemerintah beralasan penambangan tidak merusak lingkungan secara total dan mereka juga menawarkan solusinya seperti eko-wisata.
Dalam jurnal Kapitalisme, Krisis, Ekologi dan Keadilan Intergenerasi: Analissi Kritis atas Problem Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia menuliskan pada kenyataanya, cara berpikir kapitalisme akan berujung pada eksploitasi dan banyak terjadi kasus serupa justru berujung kerusakan lingkungan yang tidak berkesudahan dan memiliki efek domino. Misalnya proyek food estate era Orde Baru dalam Repelita justru menjadi penyumbang pembabatan hutan yang berakibat pada rusaknya ekosistem dan menyumbang gas karbon. Hal ini kemudian ditambah bahwa kapitalisme berorientasi dengan pertumbuhan ekonomi.
Jika dilihat dalam sejarahnya terutama masa Orde Baru maka terlihat dengan jelas banyak program yang mengatasnamakan “proyek nasional” sejatinya hanya untuk menumbuhkan ekonomi semata dan memarjinalkan kemakmuran rakyat. Jika dilihat dalam proyek PSN Bendungan Bener, maka pengairan tidak hanya ditujukan untuk perswahan, melainkan juga untuk NYIA (New Yogyakarta International Airport) dan Industri di 10 kecamatan. Sudah umum diketahui bahwa kebutuhan air untuk industri dan bandara yang beroeintasi profit tentunya lebih besar daripada kebutuhan warga sekitar.
Adanya corak budaya berpikir kapitalisme yang antropofistik maka menjadikan sumber daya alam hanya dikelola oleh manusia. Budaya Kapitalisme yang lain seperti mengutamakan efisiensi pengeluaran tetapi melupakan kehidupan di dalamnya. Kehidupan yang ada di desa Wadas tidak hanya mengenai kehidupan manusia, melainkan kehidupan satwa yang terancam eksistensinya jika penambangan dilakukan. Dampak dari penambangan juga turut menjadi perhatian, pasalnya banyak peristiwa penambangan serupa meninggalkan bekas galian yang dibiarkan begitu saja.
Pemerintah memang menawarkan komitmen dan solusi seperti mereklamasi dan menjadikannya ekowisata, tetapi peristiwa serupa yang telah terjadi cukup memberikan gambaran mengenai upaya pemerintah dalam merehabilitasi bekas tambang. Penambangan jika dilakukan di desa Wadas juga akan berakibat pada kerusakan alam yang berujung pada bencana seperti kerusakan lahan dan tanah longsor. Berbagai dampak tersebut tentunya kelak akan mempengaruhi kehidupan Warga Wadas.
Abainya pemerintah dalam melihat kehidupan dalam desa Wadas serta dampaknya pada masa depan disebabkan pemerintah kurang memperhatikan kaitan antara tanah dan kehidupan. Pemerintah tidak memahami bagaimana cara berpikir intergenerasi dalam merawat alam, padahal pemikiran ini dipahami betul oleh Warga Wadas.
Pemikiran Intergenerasi mengatur bagaimana generasi sekarang dapat meninggalkan kondisi kehidupan yang sama untuk generasi selanjutnya. Pemerintah lupa bahwa kehidupan agraris di Desa Wadas merupakan kehidupan yang sudah mapan yang sudah tentu dapat diwariskan kepada generasi sesudahnya.
Ditambah dalam kehidupan sosial di desa Wadas didasari pada ikatan komunal (seduluran) sehingga mereka memiliki rasa tanggung jawab membela tanah mereka karena kesamaan budaya dan sejarah. Hal ini berbeda dengan permasalahan lahan di perkotaan yang dengan mudah diselesaikan melalui mekanisme ganti rugi lahan. Masyarakat perkotaan tidak memiliki ikatan komunal, mereka juga tidak memiliki pemikiran intergenerasi dan mereka juga tidak bergantung kehidupan dengan tanah.
Persoalan Wadas menjadi polemik yang belum usai. Banyak yang belum mengetahui akar permasalahan dari konflik ini. Penyelesaian seperti ganti rugi lahan pun belum menjadi solusi yang tepat. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan pandangan antara pemerintah dan warga Wadas dalam memandang tanah.