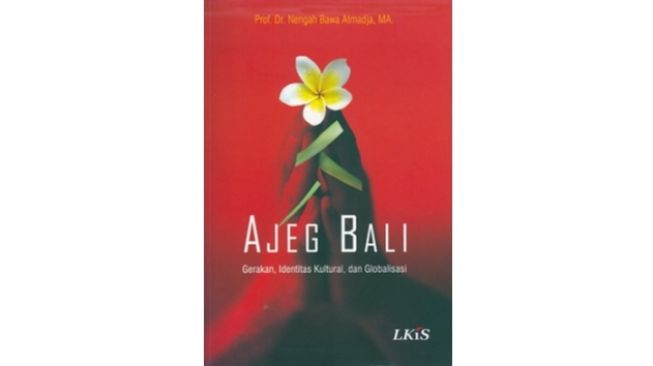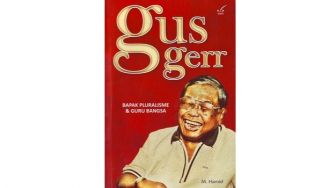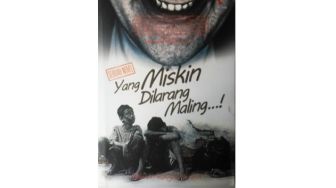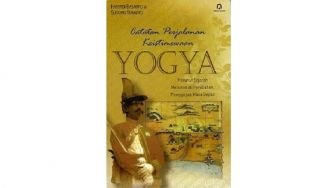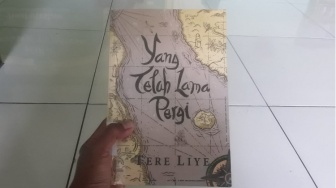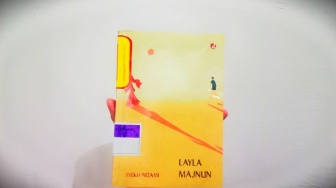Bali menjadi salah satu pulau di Indonesia yang eksotis sekaligus menyimpan banyak misteri. Sejumlah antropolog Barat dalam karya etnografisnya menggambarkan pulau Bali dengan penuh pesona dan gairah, dikarenakan relasi sinergis antar masyarakat lokal Bali, agama, serta keindahan alamnya sebagai corak khas kebudayaan Bali. Namun, Bali sedang mengalami pengikisan budaya serta identitas. Globalisasi telah masuk, mulai menggerus pesona dan daya sakral pulau Dewata itu.
Dalam konteks demikian, Prof. Nengah dalam buku Ajeg Bali: Gerakan, Identitas Kultural, dan Globalisasi ini merajut benang korelasi antara Bali, tradisi lokal, dengan globalisasi. Buku setebal 550 halaman ini mencoba menguak seluk-beluk pulau Dewata yang mana telah diklaim memiliki corak negatif oleh khalayak pada umumnya
Menurut Prof. Nengah, akar pemicu pergolakan kebudayaan Bali bermula ketika rezim Orde Baru menetapkan kebijakan pembangunan ekonomi melalui sektor pariwisata. Dalam waktu relatif cepat, pariwisata tumbuh dan berkembang di pulau Dewata ini. Pelbagai lahan pertanian beralih guna menjadi tempat wisata.
Parahnya, berbagai kawasan wisata yang terdapat di pulau Dewata itu seperti Denpasar, Kuta, Sanur, dan Badung dipenuhi oleh reklame yang carut-marut serta dihuni oleh berbagai wisatawan asing dengan membawa semangat yang tidak sesuai dengan khazanah lokal kebudayaan Bali. Di sekeliling kawasan wisata itu pula dipenuhi kafe-kafe temaram yang berfungsi sebagai media transaksi harga diri. Maka kisah industri seks di pulau Dewata bukan lagi menjadi mitos belaka (halaman 171-248).
Tentu kita masih ingat ketika dirilisnya film dokumenter ihwal lelaku gigolo di kawasan pantai Kuta oleh Amit Virmani (Cowboys in Paradise) yang sempat menyulut api kontroversi pelbagai pihak. Namun ternyata tidak sedikit pula pelbagai kalangan yang diam-diam mengamini bahwa pulau Dewata kini telah mengalami penggerusan budaya oleh Globalisasi.
Menurut penelusuran Prof. Nengah, terjadi pergelutan memanas antara etnisitas masyarakat lokal Bali dengan para pendatang. Posisi para pendatang yang semula di pinggiran, kini mulai mendominasi sektor perekonomian di kawasan pariwisata yang cukup strategis. Sehingga kondisi tersebut menimbulkan berbagai ketegangan yang serius (hlm. 336).
Secara keseluruhan buku ini layak untuk diapresiasi, meskipun telah banyak buku-buku yang mengkaji dan menelaah tentang pulau Bali, seperti Sisi Gelap Pulau Dewata; Sejarah Kekerasan Politik (2006); dan Bali yang Hilang (2008), buku ini tetap memberi corak warna baru dan perspektif yang berbeda. Salah satu hal yang ingin diungkapkan penulis buku adalah bahwa nilai-nilai tradisi Bali merupakan kesatuan komitmen yang bersemayam pada masanya, bukan sesuatu yang nir-konflik, melainkan suatu tatanan yang aktif dan dinamis serta terus melibatkan diri dalam tatanan nilai global seiring dengan kebutuhan masyarakat Bali masa kontemporer.