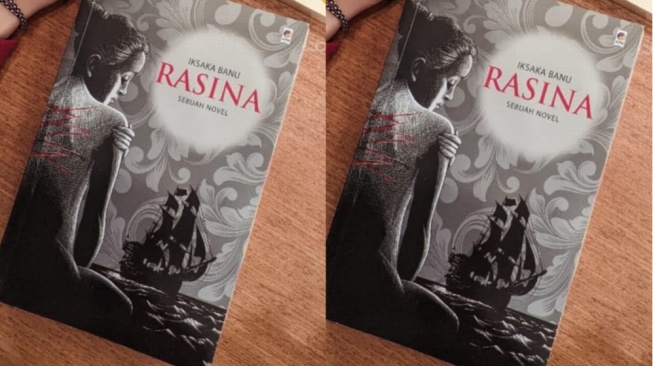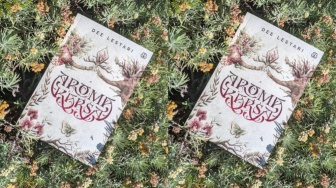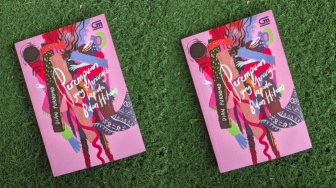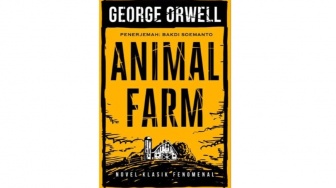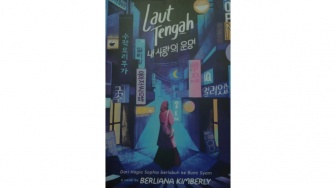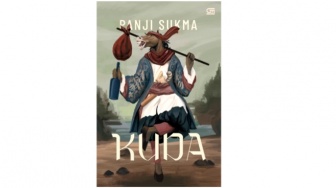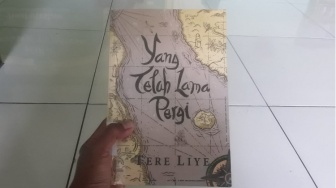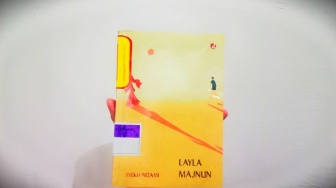Novel Rasina karya Iksaka Banu adalah sebuah novel fiksi sejarah yang ditulis dengan dua latar yang berbeda, tidak hanya mendokumentasikan periode kelam kolonialisme VOC tetapi juga menempatkan trauma sejarah dalam konteks konflik pribadi yang cukup intens.
Iksaka Banu dikenal sebagai penulis yang konsisten mengangkat isu-isu kolonialisme dengan perspektif kritis dan analitis, sebuah karakteristik yang kental dalam karya-karyanya.
Novel Rasina, yang terbit pada tahun 2023, memperkuat posisinya sebagai penulis yang mampu menyajikan narasi sejarah yang kompleks melalui medium fiksi.
Novel Rasina dibangun dengan dua latar waktu yang sangat signifikan. Novel ini menggunakan latar ganda yaitu kehidupan di sekitar Kota Tua Jakarta, Kaastel Batavia, Ommelanden, dan Weltevreden pada pertengahan abad ke-18 (tahun 1755), dan kilas balik yang mendasar ke tragedi Kepulauan Banda pada tahun 1621.
Latar utama tahun 1755 menggambarkan masa ketika Kompeni Hindia Timur (VOC) telah melewati masa kejayaannya. Periode ini diwarnai banyak peristiwa, di mana pejabat Kompeni secara aktif menumpuk harta melalui korupsi dan perdagangan gelap, termasuk penyelundupan budak dan opium.
Dalam pusaran korupsi inilah, petugas hukum Batavia, Jan Aldemaar Staalhart dan Joost Boorsveld, menemukan diri mereka terlibat dalam penyelidikan arus perdagangan ilegal yang melibatkan orang-orang penting berkekuasaan besar.
Namun, akar penderitaan tokoh utama Rasina tertanam jauh di masa lalu, yaitu pada peristiwa penting di Banda tahun 1621.
Latar pada novel ini merujuk pada pembantaian massal penduduk Banda oleh Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen, yang tujuannya adalah memonopoli perdagangan pala.
Rasina merupakan keturunan dari korban pembantaian massal tersebut. Ia adalah seorang budak bisu yang juga berfungsi sebagai pelayan rumah tangga dan budak nafsu tuannya. Meskipun digambarkan lemah atau penakut, dia menyimpan harapan yang kuat untuk bebas dari siksaan.
Novel ini menggunakan sudut pandang orang pertama. Meskipun temanya berat, gaya bahasa yang digunakan Iksaka Banu digambarkan sederhana, mudah dimengerti, dan biasa diucapkan sehari-hari.
Struktur alur digambarkan seimbang (tidak terlalu cepat atau lambat), dengan plot yang saling melengkapi. Pilihan bahasa yang sederhana ini krusial.
Aksesibilitas narasi memungkinkan tema berat tentang trauma dan perbudakan mencapai audiens yang lebih luas, sehingga novel ini dapat berfungsi sebagai kritik sosial yang efektif dan mendorong refleksi sosial.
Bentuk-bentuk penindasan yang detail dan brutal (fisik, verbal, ekonomi) dalam novel ini secara gamblang mencerminkan ketimpangan kekuasaan kolonial.
Namun, novel ini juga menawarkan pandangan optimis melalui penggambaran perlawanan aktif dan harapan Rasina untuk kebebasan dan mendapatkan keadilan atas perlakuan buruk dari para tuannya yang tidak sesuai dengan hukum dan undang-undang Kompeni.
Perlawanan Rasina juga mencakup upaya untuk menegaskan hak-haknya. Novel ini menunjukkan upaya kuat untuk melapor ke pihak berwenang.
Tindakan ini, meskipun hasilnya tidak terjamin, adalah klaim atas haknya sebagai manusia yang menantang sistem yang memperlakukannya sebagai binatang bukan manusia.
Kisah hidup Rasina dlam novel ini dirancang untuk memberikan banyak pembelajaran, dan mendorong pembaca untuk memperjuangkan hidup melawan keserakahan yang langgeng, serta untuk selalu berpihak pada kemanusiaan.
Novel ini juga memberikan pesan bahwa sebagai penegak hukum dalam hal ini Jan Aldemaar Staalhart dan Joost Boorsveld harus berani mengatakan tidak atas segala konsekuensi yang dihadapinya.
Sebagai penegak hukum harus berani melawan arus demi menjunjung tinggi asas-asas keadilan terhadap para korban.
Novel ini sangat layak untuk dibaca karena memberi pesan mendalam tentang bagaimana dinamika kekuasaan dan diskriminasi di masa lalu yang terus relevan dalam konteks kontempore.