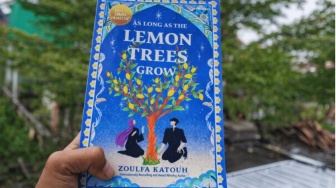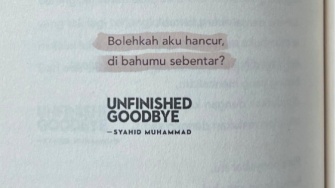Novel Menyusu Celeng karya Sindhunata ini pernah terbit dengan judul Tak Enteni Keplokmu: Tanpa Bunga dan Telegram Duka pada tahun 2000, lalu diterbitkan kembali oleh Gramedia dengan judul Menyusu Celeng. Butuh perjuangan tersendiri untuk menyelesaikan novel ini. Novel yang saya kira bisa diselesaikan dengan sekali duduk, ternyata berkali-kali duduk pun belum juga tamat.
Meskipun disebut novel, bagi saya isinya lebih terasa seperti satire politik yang dipenuhi esai-esai renungan politis, kental dengan aroma Jawa. Membacanya nikmat, meski kadang diselingi metafora-metafora yang tidak mudah diterjemahkan.
Sinopsis Novel
Kisah diawali dengan cerita tentang seorang pelukis yang mengalami pergulatan batin, baik dalam karya maupun kehidupan pribadinya. Karya-karyanya banyak mengandung kritik sosial. Yang paling menghebohkan adalah lukisan celeng. Celeng menjadi simbol ketamakan, kerakusan, tipu daya, dan kesewenang-wenangan. Ternyata, lukisan celeng inilah yang justru mendatangkan petaka.
Lukisan celeng karya Djokopekik menjelma bukan hanya pada diri pelukis, tetapi juga pada diri penguasa, anak-anak, masyarakat penonton wayang—pada semua orang. Manusia adalah celeng di balik topengnya, dan celeng yang paling berbahaya adalah koruptor yang mencuri uang rakyat tanpa rasa malu atas kecelengannya. Celeng digambarkan sebagai nafsu yang melekat dalam diri manusia.
Sang pelukis pun menjadi resah setelah celeng “salah kedadean” yang ia ciptakan memporak-porandakan zaman. Ia mencari asal-muasal mengapa celengnya menjadi begitu berbahaya. Ternyata, celeng itu dilukis dengan dendam, dan dari dendam itulah lahir celeng yang mematikan. Pelukis kemudian mengakhirinya dengan melukis sebuah celeng besar yang sudah mati.
Namun, cerita tidak berhenti di situ. Di usia tuanya yang tenang, sang pelukis kembali melukis celeng dalam sebuah bus yang kemudian dikenal sebagai bus celeng. Pelukis ternyata tidak benar-benar mampu mengenyahkan celeng dari dalam dirinya. Ia mengaku membenci kehidupan kaum borjuis, tetapi sesekali tetap menikmati kehidupan borjuis itu sendiri. Hingga akhir kisah, pelukis dalam novel ini tidak pernah berhasil sepenuhnya mengusir celeng dari dirinya. Celeng hanya bisa dikendalikan, bukan dihilangkan.
Struktur cerita terjalin erat dengan gaya kepemimpinan Orde Baru dan situasi politik Indonesia sejak 1965 hingga masa Reformasi. Novel ini tidak hanya membahas karut-marut politik Indonesia, tetapi juga perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Di dalamnya kita dapat menemukan sosok dan sepak terjang Megawati, Amien Rais, dan Gus Dur yang digambarkan secara menghibur. Gaya ceritanya surealis, menggabungkan unsur fiksi dan nonfiksi, membuat pembaca kerap bertanya: ini nyata atau tidak?
Kelebihan dan Kekurangan Novel
Novel ini sarat pesan moral tentang keadilan bagi kaum tertindas serta kritik tajam terhadap kaum borjuis. Ia menjadi cermin bahwa perubahan tidak bisa hanya diserahkan kepada pejabat di atas, tetapi harus dimulai dari rakyat kecil. Satire politiknya dibalut filsafat yang relatif mudah dipahami, lucu, dan benar-benar mampu mengundang tawa di hampir setiap bab.
Namun, penggunaan metafora yang sangat banyak bisa membuat pembaca yang menyukai bacaan ringan merasa jenuh. Buku ini seolah mengulang kata-kata filsuf Friedrich Nietzsche: binatang buas itu belum mati. Dalam peradaban modern, binatang buas itu masih hidup, bahkan semakin hidup—dan malah diilahikan.
Buku ini cocok dibaca oleh semua kalangan, termasuk remaja, dan tentu saja sangat layak dibaca oleh para politisi—jika sempat, ya.
Identitas Buku
Judul: Menyusu Celeng
Penulis: Sindhunata
Penerbit: Gramedia Pustaka Utama
Tahun terbit: 2019
Jumlah halaman: ± 360 halaman
Bahasa: Indonesia
Genre: Novel, satire politik, filsafat sosial