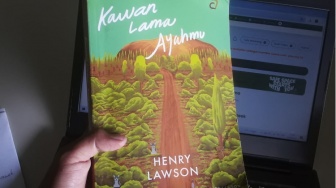Hujan turun pelan sejak sore. Jalanan kota basah, lampu-lampu toko berkelap-kelip di genangan air. Malam itu, seharusnya ramai dengan terompet dan petasan, tapi hampir semua orang memilih berteduh di rumah. Malam tahun baru yang biasanya semarak, kini sunyi dan muram.
Di bawah tenda plastik biru yang bocor, Pak Sodikin duduk menatap kardus terompetnya. Tangannya kasar, kukunya hitam karena debu jalanan, wajahnya letih tapi tetap tegar. Dari jauh, ia tampak kecil, terombang-ambing oleh hujan dan angin dingin.
“Pak, masih jualan sampai jam berapa?” tanya seorang anak muda yang berteduh sebentar.
Pak Sodikin tersenyum tipis, senyum yang terlalu sering ia pakai untuk menutupi lelah.
“Sampai tengah malam, Mas. Siapa tahu ada yang beli.”
“Siapa tahu.” Dua kata itu seperti mantra bagi hidupnya.
Di rumah kontrakan sempitnya, dua anaknya menunggu. Keduanya berkebutuhan khusus, yang tak pernah mengerti kalender atau perayaan tahun baru. Yang mereka tahu hanya lapar dan kenyang. Dan Pak Sodikin harus memastikan mereka makan.
“Yang penting halal, Pak,” kata seorang tetangga tahun lalu, mengingatkannya akan batasan.
Pak Sodikin mengangguk. Ia selalu mengangguk. Ia tak pandai berdebat. Ia hanya tahu: anak-anak harus makan.
Tak jauh dari situ, Mbok Satira menata petasan di atas terpal lusuhnya. Rambutnya putih, punggungnya bungkuk. Sendirian. Malam itu, ia hanya bisa menatap hujan, berharap ada pembeli. Anak-anaknya entah di mana. Satu-satunya keluarga yang tersisa hanyalah dagangan dan malam yang dingin.
“Mbok… nggak laku-laku ya?” tanyaku pelan.
Ia tertawa getir, menahan napas dingin.
“Dari sore baru satu bungkus, Nak… untungnya nggak banyak beli modalnya,” katanya, matanya berkaca-kaca.
Hujan makin deras. Kardus terompet Pak Sodikin mulai basah, beberapa terompet menyerap air dan tidak bisa dijual. Ia menepuknya pelan, seolah menenangkan benda mati itu.
“Pak, besok anak-anaknya makan apa?” aku bertanya, suara pelan.
Pak Sodikin terdiam lama. Matanya menatap jauh, kosong, tapi hangat.
“Ya… yang ada aja, Nak,” jawabnya lirih. “Kalau besok nggak ada yang beli… ya Allah… mudah-mudahan cukup.”
Aku menunduk, tak bisa berkata apa-apa. Hatiku sesak. Di ponselku, broadcast tentang haramnya merayakan tahun baru terus berdatangan. Vonis, fatwa, hinaan. Semua orang sibuk menegakkan “kebenaran”. Tapi di sini, di hujan dan malam yang sepi, ada manusia kecil yang tidak punya pilihan.
Tiba-tiba seorang anak kecil berlari, basah kuyup, tangannya memegang dompet tipis.
“Pak, beli satu terompet!” serunya riang.
Pak Sodikin menatapnya. Terompet itu terselamatkan. Ia mengangguk pelan.
“Terima kasih, Nak… semoga rezeki Ayahmu lancar,” kata Pak Sodikin lirih, matanya basah.
Mbok Satira menatap dari jauh. Seorang ibu menanyakan petasan, membeli tiga bungkus kecil. Ia tersenyum. Sederhana. Tapi malam itu, ia pulang dengan hati sedikit hangat.
Aku membeli satu terompet dan satu bungkus petasan. Bukan untuk merayakan. Bukan untuk bersenang-senang. Hanya untuk menyalakan harapan kecil agar mereka bisa makan malam itu.
Saat hujan reda, Pak Sodikin menatap langit, menyeka air matanya. Mbok Satira menunduk menata sisa dagangan. Dan aku… aku pulang dengan hati penuh dilema. Di luar, orang-orang sibuk menegakkan halal-haram. Tapi di bawah hujan, aku belajar bahwa kadang empati lahir bukan dari dalil, tapi dari perut yang kosong, tangan yang gemetar, dan doa-doa kecil yang naik diam-diam ke langit.
Malam itu, aku menangis pelan di sudut kota yang basah. Bukan karena aku tak takut neraka. Bukan karena ingin melakukan dosa. Tapi karena aku melihat kemuliaan orang kecil. Orang yang mengorbankan malam hujan demi keluarga. Orang yang menghidupi anak-anaknya tanpa syarat, tanpa debat, hanya dengan hati.
Dan aku berbisik di dalam hati,
“Ya Allah, semoga Engkau berkahi mereka. Engkau beri mereka cukup, meski malam ini sepi dan basah.”
Malam itu, terompet dan petasan menjadi saksi: Islam bisa sederhana, ramah, dan hangat—di tangan yang paling kecil sekalipun.