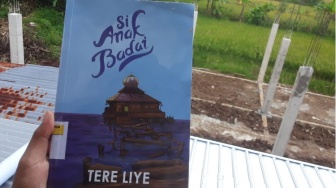"Aura batin itu tidak bisa bohong, Mas. Ini bukan sekadar lukisan, ini adalah esensi jiwa Mas yang saya terjemahkan ke dalam bentuk visual," ujar Satya dengan nada sok bijak, sambil mengusap dagunya yang ditumbuhi janggut jarang-jarang.
Di depannya, seorang pemuda bernama Doni menatap kanvas berukuran 40x40 cm itu dengan kening berkerut dalam. Satya adalah seorang pelukis surealis yang merasa dirinya adalah titisan Salvador Dalí yang lahir di Tanah Abang. Setelah karyanya ditolak oleh tiga galeri besar di Jakarta bulan ini karena dianggap "terlalu gelap dan kurang komersial", Satya memutuskan untuk menggelar lapaknya di trotoar samping pohon beringin besar, tepat di depan sebuah minimarket. Yakin.
Doni, yang awalnya cuma niat membeli rokok, terjebak rayuan Satya untuk dilukis. "Tapi Om," suara Doni agak bergetar, "kenapa muka saya di sini warnanya hijau lumut, terus mata saya ada lima, dan kenapa ada akar pohon keluar dari telinga saya?"
Satya menghela napas panjang, gaya khas seniman besar yang sedang menghadapi orang awam. "Itu simbolisme, Mas! Hijau itu artinya Mas sedang haus akan pertumbuhan ekonomi alias uang. Mata lima itu artinya Mas terlalu banyak melihat cicilan. Dan akar itu? Itu artinya Mas kurang piknik, pikiran Mas sudah menyatu dengan rutinitas yang kaku."
"Tapi ini seram, Om! Sumpah, kalau saya bawa pulang, ibu saya pasti memanggil dukun atau ustaz buat merukyah saya. Ini bukan lukisan aura, ini mah poster film horor tahun 80-an! Saya yakin ini pasti penunggu pohon beringin ini." Doni protes keras, matanya melirik ke arah pohon beringin di belakang.
Satya memutar bola matanya. Inilah kutukannya sebagai seniman surealis di jalanan. Di akademi seni, orang menyebut karyanya "eksplorasi bawah sadar yang provokatif". Di jalanan, orang menyebutnya "gambar setan". Padahal, Satya cuma mencoba jujur pada insting artistiknya. Ia kecewa berat.
"Ya sudah, karena Mas tidak paham estetika tingkat tinggi, bayar setengah harga saja. Buat beli mi instan," gumam Satya pasrah.
Doni akhirnya membayar, meski dengan wajah yang lebih kusut dari lukisannya sendiri. Ia membawa kanvas itu dengan cara dibalik, takut orang-orang di angkot mengira dia sedang membawa barang klenik. Malu.
Sepeninggal Doni, Satya kembali termenung. Ia menatap pohon beringin tua di sampingnya. Baginya, pohon itu bukan sekadar tumbuhan, melainkan sebuah entitas yang memiliki struktur geometris yang meliuk-liuk seperti pikiran manusia yang kalut. Ia mulai menggoreskan kuasnya lagi, mencoba menangkap "getaran" dari dahan-dahan tua itu. Seolah, ia hidup.
Tak lama kemudian, seorang ibu paruh baya yang baru saja turun dari ojek berhenti di depan lapaknya. Namanya Bu Ratna. Ia melihat ke arah kanvas Satya yang baru setengah jadi, sebuah lukisan pohon yang dahannya berbentuk tangan manusia yang sedang menggapai-gapai langit dengan latar belakang bulan yang meleleh seperti es krim murahan. Wajah pohon itu mirip orang gagal nyaleg.
"Astagfirullah!" Bu Ratna menutup mulutnya. "Mas! Mas ini gambar apa?"
Satya tersenyum bangga. "Ini potret metafisika dari pohon beringin ini, Bu. Saya melukis jiwa yang terperangkap dalam serat-serat kayu."
Wajah Bu Ratna pucat pasi. "Tuh, kan! Benar kata orang-orang! Pohon beringin ini memang ada penunggunya. Jadi ini ya, Mas, rupa hantu yang sering bikin bulu kuduk berdiri itu? Waduh, Mas hebat ya punya indra keenam bisa lihat hantu sampai digambar detail begini. Itu kenapa bulannya meleleh? Pasti karena panasnya api neraka ya, Mas?"
Satya melongo. "Bukan, Bu. Ini surealisme. Ini tentang distorsi realitas terhadap waktu..."
"Jangan sok pakai istilah ribet, Mas. Saya juga mengerti beginian," potong Bu Ratna cepat. "Saya mau beli lukisan ini buat dipasang di depan pagar rumah biar maling pada takut masuk. Kalau maling lihat gambar hantu Mas ini, saya yakin mereka langsung tobat nasuha. Saya yakin aura magisnya bisa menjaga rumah."
Satya merasa harga dirinya sebagai seniman intelektual merosot drastis. Karyanya yang ia buat dengan perenungan filosofis mendalam, kini fungsinya setara dengan stiker "Awas Ada Anjing Galak". Namun, perutnya yang keroncongan lebih keras suaranya daripada egonya.
"Dua ratus ribu, Bu," kata Satya pelan.
"Seratus ribu, ya? Kan ini gambar setan, nanti saya mesti beli kembang tujuh rupa lagi buat menetralkan auranya di rumah," tawar Bu Ratna.
Transaksi terjadi. Satya mengantongi uang seratus ribu dengan perasaan campur aduk antara senang bisa makan ayam penyet dan sedih karena dicap sebagai pelukis hantu jalanan. Ingin rasanya ia mengamuk. Gila.
Malam makin larut. Lampu jalanan mulai berkedip-kedip, menciptakan bayangan yang makin aneh di trotoar. Satya mulai berkemas. Ia melihat sisa cat di paletnya. Campuran warna ungu tua, hitam, dan sedikit merah menyala. Ia menatap bayangannya sendiri di kaca minimarket. Wajahnya terlihat tirus, matanya cekung, rambutnya berantakan.
Ia tersenyum sendiri. Ia menyadari sesuatu, hidupnya sendiri saat ini sudah sangat surealis. Seorang pelukis yang mendamba pengakuan elit, namun justru bertahan hidup dari ketakutan orang-orang akan takhayul.
Ia mengambil sebuah kardus bekas yang tergeletak di jalan, lalu dengan sisa cat yang ada, ia menuliskan sebuah papan iklan kecil, "Terima lukis indra keenam & potret aura gaib. Hasil dijamin mengandung kekuatan magis."
Mungkin dengan ini besok akan lebih laku. Biarlah dunia menganggapnya gila atau bersekutu dengan jin, yang penting ia tetap bisa memegang kuas. Baginya, kenyataan memang terlalu membosankan untuk dilukis apa adanya dan dipikirkan terlalu keras. Kadang, kita butuh sedikit distorsi dan beberapa pasang mata tambahan dari orang yang salah paham. Pasrah.
Satya berjalan pulang dengan tas berat di pundaknya, melewati deretan gedung tinggi Jakarta yang berkilau. Di mata Satya, gedung-gedung itu terlihat seperti silet raksasa yang mencoba memotong awan. "Nah, itu ide bagus buat besok," gumamnya sambil tertawa kecil, melintasi trotoar yang mulai sepi. Lagi.