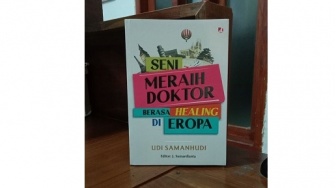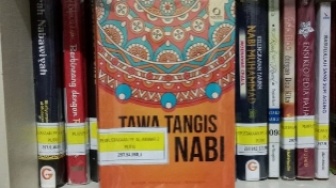Pengalaman ini takkan pernah kulupakan seumur hidupku. Kejadiannya berlangsung saat aku dan delapan teman lainnya mengikuti program pengabdian masyarakat di sebuah desa terpencil di lereng Gunung Lawu. Kelompok kami terdiri atas sembilan mahasiswa: tiga laki-laki dan enam perempuan. Desa tersebut asri, namun memiliki aura yang ganjil; seolah-olah waktu berhenti berputar di sana puluhan tahun yang lalu.
Kami ditempatkan di sebuah bangunan yang dulunya merupakan puskesmas pembantu. Bangunan itu sudah tidak digunakan sejak awal tahun 2005-an. Dari depan, cat putihnya sudah mengelupas, digantikan oleh noda hitam jamur dan lumut yang merambat. Meskipun sudah dibersihkan, noda-noda itu masih membekas. Jendela-jendelanya tinggi dengan teralis besi yang berkarat, menciptakan bayangan panjang yang menyerupai jemari kurus saat Matahari terbenam.
Pak Kades mengantar kami sampai ke depan pintu kayu ganda yang berat. Saat kunci diputar, suara deritnya memecah kesunyian desa.
“Maaf, fasilitasnya terbatas. Hanya ini gedung yang cukup besar untuk kalian semua,” ucap Pak Kades. Pandangannya sempat menyapu lorong panjang di dalam bangunan itu sebelum ia buru-buru berpamitan dengan raut wajah yang tampak tidak tenang.
Kami mulai membagi ruang. Di bangunan itu ada bekas ruang administrasi, ruang periksa, dan beberapa bangsal kecil yang kini hanya berisi dipan kayu tanpa kasur. Di ujung lorong, terdapat satu pintu besi yang tertutup rapat dengan rantai berkarat yang melilit gagangnya. Bau karbol yang samar namun menusuk langsung menyeruak, bercampur dengan bau debu yang sudah mengendap bertahun-tahun.
“Itu ruang apa, Pak?” tanya Rian, ketua kelompok kami, saat Pak Kades hampir melangkah pergi.
Langkah kaki Pak Kades terhenti. Tanpa menoleh, ia menjawab pelan, “Itu dulu ruang tindakan darurat. Kuncinya sudah hilang. Sebaiknya jangan mencoba membukanya, apalagi masuk ke sana. Biarkan saja tetap terkunci.”
Setelah kepergian Pak Kades, suasana mendadak sunyi. Angin gunung serasa menyelinap masuk ke tulang. Namun, ketegangan itu justru dianggap remeh oleh Bandi. Dengan langkah angkuh, ia mendekati pintu besi yang melilit rantai berkarat itu.
"Hah, bangunan reyot saja kok ditakut-takuti," cibir Bandi sambil tertawa kecil.
Tok! Tok! Tok!
Ia mengetuk pintu itu dengan keras menggunakan kepalan tangannya. Suara benturan logam yang berat bergema di sepanjang lorong yang lembap. Kami semua terkesiap. Putri mencoba memperingatkan, "Ban, jangan cari masalah. Pak Kades tadi bilang apa?"
Bandi tidak menghiraukan. Ia justru menempelkan telinganya ke pintu besi yang dingin itu. "Kosong begini, paling cuma isinya alat medis lama atau tikus," katanya sambil kembali mengetuk, kali ini lebih seperti hantaman.
Malam pertama di puskesmas itu terasa berat. Udara pegunungan yang dingin merembes masuk melalui celah-celah ventilasi. Kami memutuskan untuk menggelar matras di ruang tengah agar bisa bersama-sama karena merasa tidak nyaman dengan luasnya bangunan itu. Namun, sekitar jam dua pagi, aku terbangun karena mendengar suara logam yang beradu. Kring... kring... Suaranya lirih, mirip bunyi roda troli medis yang didorong di atas lantai keramik yang pecah-pecah. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanya suara angin yang menggerakkan rantai di ujung lorong.
Teror sebenarnya dimulai pada malam keempat. Saat itu, salah satu teman perempuanku, Ajeng, sedang ke kamar mandi di bagian belakang. Tiba-tiba, teriakan histeris memecah keheningan malam. Kami semua berlari menuju sumber suara dan menemukan Ajeng terduduk lemas di depan pintu besi yang dirantai itu.
“Ada... ada suara orang bersenandung dari dalam,” isak Ajeng dengan wajah pucat pasi.
Kami semua terdiam. Di balik pintu besi yang gelap itu, samar-samar terdengar suara wanita menyanyikan lagu nina bobo dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya sangat merdu, namun terasa begitu menyayat hati dan dingin. Sapto memberanikan diri mendekat. Saat ia menyentuh rantai pintu, suara senandung itu tiba-tiba berubah menjadi suara tawa cekikikan yang melengking.
Seketika, suhu di lorong itu merosot drastis. Dari celah bawah pintu besi, perlahan keluar cairan kental berwarna merah kehitaman yang mengeluarkan bau darah yang menyengat. Jantungku berdegup kencang hingga terasa ingin melompat keluar. Kami semua berlari kembali ke ruang tengah, mengunci pintu, dan merapatkan diri.
Namun, gangguan itu tidak berhenti. Di tengah kegelapan, lampu neon di langit-langit berkedip dan meledak satu per satu. Bau karbol menjadi sangat tajam hingga membuat mual. Tiba-tiba, dari arah lorong muncul sosok perawat dengan seragam putih kusam yang penuh noda darah. Wajahnya hancur di satu sisi, matanya hanya menyisakan lubang hitam yang dalam. Ia memegang sebuah jarum suntik besar yang berkarat.
"Siapa yang mau sembuh duluan?" tanyanya dengan suara serak yang bergema di dalam kepala kami.
Kami mencoba lari ke pintu depan, namun pintu itu terasa seolah-olah telah menyatu dengan dinding. Sementara itu, sosok perawat itu mulai berjalan mendekat dengan gerakan patah-patah yang mengerikan. Bandi tiba-tiba jatuh tersungkur dan mengerang kesakitan seolah ada yang mencekiknya. Matanya terbuka lebar, namun pupilnya menghilang. Sungguh mengerikan kejadian waktu itu.
Pagi harinya, kami pergi meninggalkan puskesmas itu dengan beban di hati, menyadari bahwa bangunan tua itu menyimpan duka yang masih bernapas. Kejadian ini menjadi pengingat keras bagi kami: di mana pun kita berada, tata krama adalah pelindung utama, karena setiap sudut bangunan memiliki memori dan penghuni yang berhak atas ketenangan mereka.