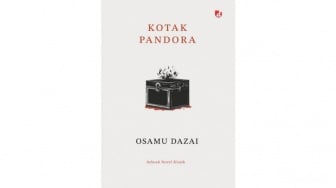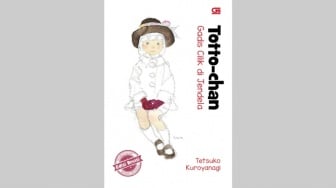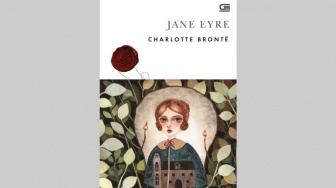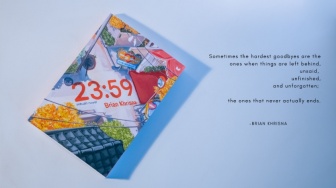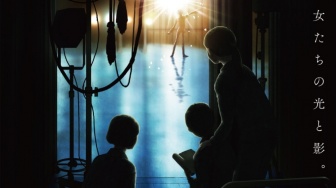Dalam sebuah negara yang mengaku demokratis, kebebasan berpendapat seharusnya menjadi fondasi yang tak tergoyahkan. Namun, belakangan ini, pola yang berulang terus terjadi: kritik dilemparkan, pihak yang merasa tersinggung bereaksi, lalu permintaan maaf dan klarifikasi menjadi akhir dari narasi yang seharusnya menjadi diskusi publik yang sehat.
Fenomena ini kian nyata ketika lagu "Bayar Bayar Bayar" dari Sukatani mendadak lenyap setelah menuai kontroversi dengan institusi kepolisian.
Musik, seperti bentuk seni lainnya, adalah cerminan realitas sosial. Sejarah telah mencatat bagaimana musisi sering menjadi suara dari kegelisahan masyarakat. Lagu-lagu protes, dari Iwan Fals hingga Efek Rumah Kaca, pernah menggema sebagai kritik terhadap kebijakan dan ketimpangan sosial.
Tetapi ketika lirik lagu yang mengangkat realitas pungutan liar harus ditarik dan para musisinya meminta maaf, pertanyaannya menjadi lebih besar: apakah kritik melalui seni masih bisa diterima, ataukah ruang demokrasi telah dipersempit oleh sensitivitas berlebihan?
Dalam kasus ini, bukan hanya soal sebuah lagu yang akhirnya dihapus. Ini adalah potret dari bagaimana kekuatan yang lebih besar masih memiliki kendali atas narasi publik.
Setiap kritik yang dianggap menyinggung institusi tertentu kerap berujung pada tekanan, bukan diskusi. Tidak jarang, klarifikasi yang diberikan bukan karena kesalahan yang diakui, tetapi karena tekanan yang datang dari pihak-pihak yang tidak ingin citranya terganggu.
Padahal, jika kritik selalu direspons dengan represi atau tuntutan klarifikasi, bukankah itu menandakan adanya sesuatu yang memang patut dikritik?
Fenomena "negara klarifikasi" bukan hanya terjadi pada dunia musik. Kritik di berbagai ranah, baik politik, hukum, maupun sosial, sering kali berakhir dengan skenario serupa.
Kasus demi kasus menunjukkan bahwa siapa pun yang berani menyuarakan kritik keras harus bersiap dengan konsekuensi: peringatan, ancaman, atau bahkan kriminalisasi.
Di tengah ketimpangan ini, masyarakat dibuat ragu untuk bersuara. Sebab, ketika kritik tidak bisa diterima dengan kepala dingin, siapa yang berani mengambil risiko?
Ini bukan sekadar perdebatan tentang satu lagu atau satu musisi. Ini adalah cerminan dari bagaimana demokrasi dijalankan. Demokrasi tidak hanya sebatas hak memilih pemimpin, tetapi juga kebebasan untuk berbicara tanpa takut dibungkam.
Kritik seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman, tetapi sebagai pengingat bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Jika setiap kritik hanya berujung pada klarifikasi dan permintaan maaf, lalu di mana ruang untuk perubahan?
Negara demokratis seharusnya memiliki aparatur yang terbuka terhadap kritik, bukan justru menciptakan atmosfer ketakutan. Kalau kritik dianggap sebagai bentuk perlawanan yang harus diberangus, maka demokrasi itu sendiri sedang berada di ujung tanduk.
Masyarakat tidak boleh dibiarkan diam karena takut akan konsekuensi dari suara mereka. Sebab, tanpa kritik, tidak ada perbaikan. Dan tanpa perbaikan, demokrasi hanya akan menjadi sekadar jargon kosong.