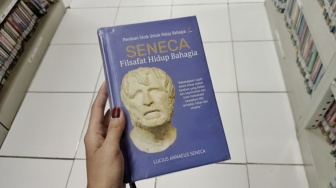Presiden Prabowo Subianto akan segera merealisasikan Sekolah Rakyat yang digadang-gadang sebagai solusi untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Proyek besar ini menargetkan 200 sekolah dengan sistem asrama penuh dari jenjang SD hingga SMA, dan mulai membuka pendaftaran murid serta guru sejak April 2025. Bila berjalan sesuai rencana, 53 sekolah akan langsung beroperasi pada Juli mendatang.
Secara teknis, program ini tampak menjanjikan. Sekolah Rakyat ditujukan untuk anak-anak dari Desil 1 dan Desil 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), artinya hanya anak dari keluarga paling miskin yang boleh mendaftar.
Proses seleksi mencakup tes psikologi, akademik, dan kesehatan, dengan fasilitas asrama yang sepenuhnya gratis. Ini akan menjadi kesempatan emas bagi ribuan anak dari pelosok negeri yang selama ini terhambat akses pendidikan karena faktor ekonomi dan geografis.
Namun, seiring dengan kesiapan peluncuran program ini, muncul sejumlah catatan kritis yang patut diperhatikan sebelum Sekolah Rakyat benar-benar dijalankan. Pertama adalah soal tupoksi kelembagaan. Program sebesar ini justru berada di bawah naungan Kementerian Sosial, bukan Kementerian Pendidikan. Hal ini menjadi anomali yang patut dipertanyakan karena urusan pendidikan bukan sekadar soal bantuan sosial atau penanggulangan kemiskinan, tapi menyangkut kurikulum, kualitas pengajar, dan evaluasi berkelanjutan. Semua itu adalah ranah Kemendikbudristek.
Selain itu, mekanisme seleksi juga menyisakan ironi. Mengapa anak-anak dari keluarga termiskin harus diuji dengan tes akademik dan psikotes terlebih dahulu? Apakah adil meminta kesiapan akademik dari anak-anak yang bahkan mungkin belum pernah bersekolah secara rutin karena kendala ekonomi dan infrastruktur? Alih-alih membantu, seleksi ketat bisa menjadi penghalang awal yang menyaring mereka secara tidak adil.
Dari sisi anggaran, Sekolah Rakyat juga menyedot perhatian. Rp150 miliar per sekolah bukanlah angka kecil, terutama jika dikalikan untuk 200 sekolah. Presiden bahkan meminta pemerintah daerah menyiapkan tanah 5 hingga 20 hektare untuk setiap sekolah. Meski niatnya baik, program ini terancam menjadi proyek mercusuar jika tidak disertai perbaikan sistemik pada sekolah-sekolah yang sudah ada.
Faktanya, mayoritas penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas masih hanya lulusan SD atau SMP. Data BPS 2024 mencatat bahwa hanya sekitar 10 persen yang lulus perguruan tinggi, sementara 24,72 persen hanya lulus SD dan 22,79 persen lulus SMP. Di wilayah-wilayah seperti Papua Pegunungan, rata-rata lama sekolah bahkan hanya 5,1 tahun. Artinya, banyak anak yang bahkan belum lulus SD. Bukankah seharusnya perhatian utama pemerintah difokuskan ke sini dulu?
Tantangan pendidikan di Indonesia tidak hanya soal akses, tetapi juga kehadiran guru, kualitas belajar, dan infrastruktur. Di Papua Barat, misalnya, tingkat ketidakhadiran guru mencapai 37 hingga 43 persen. Anak kelas 2 SD masih kesulitan membaca kalimat sederhana. Kondisi geografis ekstrem, budaya lokal yang tidak selalu kompatibel dengan sistem sekolah formal, serta kapasitas pemerintah daerah yang terbatas, menjadikan pendekatan satu model seperti Sekolah Rakyat tidak bisa diterapkan secara merata di seluruh wilayah.
Daripada membangun sekolah baru dari nol, pemerintah bisa menempuh pendekatan reformasi sekolah-sekolah konvensional. Mulai dari merehabilitasi sekolah rusak, menambah ruang kelas, memperbaiki gaji dan distribusi guru honorer, hingga menyederhanakan kurikulum agar lebih sesuai dengan konteks lokal. Jika tetap ingin membuat sekolah asrama, maka sebaiknya model Sekolah Rakyat dikembangkan oleh Kemendikbud dengan kolaborasi multisektor, bukan eksklusif ditangani Kemensos.
Sekolah Rakyat bisa menjadi solusi jika dilandasi niat yang tepat dan dikelola oleh lembaga yang tepat pula. Jangan sampai niat mulia ini justru menjadi alat pencitraan atau sekadar bentuk pelarian dari tanggung jawab memperbaiki sistem pendidikan nasional yang sudah ada. Program ini juga perlu transparansi publik soal lokasi sekolah, metode seleksi, dan hasil evaluasi berkala.
Pendidikan adalah hak dasar, bukan hadiah bagi yang lolos seleksi. Bila Sekolah Rakyat benar-benar ingin menyasar kelompok paling miskin, maka pendekatannya tidak boleh berbasis kompetisi, tapi keberpihakan. Alih-alih membuat sekolah eksklusif, negara harus hadir memperbaiki sekolah-sekolah umum agar siapapun, miskin atau tidak, mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu dan setara.
Dengan peluncuran Sekolah Rakyat yang sudah di depan mata, inilah saat yang tepat bagi pemerintah untuk memastikan bahwa program ini bukan hanya cepat digelar, tapi juga berkelanjutan, inklusif, dan kontekstual. Sebab jika tidak, yang akan muncul bukan harapan baru bagi anak-anak miskin, tapi kekecewaan baru dari kebijakan yang salah jalur.
CEK BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS