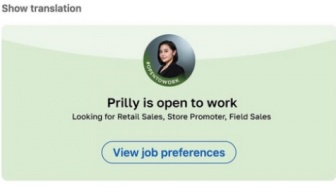Pemenuhan kesejahteraan anak di Indonesia hingga saat ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural dan sistemik yang signifikan. Meskipun kerangka hukum dan kebijakan perlindungan anak telah dirancang dengan baik melalui berbagai peraturan perundang-undangan, implementasi di lapangan kerap kali tidak mencapai hasil yang diharapkan. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta rendahnya responsivitas terhadap situasi darurat menjadi faktor utama yang menghambat upaya tersebut. Anak-anak yang berada dalam kondisi rentan—seperti mereka yang terdampak konflik sosial di Maluku, Aceh, dan Papua, atau menjadi korban kekerasan seksual di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat—sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai sesuai dengan hak-hak kodrati mereka.
Pada tanggal 8 April 2025, Menteri Sosial Republik Indonesia, Tri Rismaharini, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Cirebon dalam rangka memberikan penguatan psikologis dan bantuan sosial kepada para korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang guru. Dalam pernyataan resminya, beliau menyampaikan, “Kunjungan ini merupakan respons atas maraknya pemberitaan di media massa dan platform media sosial terkait kasus rudapaksa yang menimpa anak-anak di wilayah ini” (Kementerian Sosial RI, 2025). Kunjungan tersebut tidak hanya menjadi cerminan keprihatinan pemerintah terhadap kondisi anak-anak, tetapi juga menyoroti urgensi perlindungan yang tidak dapat ditunda di tengah sistem hukum yang masih berjalan dengan lambat dan belum sepenuhnya efektif.
Kerangka Hukum: Landasan Normatif dan Kesenjangan Implementasi
Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak anak, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Instrumen-instrumen ini menegaskan bahwa anak berhak atas perlindungan menyeluruh, mencakup aspek kehidupan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan dari segala bentuk kekerasan serta diskriminasi. Komitmen nasional ini diperkuat dengan ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang mengikat Indonesia secara hukum untuk memenuhi standar internasional dalam perlindungan anak.
Namun, meskipun kerangka normatif telah tersedia, implementasinya masih jauh dari ideal. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto (1979) dalam kajian mereka tentang hukum sebagai subsistem budaya dan sosial menegaskan bahwa efektivitas hukum bergantung pada tiga pilar utama: substansi (isi hukum), struktur (lembaga penegak hukum), dan budaya hukum (pola perilaku masyarakat). Ketidaksinkronan ketiga elemen ini menjadi penyebab utama stagnasi perlindungan anak di Indonesia. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa pada tahun 2023, terdapat 4.136 kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan, namun kurang dari 40% di antaranya yang berhasil diselesaikan melalui proses hukum yang memadai (KPAI, 2024).
Sebagai contoh, anak-anak korban konflik di Poso, Sulawesi Tengah, pasca-kerusuhan komunal pada awal 2000-an, lebih banyak menerima bantuan rehabilitasi dari Kementerian Sosial dibandingkan intervensi hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan. Demikian pula, kasus kekerasan seksual di Cirebon baru mendapat perhatian luas setelah menjadi viral di media sosial, menunjukkan bahwa respons hukum sering kali bersifat reaktif ketimbang proaktif. Kesenjangan ini menegaskan bahwa hukum yang ada belum sepenuhnya berfungsi sebagai alat perlindungan yang responsif dan preventif.
Hak Kodrati Anak: Antara Pengakuan dan Realitas
Hak anak sebagai hak kodrati dan fundamental telah diakui secara eksplisit dalam sistem hukum nasional. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan perlindungan anak sebagai “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) sebagai lembaga pemerintah pusat memiliki mandat untuk memastikan implementasi kebijakan ini melalui program-program strategis, seperti Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).
Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pengakuan hukum tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam kehidupan anak-anak Indonesia. Laporan dari Yayasan Sayangi Tunas Cilik (YSTC), sebuah organisasi non-profit yang bergerak di bidang advokasi anak, mencatat bahwa pada tahun 2023, lebih dari 50.000 anak jalanan di Jakarta hidup dalam kondisi rentan, tanpa akses memadai terhadap pendidikan, kesehatan, atau perlindungan hukum (YSTC, 2024). Di wilayah Maluku, anak-anak korban konflik antarkomunitas pada periode 1999-2002 masih menghadapi trauma berkepanjangan akibat minimnya program pemulihan yang berkelanjutan. Sementara itu, di Papua, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa konflik berkepanjangan hingga tahun 2023 telah menyebabkan lebih dari 12.000 anak mengungsi, dengan sebagian besar tidak mendapatkan pendampingan psikologis atau pendidikan alternatif (BPS, 2024).
Kasus di Cirebon semakin memperkuat gambaran ini. Kekerasan seksual yang menimpa anak-anak oleh seorang guru menunjukkan betapa rapuhnya sistem perlindungan di tingkat lokal, hingga memerlukan intervensi langsung dari pemerintah pusat. Situasi ini mencerminkan bahwa hak-hak anak yang dijamin oleh hukum belum sepenuhnya menjadi realitas yang dirasakan oleh mereka yang paling membutuhkannya.
Urgensi Perlindungan Anak: Bukti Empiris dan Analisis Mendalam
Urgensi perlindungan anak tidak dapat dipandang sebelah mata, mengingat anak merupakan subjek yang rentan terhadap berbagai bentuk ancaman, mulai dari kekerasan fisik dan seksual hingga eksploitasi dan dampak konflik sosial. Arif Gosita (1983) dalam karyanya tentang kesejahteraan anak menegaskan bahwa perlindungan anak harus didasarkan pada prinsip keadilan yang rasional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Prinsip ini selaras dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang menyatakan bahwa “anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik sebelum maupun sesudah kelahiran, serta terhadap lingkungan yang dapat membahayakan perkembangannya.”
Data empiris memperkuat argumen ini. Menurut laporan Kementerian Sosial RI, pasca-tsunami Aceh pada Desember 2004, lebih dari 150.000 anak kehilangan salah satu atau kedua orang tua mereka, dan hingga tahun 2010, hanya sekitar 30% yang mendapatkan rehabilitasi psikososial penuh (Kementerian Sosial RI, 2011). Di wilayah Papua, konflik bersenjata yang berlangsung selama dekade terakhir telah menyebabkan ribuan anak kehilangan akses terhadap pendidikan formal, dengan angka putus sekolah meningkat sebesar 15% antara tahun 2020 dan 2023 (BPS, 2024). Sementara itu, di Kalimantan, YSTC melaporkan bahwa eksploitasi anak dalam sektor perkebunan kelapa sawit masih marak, dengan lebih dari 5.000 anak di bawah umur terdeteksi bekerja dalam kondisi berbahaya sepanjang tahun 2023 (YSTC, 2024).
Kasus kekerasan seksual di Cirebon menjadi bukti nyata lain dari urgensi ini. Pelaku yang merupakan seorang guru—figur yang seharusnya menjadi pelindung—justru menyalahgunakan kepercayaan tersebut, meninggalkan trauma mendalam bagi para korban. Kunjungan Menteri Sosial Tri Rismaharini pada April 2025, yang mencakup pemberian bantuan sosial dan pendampingan, menunjukkan bahwa respons pemerintah masih bersifat ad hoc dan belum menyentuh akar masalah, seperti lemahnya sistem pencegahan dan penegakan hukum di tingkat lokal.
Jalan ke Depan: Sinkronisasi Kebijakan, Infrastruktur, dan Aksi Konkret
Untuk mengatasi tantangan tersebut, implementasi hak-hak anak memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, melibatkan sinkronisasi antara kebijakan, infrastruktur pendukung, dan budaya hukum yang kondusif. Regulasi yang ada harus diterjemahkan ke dalam aksi konkret yang dapat dirasakan langsung oleh anak-anak di seluruh pelosok negeri. Kementerian Sosial, sebagai lembaga yang memiliki fungsi rehabilitasi sosial, dapat memperluas program Layanan Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) untuk menjangkau anak-anak korban konflik di Maluku dan Papua, dengan dukungan anggaran dari Kementerian Keuangan.
Sementara itu, KPPPA dapat berkolaborasi dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk membentuk satuan tugas khusus yang menangani kasus kekerasan anak secara cepat dan terkoordinasi, sebagaimana yang dibutuhkan dalam kasus Cirebon. KPAI dalam laporan tahunannya merekomendasikan penguatan sistem pelaporan berbasis masyarakat dan pendampingan psikologis di tingkat kabupaten/kota, dengan target menurunkan angka kekerasan anak sebesar 20% pada akhir tahun 2025 (KPAI, 2024). Di sisi lain, YSTC mengusulkan pelibatan komunitas lokal dalam program pencegahan eksploitasi anak, yang telah terbukti efektif di beberapa daerah urban seperti Surabaya dan Bandung, dengan tingkat keberhasilan mencapai 70% dalam mengurangi angka anak jalanan (YSTC, 2024).
Pemerintah daerah juga memiliki peran krusial. Dinas Sosial Provinsi Maluku, misalnya, dapat menginisiasi program rehabilitasi terpadu bagi anak-anak korban konflik, mencakup pendidikan alternatif, konseling trauma, dan reintegrasi sosial. Pendekatan ini memerlukan alokasi sumber daya yang memadai serta komitmen lintas sektor untuk memastikan keberlanjutan. Tanpa langkah-langkah konkret tersebut, anak-anak akan terus berada dalam risiko, sementara hukum hanya menjadi janji di atas kertas.
Anak-anak merupakan generasi penerus yang menentukan masa depan bangsa, sehingga perlindungan terhadap mereka bukanlah pilihan, melainkan kewajiban mutlak. Jika sistem hukum dan kebijakan terus berjalan tanpa efektivitas yang nyata, hak-hak anak yang telah dijamin oleh undang-undang akan tetap menjadi wacana normatif tanpa dampak riil. Undang-Undang Perlindungan Anak dengan tegas menyatakan bahwa setiap anak berhak hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Namun, realitas menunjukkan bahwa hak tersebut belum sepenuhnya terwujud bagi jutaan anak di Indonesia.
Pemerintah, bersama seluruh pemangku kepentingan, harus segera mengambil langkah strategis untuk menutup kesenjangan antara regulasi dan implementasi. Anak-anak tidak memiliki kemewahan untuk menunggu hukum menjadi sempurna—mereka membutuhkan perlindungan yang nyata dan segera. Sebagaimana ditekankan dalam visi KPPPA, “Anak yang terlindungi adalah investasi bagi masa depan bangsa” (KPPPA, 2023). Pertanyaannya kini adalah: kapan kita benar-benar mewujudkan visi tersebut dalam tindakan yang terukur dan berkelanjutan?