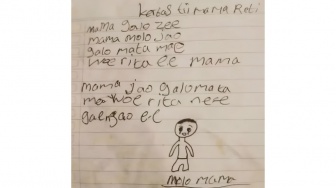Kamu pernah nggak ngalamin ini: lagi jalan ke minimarket, lihat tulisan “Diskon Besar! Barang Banyak!” Tapi pas lihat harganya… tetep mahal. Terus lo mikir, “Ini diskon apanya?”
Nah, itu persis seperti situasi beras kita sekarang. Stoknya katanya memecahkan rekor sejarah, tapi harga di lapangan? Masih naik daun, bahkan lebih stabil dari hubunganmu yang nggak pasti itu.
Pemerintah lewat Mentan Amran dengan bangga menyampaikan bahwa stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai 3,5 juta ton per 4 Mei 2025. Ini adalah angka tertinggi dalam sejarah Indonesia, bahkan ngalahin rekor zaman 1997.
Terdengar mengagumkan, kan? Sampai kamu sadar... kok ya harga beras tetap mahal? Ibarat kamu punya lemari es penuh makanan, tapi tetap kelaparan karena pintunya dikunci dari luar.
Secara teori ekonomi dasar yang diajarin anak IPS SMA, kalau pasokan naik dan permintaan tetap, harga harusnya turun dong? Tapi entah kenapa, logika itu kayak nggak berlaku di negeri +62.
Stok beras 3,5 juta ton tapi realitanya harga tetap nggak turun-turun. Angka besar bisa jadi ilusi, apalagi kalau nggak disertai efek nyata ke dapur masyarakat.
Lucunya, pemerintah memamerkan keberhasilan mengumpulkan stok, tapi sepi bicara soal kenapa rakyat tetap harus bayar mahal.
Lebih parahnya lagi, sebagian besar dari stok ini ternyata hasil impor. Jadi, yang digembor-gemborkan bukan prestasi swasembada, tapi prestasi belanja dari luar negeri.
Menurut data BPS, Indonesia sudah mengimpor lebih dari 2,5 juta ton beras sepanjang kuartal pertama 2025, terutama dari Thailand dan Vietnam. Jadi saat pemerintah bangga dengan banyaknya cadangan, wajar dong publik bertanya: “Ini prestasi logistik atau bukti kita nggak mampu produksi sendiri?”
Kita udah capek dengar jargon “menuju swasembada pangan” yang diputar ulang oleh Presiden kita. Tapi kenyataannya, petani lokal tetap berkutat dengan pupuk yang mahal, irigasi yang rusak, dan harga gabah yang kadang lebih rendah dari ongkos panennya.
Kalau kita memang serius ingin swasembada, seharusnya investasi paling besar bukan di gudang penyimpanan beras impor, tapi di petani kecil yang tiap hari berjemur demi produksi pangan dalam negeri.
Tapi sayangnya, mereka justru sering jadi korban dari logika pasar yang lebih memihak pada kemudahan impor ketimbang kestabilan produksi lokal. Di sinilah rasa ironi itu makin terasa: kita punya beras banyak, tapi petani kita tetap hidup dalam ketidakpastian.
Buat banyak keluarga di Indonesia, beras bukan sekadar makanan, tapi simbol rasa aman. Kalau harga beras mahal, yang terguncang bukan cuma isi kantong, tapi juga psikologi publik. Makanya nggak heran kalau isu harga beras bisa bikin pemerintah dapet cap “gagal” di mata rakyat.
Karena jujur aja, anak muda hari ini mungkin bisa bertahan tanpa beli tiket konser atau ganti iPhone terbaru. Tapi kalau emak-emak nggak bisa beli beras dengan harga wajar, itu pertanda ada yang sangat keliru di sistem kita.
Jadi, apa yang bisa kita lakukan?
Pertama, sebagai warga, jangan langsung percaya narasi besar soal stok. Lihat realitanya di pasar. Kalau harga nggak turun, artinya ada yang salah di sistem, bukan di keranjang belanja kita.
Lalu, dorong transparansi soal distribusi beras. Publik perlu tahu: dari 3,5 juta ton itu, berapa persen yang udah disalurkan? Berapa persen yang masih numpuk di gudang?
Kita juga perlu lebih vokal mendukung petani lokal. Karena mereka yang seharusnya kita banggakan, bukan angka di statistik.
Terakhir, mari pertanyakan narasi-narasi yang hanya pamer angka besar tanpa efek nyata. Jangan sampai kita dibuat kagum, tapi tetap lapar. Karena bangsa besar bukan cuma dinilai dari cadangannya, tapi dari sejauh mana rakyatnya bisa makan layak setiap hari.
Jadi, stok beras boleh tinggi, tapi kalau harga tetap bikin pusing, itu bukan prestasi. Itu PR.
Cek berita dan artikel lainnya di GOOGLE NEWS