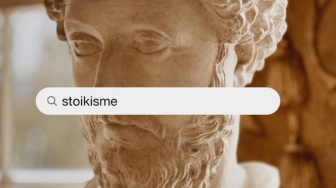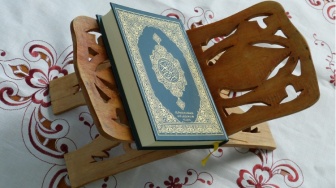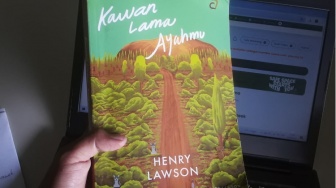Bayangkan Anda adalah seorang dosen Indonesia lulusan luar negeri. Di sana, Anda mendapatkan gaji layak, laboratorium lengkap, kebebasan akademik, dan—yang paling menyenangkan—pengakuan sebagai intelektual.
Lalu suatu hari, Anda diminta pulang. Tapi apa yang menanti? Gaji pas-pasan, birokrasi panjang, dan sering kali, rasa frustrasi karena ilmu tak kunjung terpakai.
Inilah dilema yang dihadapi banyak dosen diaspora Indonesia. Mengajar di negeri orang memberikan kepastian dan prestise. Sementara pulang ke tanah air, meski penuh semangat nasionalisme, sering kali hanya jadi wacana.
Wacana yang tak punya ruang untuk hidup dalam sistem pendidikan tinggi kita yang belum siap menyambut kepakaran dengan adil dan bermartabat.
Gaji dan Martabat—Sains Tak Bisa Hidup dari Semangat Saja
Mitos “mengajar itu panggilan jiwa” barangkali masih akrab di telinga kita. Tapi ketika seorang dosen Indonesia dengan gelar PhD dari kampus ternama hanya dibayar Rp4 jutaan, lalu disandingkan dengan koleganya di Singapura yang menerima Rp80 juta, kita harus jujur bertanya: seberapa bernilai ilmu pengetahuan di negeri sendiri?
Khomsan (2025) menyatakan bahwa dosen diaspora merasa lebih dihargai di luar negeri—bukan hanya secara finansial, tapi juga secara sosial dan institusional. Mereka bisa fokus meneliti tanpa harus mengurus absen manual atau proposal dana hibah yang menumpuk. Sementara di Indonesia, sering kali beban administratif lebih besar dari beban akademik itu sendiri.
Data dari Abdillah (2024) mengungkapkan bahwa gaji dosen Indonesia berada di kisaran Rp2,3 juta hingga Rp6,37 juta. Dibandingkan Singapura, Malaysia, atau bahkan Thailand, angka ini jelas membuat ciut nyali siapa pun yang hendak pulang. Meski Permendikbudristek No. 44/2024 menjanjikan standar minimum dan tunjangan, faktanya belum banyak berubah di lapangan.
Ilmu butuh lingkungan tumbuh, dan salah satu tanahnya adalah kesejahteraan. Jika intelektual tak bisa hidup layak, maka jangan heran bila mereka memilih menabur ilmunya di tanah yang lebih subur—meski itu berarti jauh dari Indonesia.
Di Sana Ada Laboratorium, Di Sini Ada "Lampiran Surat Tugas"
Perpindahan tenaga ahli dari negara berkembang ke negara maju bukanlah cerita baru. Mishra (2023) menyebut ini sebagai brain drain—pengeringan otak dari negara asal karena negara lain menawarkan fasilitas lebih lengkap, sistem meritokrasi, dan kebebasan akademik.
Bagi seorang dosen diaspora, bekerja di universitas luar negeri berarti mendapatkan akses ke jurnal terbaru, dana riset yang jelas, kolaborasi internasional, dan—yang tak kalah penting—penghargaan terhadap waktu dan ide.
Di sisi lain, kembali ke Indonesia sering kali berarti menabrak tembok birokrasi, minimnya dana penelitian, dan kultur akademik yang belum sepenuhnya inklusif terhadap inovasi.
Sy & Hosoe (2023) menggambarkan bahwa migrasi profesional terjadi karena kombinasi “faktor pendorong” dan “faktor penarik”. Di Indonesia, pendorongnya adalah gaji rendah, sistem riset yang kaku, dan administrasi yang melelahkan. Di luar negeri, penariknya adalah stabilitas kerja, otonomi akademik, dan penghargaan berbasis kompetensi.
Banyak diaspora akademik ingin pulang. Tapi mereka tahu, idealisme saja tak cukup. Pulang bukan hanya soal pesawat ke Jakarta, tapi juga soal sistem yang siap menerima dan memberdayakan mereka. Jika yang menanti hanya tumpukan surat tugas dan sidang struktural yang tak ada ujungnya, wacana “pulang” akan terus jadi ilusi.
Dari Nasionalisme ke Realisme—Apa yang Harus Diperbaiki?
Kita terlalu sering menggantungkan nasionalisme pada pundak individu, tanpa menghadirkan sistem yang layak untuk kembali. Ketika diaspora akademik enggan pulang, mereka sering dianggap tidak cinta tanah air. Padahal, realitasnya jauh lebih kompleks dari itu.
Pertama, kita harus akui bahwa banyak institusi pendidikan tinggi di Indonesia belum ramah terhadap meritokrasi. Seorang diaspora dengan publikasi Q1 dan paten internasional bisa saja tetap diperlakukan seperti dosen junior karena "belum tahu kultur kampus sini." Kedua, integrasi ke dalam ekosistem riset nasional kerap kali tidak disiapkan, bahkan untuk diaspora yang ingin mengabdi secara kolaboratif.
Sistem insentif juga bermasalah. Riset dihargai berdasarkan kuantitas, bukan kualitas. Kenaikan pangkat lebih cepat jika mengurus administrasi daripada jika menghasilkan inovasi. Di sinilah letak tragedinya: kita punya sumber daya intelektual, tapi tak punya tata kelola yang cukup bijak untuk memeliharanya.
Apa yang bisa dilakukan? Pemerintah perlu membuat skema khusus untuk pemulangan diaspora akademik yang bukan sekadar seremoni, melainkan dibarengi fasilitas, fleksibilitas, dan integrasi kebijakan.
Kampus harus dibekali anggaran otonom dan manajemen SDM berbasis kualitas. Dan yang paling penting: budaya akademik kita harus tumbuh dewasa—tidak mudah tersinggung oleh kritik, terbuka terhadap perbedaan cara berpikir, dan menghargai profesionalisme di atas senioritas.
Pulang Bukan Kewajiban, tapi Harapan yang Harus Diciptakan
Dosen diaspora Indonesia bukan tidak cinta tanah air. Mereka hanya belum melihat alasan kuat untuk kembali. Dan itu bukan salah mereka. Itu salah sistem yang belum mampu menciptakan ruang hidup yang layak bagi intelektual.
Ironisnya, kita sering memanggil diaspora saat krisis—ketika kita butuh ahli untuk presentasi internasional atau penyusunan visi besar. Tapi setelah itu, mereka kembali menjadi “tamu” dalam sistem sendiri. Kita mencintai kepakarannya, tapi belum bersedia menyesuaikan sistem untuk menghargainya.
Pulang ke Indonesia seharusnya menjadi pilihan yang rasional, bukan sentimental. Jika sistem pendidikan tinggi kita bisa menjanjikan kesejahteraan, profesionalisme, dan otonomi yang sehat, maka dosen diaspora akan pulang bukan karena diminta, tapi karena merasa dibutuhkan dan dihargai.
Jadi, jika kita ingin wacana “pulang” menjadi kenyataan, kita harus berhenti menyalahkan individu, dan mulai membenahi struktur. Karena cinta tanah air bukan soal alamat domisili, tapi soal kontribusi yang diberi ruang untuk tumbuh.
Cek berita dan artikel lainnya di GOOGLE NEWS