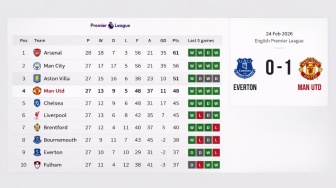Dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (1/7/2025), Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa proyeksi defisit APBN tahun 2025 telah melebar ke angka Rp662 triliun atau 2,78% dari PDB. Angka ini lebih besar dari target awal sebesar Rp616,2 triliun.
Mengapa hal ini bisa terjadi?
Defisit APBN bukanlah kesalahan rakyat. Ini bukan karena warung online terlalu banyak, atau karena karyawan-karyawan kantoran kurang patuh bayar pajak. Defisit terjadi karena negara belanja lebih banyak dari yang bisa dihasilkan.
Belanja negara memang penting. Tapi apakah belanja negara selama ini dikelola dengan efektif dan efisien? Berapa persen dari anggaran yang benar-benar sampai pada masyarakat bawah, dan berapa persen yang terserap oleh biaya birokrasi dan proyek yang tak berdampak langsung?
Di sisi lain, pemerintah punya delapan prioritas yang terus digaungkan, yaitu program makan bergizi gratis, pendidikan, kesehatan, ketahanan energi dan pangan, koperasi Merah Putih, hingga perlindungan sosial.
Tapi dalam praktiknya, belanja negara kita sering kali terjebak dalam program-program pencitraan, bukan pemberdayaan. Program digelar megah, tapi tak menyentuh kebutuhan paling mendesak.
Gedung dibangun besar-besaran, tapi pelayanan di dalamnya tetap lambat. Banyak juga proyek yang digarap terburu-buru menjelang akhir tahun anggaran, hanya agar dana terserap sempurna, bukan agar manfaatnya terasa maksimal.
Contohnya program “Makan Bergizi Gratis”. Apakah kita punya data gizi anak yang akurat? Apakah sekolah punya kapasitas logistik dan infrastruktur yang memadai? Atau ini hanya menjadi proyek besar-besaran yang lebih banyak memberi rezeki pada vendor katering ketimbang memperbaiki kualitas hidup anak-anak?
Karena di saat yang sama, banyak sekolah negeri di daerah yang masih kekurangan guru, gedungnya rusak, bahkan tidak punya toilet yang layak. Kalau yang gratis hanya makanannya, tapi anak-anak tetap belajar di ruang kelas berdebu dan pakai kursi rusak, apa itu yang dimaksud dengan “pembangunan sumber daya manusia”?
Lalu bicara soal ketahanan energi, yang belakangan ini malah tercoreng oleh polemik pembelian jet tempur, bukan oleh inovasi energi bersih.
Ketahanan pangan pun masih jadi PR besar, petani masih menjerit soal harga jual yang tidak sebanding dengan ongkos produksi. Beras lokal dikalahkan oleh impor, pupuk subsidi langka, dan irigasi banyak yang mati.
Jadi kita ingin tahan pangan, tapi tidak benar-benar memberdayakan yang menanamnya. Kita bicara swasembada, tapi tetap tergantung pada rantai pasok global. Lalu uang triliunan itu sebenarnya untuk memperkuat petani, atau hanya untuk menambah gedung dan birokrasi di kementerian pertanian?
Sementara belanja terus meningkat, penerimaan negara justru menurun. Dari target Rp3.005,1 triliun, proyeksi realisasinya hanya sebesar Rp2.865,5 triliun atau baru 95,4% dari target. Beberapa penyebabnya adalah batalnya pemberlakuan penuh PPN 12%, dividen BUMN yang masuk ke Danantara (bukan lagi APBN), hingga harga komoditas yang melemah.
Dengan kondisi seperti ini, lalu kenapa pemerintah tidak menyesuaikan langkah, dan justru tetap memaksa untuk berlari?
Pemerintah sepertinya takut mengoreksi janji politiknya, meski realita ekonomi sudah berkata lain. Maka solusi yang dianggap aman, yaitu efisiensi di sana-sini dan potong anggaran kementerian demi bisa terus membiayai program prioritas presiden. Program-program ini seolah menjadi bukti bahwa negara hadir, tanpa sempat ditimbang apakah itu tahan lama, atau hanya pamer kebijakan.
Melebarnya defisit bukan hanya soal angka di neraca. Ia adalah tanda bahwa negara kita tidak sedang baik-baik saja. Tapi saat ini, sayangnya pemerintah lebih sibuk mempertahankan narasi bahwa “semuanya masih terkendali”.
APBN 2025 sedang dihadapkan pada tantangan besar, yaitu defisit yang melonjak, pendapatan yang turun, dan tekanan belanja dari janji-janji politik.
Kita patut mempertanyakan, apakah belanja negara saat ini benar-benar untuk rakyat, atau hanya untuk memenuhi ambisi kekuasaan?