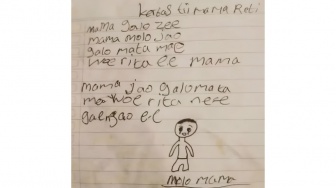Pemerintah kembali melayangkan wacana yang bikin timeline ramai, yaitu memblokir gim Roblox. Alasannya karena banyak konten kekerasan di dalamnya.
Pemerintah ingin memblokir Roblox untuk melindungi anak-anak dari pengaruh buruk dunia digital. Sekilas terdengar heroik. Tapi sebenarnya, apakah pemblokiran itu benar-benar melindungi, atau cuma memberi rasa aman semu?
Roblox adalah platform kreatif tempat pemain membuat dunia virtual, menulis skrip, mendesain karakter, bahkan menjual karya mereka. Bukan sekedar gim tembak-tembakan atau adu kekerasan. Anak-anak yang tertarik coding bisa belajar bahasa pemrograman sederhana lewat Roblox Studio.
Banyak yang menjadikan Roblox sebagai batu loncatan untuk keterampilan digital. Tapi ya, sama seperti YouTube, TikTok, atau media sosial lainnya, kontennya tergantung siapa yang membuat, dan tidak semua kreator peduli soal keamanan anak.
Masalahnya, pemblokiran sering dilakukan tanpa memisahkan mana sisi positif yang bisa dimanfaatkan, dan mana yang harus diawasi.
Psikolog anak sudah bilang, regulasi yang tepat lebih penting daripada blokir total. Verifikasi usia, standar keamanan, sampai kampanye literasi digital harusnya jadi fokus.
Soalnya, anak-anak yang mau mengakses konten tertentu selalu menemukan cara. Hari ini Roblox diblokir, besok mereka mungkin pindah ke platform lain yang malah lebih gelap dan tidak terpantau.
Di Indonesia, literasi digital memang masih jadi PR besar. Pemahaman soal keamanan daring, etika, dan penggunaan teknologi belum merata. Banyak orang tua yang bahkan tidak tahu gim apa yang dimainkan anaknya, apalagi cara mengaktifkan parental control. Jadi kalau Roblox diblokir sekalipun, risiko anak terpapar konten serupa di tempat lain tetap tinggi.
Di sisi lain, pemblokiran juga sering jadi cara instan pemerintah untuk menunjukkan respons cepat. Publik lihat ada masalah, pemerintah keluarkan kebijakan larangan, semua terlihat tanggap.
Pakar pendidikan seperti Ubaid Matraji dari JPPI sudah mengingatkan, “Pemblokiran hanya solusi jangka pendek. Yang mendesak adalah literasi digital bagi orang tua dan anak.” Dan ini bukan cuma teori. Di banyak negara, literasi digital dijadikan kurikulum sejak dini. Anak-anak belajar mengenali hoaks, mengatur privasi, dan menolak interaksi mencurigakan di dunia maya.
Sayangnya, di sini pendekatannya masih reaktif. Tunggu masalah besar muncul, baru ada kebijakan. Padahal kalau literasi digital sudah kuat, kasus-kasus seperti konten kekerasan di Roblox bisa diminimalisir tanpa harus memblokir platform.
Kita juga perlu bicara tentang akses dan pengawasan. Banyak keluarga yang membiarkan anak bermain gim online berjam-jam tanpa pengawasan karena menganggap itu aman selama anaknya anteng. Di sinilah masalahnya. Anak bisa masuk ke ruang obrolan dengan orang asing, mengakses game tematik yang tidak sesuai usia, atau melihat konten yang menormalisasi kekerasan. Dan ini berarti bukan masalah Roblox saja.
Maka, kalau wacana blokir Roblox benar-benar dijalankan, apa yang sebenarnya kita dapat? Apakah anak-anak akan otomatis aman? Atau justru mereka akan beralih ke platform lain yang jauh lebih sulit diawasi karena namanya tidak seterkenal Roblox?
Mungkin yang kita harus kita lakukan adalah memperbesar pengawasan yang bijak, memberi orang tua alat dan pengetahuan untuk memantau aktivitas anak secara efektif. Memberi anak pemahaman bahwa dunia digital punya sisi gelap yang harus dihindari.
Karena melindungi anak di dunia digital itu tidak cukup hanya dengan memutus kabel internet mereka. Tapi juga dengan membekali mereka dengan kemampuan mengenali risiko, memilih dengan bijak, dan berani berkata “tidak” pada konten yang berbahaya.