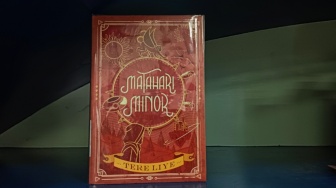Pernahkah kita menyadari bahwa banyak kebijakan publik di negeri ini terasa seperti keputusan mendadak, serba reaktif, dan tak pernah benar-benar memikirkan dampak jangka panjang? Mulai dari bantuan sosial, program MBG, hingga perubahan syarat usia calon presiden?
Fenomena ini bukan semata persoalan teknis, melainkan pola pikir yang bisa disebut sebagai “sindrom Nobita”—alias suka menunda, bergantung pada solusi instan, dan terlalu berharap ada ‘alat ajaib’ yang menyelesaikan semuanya dalam sekejap.
Dalam konteks ini, sindrom Nobita bukan berarti menyalahkan karakter fiktif dari Jepang. Ini tentang mentalitas pemangku kebijakan yang enggan bersusah payah membangun sistem yang kokoh, dan lebih memilih solusi jangka pendek yang cepat terlihat, meski tidak berkelanjutan.
Mentalitas Dana Cepat Habis, Perencanaan Terabaikan
Logika yang sering terjadi di birokrasi kita amat sederhana: kalau ada anggaran, ya habiskan saja di periode ini. Tidak jarang program dibuat bukan karena urgensi nyata, tapi karena "sayang kalau dananya tidak dipakai."
Mentalitas ini bisa kita lihat di berbagai tingkatan, dari pemerintahan pusat hingga unit organisasi terkecil. Hasilnya? Proyek-proyek yang muncul tanpa fondasi kuat, sering kali tanpa kesinambungan. Begitu masa jabatan selesai, program pun mati. Tak ada keberlanjutan karena tidak pernah dipikirkan sejak awal.
Beberapa daerah bahkan baru menyerap 1,69% dari anggaran di kuartal awal tahun 2025—karena aturan teknis terlambat keluar dan fokus gubernur yang pindah pasca-Pilkada.
Sementara itu, penyerapan anggaran nasional dominan terjadi pada kuartal IV, memicu "syndrome bank-end" yang asal belanja agar dana tidak hangus. Ini bukan efisiensi, tapi refleksi dari mental belanja demi pencapaian target administrasi.
Pendidikan: Korban Dari Visi dan Misi yang Belum Matang
Salah satu sektor yang paling sering jadi korban mentalitas jangka pendek adalah pendidikan. Hampir setiap pergantian menteri membawa perubahan kurikulum, sistem seleksi, hingga orientasi pembelajaran. Belum sempat sistem lama beradaptasi, sistem baru sudah datang.
Tidak ada sektor yang lebih jelas terserang sindrom ini selain pendidikan. Ketua PBPGRI Prof Unifah Rosyidi menegaskan bahwa pergantian menteri sering membawa pergantian kurikulum, sehingga guru dan murid sulit beradaptasi.
Padahal UndangUndang Nomor20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa kurikulum harus mengikuti Standar Nasional Pendidikan (SNP)—bukan selera politik atau ministerial DPR kini tengah inisiasi revisi UU Sisdiknas untuk memperkuat ini. Tapi sampai ketentuan itu berlaku, pendidikan kita tetap menjadi tumbal mental pergantian cepat.
Proyek Visioner Butuh Orang Profesional
Membangun bangsa bukan hanya tentang dana besar atau rencana ambisius. Yang paling krusial justru kualitas manusianya: orang-orang yang profesional, jujur, dan punya integritas tinggi. Sayangnya, ekosistem birokrasi kita masih penuh dengan mereka yang mengejar jabatan, tapi enggan mengemban tanggung jawab substantif.
Tak heran kalau kita lebih sering melihat proyek infrastruktur mangkrak, sistem layanan digital setengah jadi, atau kebijakan publik yang hanya bagus di kertas. Dengan mental “gaji buta” dan budaya kerja formalitas, sulit membayangkan munculnya proyek jangka panjang yang benar-benar berdampak lintas generasi.
Sistem ini tidak hanya berlaku untuk APBN, tapi juga di organisasi dan dunia usaha. Hasilnya, proyek yang muncul sering berorientasi jangka pendek—dengan KPI berupa “berapa dana yang terserap”—bukan evaluasi dampak jangka panjang.
Studi World Bank 2023 menunjukkan hanya 22% proyek publik di negara berkembang menjalani cost-benefit analysis yang memadai sebelum disetujui.
Siapa yang Bertanggung Jawab?
Salah satu argumen yang sering dipakai untuk menjustifikasi ketidaksiapan berpikir jangka panjang adalah pesimisme terhadap estafet. “Kalau saya bikin proyek besar, nanti setelah saya lengser siapa yang mau ngelanjutin?”
Argumen ini sesungguhnya justru menegaskan betapa lemahnya sistem tata kelola kita. Di negara dengan sistem matang, institusi jauh lebih kuat dari individu. Tapi di sini, kekuatan terlalu berpusat pada figur, bukan sistem.
Solusi: Ubah Sistem, Bukan Sekadar Mental
Kita tidak kekurangan ide besar. Kita juga tidak kekurangan sumber daya. Tapi selama yang duduk di kursi pengambilan keputusan masih punya mental Nobita—menunda, enggan berpikir panjang, dan malas bertanggung jawab—maka mimpi besar tinggal mimpi.
Perubahan hanya bisa terjadi bila kita mulai dari hal sederhana: membangun budaya kerja profesional, berorientasi hasil, dan memikirkan kesinambungan. Karena negara yang maju bukan dibangun oleh orang pintar sesaat, tapi oleh mereka yang konsisten menanam benih untuk masa depan.
“Kalau masih punya mental seperti ini, ya mimpi saja dulu.”