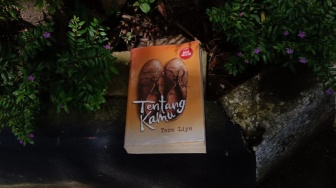Lagi-lagi, wacana e-voting kembali dilempar ke ruang publik. Pak Romy Soekarno dari Komisi II DPR kali ini mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera bertransformasi menuju "demokrasi 5.0".
Dengan "demokrasi 5.0", pemilu kita nantinya akan diselenggarakan serba digital, seperti pakai e-voting dan teknologi canggih lainnya. Kata beliau, ini bakal bikin biaya pemilu bisa ditekan jadi "cuma" Rp52 sampai Rp58 triliun dari yang tadinya bisa mencapai Rp100 triliun.
Pak Romy percaya bahwa e-voting akan membuat proses pemilu lebih efisien, hemat biaya, dan bebas dari kecurangan kertas.
Kedengarannya keren, ya? Tapi yang jadi pertanyaan, emang kita udah siap?
Masalah utamanya adalah e-voting butuh data yang bersih dan sistem identifikasi digital yang solid. Tapi sampai hari ini, kita masih punya PR besar dalam urusan itu. Contohnya saja E-KTP yang seharusnya jadi fondasi identifikasi digital saja masih sering jadi sumber masalah, baik bagi rakyat yang mengurus, maupun petugas yang melayani.
Sudah sering kali kita mendengar kasus data ganda, data salah alamat, atau warga yang tidak bisa memilih karena NIK-nya tidak terdaftar? Dan jangan lupakan berita rutin tahunan tentang kebocoran data pribadi.
Lalu sekarang kita bicara soal e-voting?
Pak Romy juga menyebut bahwa e-voting bisa mencegah kecurangan kertas sampai 100 persen. Angka 100 persen itu terlihat menggiurkan, tapi juga mencurigakan. Mungkin beliau lupa bahwa di dunia digital, kecurangan itu tidak hilang, hanya saja berubah bentuk.
Kalau di sistem kertas kita masih bisa menemukan "hantu" pemilih ganda atau suara yang tiba-tiba bertambah, maka di sistem digital kita harus berhadapan dengan bug, backdoor, atau bahkan serangan siber yang terorganisir.
Kalau manipulasi suara berbasis kertas membutuhkan oknum dan logistik, maka sistem digital cukup dengan kode berbahaya, akses admin, dan satu celah keamanan. Lebih parahnya lagi, jejaknya bisa nyaris tak terlihat.
Sistem elektronik bisa menutup keterlibatan masyarakat sipil, pengamat pemilu, bahkan saksi partai. Saat semuanya dikendalikan oleh algoritma dan server, maka kita hanya bisa percaya pada "sistem", padahal sistem itu juga dibangun dan dijaga oleh manusia.
Kalau kertas saja bisa dicurangi, apa jaminannya elektronik tidak? Hanya karena kita tak bisa melihat cara curangnya, bukan berarti tidak ada kecurangan.
E-voting juga katanya akan dikombinasikan dengan biometrik, entah itu sidik jari, retina, atau face recognition. Tapi di sinilah muncul kekhawatiran, apakah rahasia suara benar-benar masih rahasia?
Salah satu prinsip demokrasi adalah kerahasiaan suara. Pemilih harus merasa aman dan bebas memilih tanpa takut identitas pilihannya diketahui orang lain. Jika sistem face recognition diterapkan, apa jaminannya bahwa data biometrik kita tidak akan disalahgunakan atau dilacak?
Di negara +62 dengan tingkat kepercayaan publik rendah, ketakutan ini tentu bukan paranoid. Banyak warga mungkin justru takut menggunakan hak pilihnya secara jujur jika khawatir pemerintah (atau pihak tertentu) bisa mengetahui arah suaranya.
Bukan hanya itu, Pak Romy juga menyebut e-voting bisa menekan biaya jadi “hanya” Rp52–58 triliun. Tapi mari kita tengok ke belakang, pengalaman proyek digital pemerintah lebih sering overbudget dan underperform.
Sebut saja KTP elektronik, dengan anggaran triliunan, hasilnya bukan saja lambat tapi juga menyisakan korupsi besar-besaran. Begitu juga aplikasi-aplikasi pemerintah yang sering tidak optimal, serba lambat, dan tidak terintegrasi. Lalu apakah kita yakin bisa mengelola sistem pemilu nasional yang melibatkan 200 juta pemilih secara digital?
Masalah lainnya adalah apakah ketersediaan infrastruktur internet yang memadai sudah merata dan stabil di seluruh pelosok Indonesia? Bagaimana dengan daerah-daerah terpencil yang bahkan sinyal telepon saja susah didapat, apalagi koneksi internet yang kuat untuk e-voting? Karena pemilu bukan hanya tentang Jakarta atau kota-kota besar, tapi juga hajat seluruh rakyat Indonesia.
Lalu, bagaimana dengan literasi digital masyarakat? Tidak semua warga negara kita melek teknologi. Ada jutaan orang tua dan warga di pedesaan yang memang tidak terbiasa dengan gawai pintar. Memaksa mereka untuk beradaptasi dengan e-voting justru berpotensi disenfranchise sebagian besar pemilih.
Harus kita akui bahwa sistem pemilu kita memang belum sempurna. Tapi solusinya bukan berarti harus meloncat ke teknologi tinggi. Justru yang harus diperbaiki adalah kepercayaan terhadap prosesnya.
Perbaiki pendataan pemilih. Perkuat verifikasi identitas secara manual dan digital. Libatkan publik lebih aktif sebagai pengawas dan pelapor. Dan yang terpenting, tingkatkan transparansi dalam proses rekapitulasi.
Karena demokrasi bukan sekadar alat pencoblosan. Demokrasi adalah proses yang melibatkan kepercayaan, partisipasi, dan akuntabilitas. Dan semua itu tidak serta merta hadir hanya karena kita ganti kertas dengan layar sentuh.