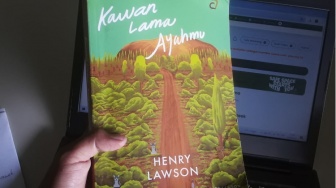Sobat yoursay, pernah mempertanyakan mengapa anak-anak kita terlihat semakin sulit berempati? Mengapa mereka bisa memukul, menendang, atau merundung teman sendiri tanpa merasa gentar, bahkan ada yang merekamnya sambil tertawa?
Pertanyaan ini makin menyesakkan ketika kita membaca kasus demi kasus yang muncul, seolah-olah kita sedang menyaksikan generasi yang tumbuh tanpa kemampuan mendasar untuk merasakan sakit orang lain.
Nama MH, siswa kelas VII SMPN 19 Tangerang Selatan, kini menjadi pengingat kelam. Ia meninggal setelah berminggu-minggu menahan sakit akibat perundungan yang dilakukan teman sekelasnya. Bukan sekali, bukan juga dua kali, MH mengaku sering dipukul dan ditendang.
Hingga pada satu hari di bulan Oktober, sebuah bangku besi menghantam kepalanya. Dan ketika ia akhirnya menyerah pada rasa sakit itu, kita semua seperti tersentak… tetapi sudah terlambat.
Kasus ini menjadi contoh perundungan, sekaligus gejala dari krisis empati.
Sobat Yoursay, empati tidak bisa lahir begitu saja. Empati ditumbuhkan lewat interaksi dan bukti bahwa emosi itu penting. Empati diasah ketika anak belajar membaca ekspresi muka, nada suara, atau ketidaknyamanan orang lain. Namun anak-anak Indonesia tengah tumbuh dalam lanskap yang memutus jalur itu.
Pertama, kita hidup di era paparan kekerasan digital yang tak lagi bisa dibendung. Ketika anak terbiasa menonton kekerasan yang lucu, ringan, atau viral, mereka belajar bahwa rasa sakit bisa menjadi hiburan.
Video perundungan, prank keterlaluan, konten prank sosial eksperimen, dan drama kekerasan menjadi makanan sehari-hari. Otak mereka pun perlahan terbiasa, dan adegan pukul-memukul bukan lagi sesuatu yang memicu empati, tetapi menjadi sesuatu yang biasa saja.
Kedua, minimnya interaksi tatap muka membuat generasi ini kesulitan membaca emosi orang lain. Banyak anak tumbuh dalam dunia yang didominasi layar, di mana mata mereka tidak benar-benar bertemu, dan ekspresi bisa diabaikan dengan satu swipe.
Interaksi digital ini tidak mengajarkan mereka menangkap getar suara, raut sedih, atau ketegangan tubuh seseorang. Dan ketika kemampuan membaca emosi melemah, empati pun ikut menurun. Mereka mungkin tahu definisi menyakiti, tetapi tidak merasakan konsekuensinya.
Ketiga, sekolah kita tanpa sadar ikut mengikis empati melalui budaya kompetitif yang berlebihan. Kita dibesarkan dalam sistem yang menilai prestasi akademik jauh lebih penting daripada kecerdasan sosial.
Di banyak kelas, empati dianggap kelemahan, membantu teman saat ulangan bisa dihukum, mengakui kelemahan dilabeli cengeng, dan keberhasilan diukur dari angka, bukan karakter. Anak-anak jadi belajar bahwa yang penting adalah menjadi unggul, bukan menjadi baik.
Akibatnya, kualitas seperti berbelas kasih, peduli, dan sensitif terhadap perasaan orang lain tidak dilihat sebagai bagian dari kecerdasan, tetapi sebagai sesuatu yang tidak berguna di arena kompetisi.
Namun, sobat yoursay, dunia sebenarnya punya alternatif. Beberapa negara melakukan gebrakan besar dengan memasukkan empati sebagai bagian inti kurikulum.
Di Denmark, misalnya, sejak 1993 sekolah mengadakan kelas empati yang wajib diikuti siswa. Mereka belajar berbicara tentang perasaan, menyelesaikan konflik dengan dialog, memahami perspektif teman, dan memastikan tidak ada murid yang merasa terasing. Hasilnya pun nyata, tingkat kebahagiaan dan kesehatan mental anak-anak mereka termasuk yang terbaik di dunia.
Anak-anak yang dilatih berempati sejak kecil tumbuh menjadi remaja yang lebih mampu mengenali emosi orang lain. Dan data menunjukkan bahwa mereka cenderung lebih sedikit terlibat dalam kekerasan.
Lalu apa yang bisa dilakukan?
Jawabannya mungkin tidak sesederhana membuat aturan baru di sekolah atau memberikan sanksi tegas kepada pelaku bullying. Kita butuh pelan-pelan mengembalikan kemampuan anak untuk berempati.
Itu dimulai dari rumah, tempat pertama di mana anak belajar bahwa emosi itu tidak tabu. Orang tua perlu mengajarkan regulasi emosi sejak dini, seperti mengenali marah, mengelola kecewa, dan menenangkan diri.
Di sekolah, ruang dialog harus dibuka. Anak perlu diajak berbicara tentang perasaan, bukan hanya tentang nilai. Ketika konflik terjadi, penyelesaian restoratif perlu diutamakan, bukan hanya hukuman yang membuat anak semakin dendam atau semakin tidak peduli.
Di dunia digital, kita juga perlu lebih sigap. Anak harus diajarkan bahwa setiap komentar punya dampak, setiap video menyimpan cerita, dan rasa sakit tidak boleh jadi tontonan.
Sobat yoursay, krisis empati adalah masalah moral, yang juga menjadi krisis masa depan. Jika anak-anak tumbuh tanpa kemampuan merasakan sakit orang lain, apa yang akan terjadi ketika mereka menjadi remaja, dewasa, atau pemimpin kelak?
Empati tidak bisa diwariskan, ia harus ditanam. Dan hari terbaik untuk mulai menanamnya adalah hari ini.