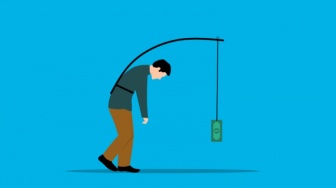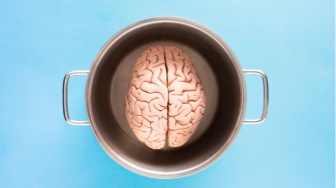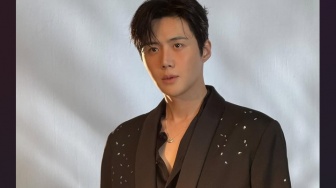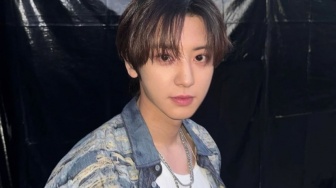Di tengah kepadatan kota, suara klakson dan derap mesin seolah menjadi latar abadi kehidupan urban. Gedung-gedung menjulang, lampu jalan menyala sepanjang malam, dan orang-orang bergegas mengejar waktu yang tak pernah mau berhenti. Di ruang yang sesak itu, siapa pun bisa merasa kehilangan ruang bernapas. Namun, ada titik-titik kecil yang menghadirkan jeda. Alunan musik dari sudut komunitas, permainan angklung di balai warga, atau sekadar nada bambu yang ditiup pelan di sebuah taman kota. Seni, yang sering dianggap pelengkap, ternyata bisa menjadi terapi yang memberi ruang lega bagi jiwa yang penat.
Kisah itu nyata di Surabaya. Di Lingkungan Pondok Sosial Keputih, Dinas Sosial Kota Surabaya rutin menghadirkan terapi seni-musik bagi penghuni dengan gangguan jiwa. Pertunjukan musik, nyanyian bersama, hingga gerakan sederhana dijadikan sarana rehabilitasi. Antara melaporkan bahwa kegiatan itu membantu menenangkan suasana hati sekaligus melatih memori para penghuni yang sebelumnya kerap terjebak dalam kecemasan.
Di tempat lain, jauh dari ruang rehabilitasi resmi, seniman dan warga di Kampung Jelekong, Bandung, mempraktikkan art therapy secara lebih spontan. Detik.com menuliskan bagaimana para seniman lokal menggunakan lukisan dan aktivitas kreatif bukan hanya untuk berkarya, melainkan juga sebagai cara menenangkan diri dari tekanan hidup sehari-hari. Seni, dalam wujud paling sederhana, hadir sebagai ruang aman untuk melepaskan beban.
Fungsi terapi ini sesungguhnya bukan sekadar cerita anekdot. Riset kesehatan menunjukkan hal serupa. Sebuah kajian yang dilakukan di Surakarta terhadap mahasiswa menemukan bahwa terapi musik efektif menurunkan tingkat stres, depresi, dan kecemasan di kalangan pelajar yang terbebani tuntutan akademik. Penelitian lain di Kota Jambi bahkan memperlihatkan bagaimana musik klasik, diperdengarkan setiap hari selama seminggu, mampu meningkatkan kemampuan berbahasa anak dengan autisme. Bukti-bukti ini menegaskan bahwa musik tidak hanya menghibur, tetapi benar-benar bekerja pada dimensi kognitif dan emosional manusia.
Dalam konteks komunitas, efeknya bisa lebih luas. Komunitas musik tradisional di berbagai kota memperlihatkan bagaimana seni menjadi ruang lintas kalangan. Di Serang, Banten, penelitian menunjukkan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus yang dilibatkan dalam permainan angklung mengalami peningkatan motorik dan kognitif. Hal ini membuktikan bahwa instrumen sederhana sekalipun, ketika dimainkan bersama, dapat menghadirkan manfaat yang lebih besar daripada sekadar alunan nada. Dari sisi sosial, ruang ini juga menyatukan berbagai latar belakang: anak sekolah, guru, orang tua, hingga pekerja kantoran, semua bisa bertemu dalam satu irama. Seni menghapus sekat, dan dalam irama kolektif, lahirlah perasaan diterima.
Namun perjalanan komunitas seni tidak selalu mulus. Tantangan nyata selalu ada. Pendanaan sering kali menjadi masalah klasik. Banyak komunitas harus berlatih di ruang seadanya, bahkan kadang harus mengalah ketika ruang latihan dipakai untuk acara komersial. Dominasi musik digital modern juga membuat seni tradisional kerap dianggap usang, seolah tidak lagi mampu bersaing dengan ritme cepat yang ditawarkan gawai. Di balik semua itu, stigma masih melekat. Seni dianggap hiburan semata, bukan kebutuhan. Padahal, di balik tiupan suling atau denting angklung, tersimpan fungsi terapeutik yang lebih dalam daripada sekadar mengisi waktu senggang.
Kota yang penuh sesak tanpa ruang seni ibarat tubuh tanpa jiwa. Gedung tinggi mungkin menandakan kemajuan, tetapi manusia di dalamnya membutuhkan ruang untuk bernapas. Komunitas seni, sekecil apa pun, mampu menjadi paru-paru kota. Ia bukan hanya menyajikan hiburan, melainkan menciptakan atmosfer yang menenangkan. Ketika seorang ibu menemukan ketenangan dari meniup suling untuk meredakan vertigonya, atau seorang remaja merasa diterima meski baru belajar memainkan alat musik, kita melihat bukti bahwa seni membangun ikatan yang tak kasat mata tetapi terasa nyata.
Dalam kerangka yang lebih luas, kita bisa membayangkan seni sebagai bentuk public therapy. Tidak semua orang mampu atau mau pergi ke psikolog, dan layanan kesehatan mental masih terbatas di banyak kota. Tetapi hadir di komunitas musik, melukis bersama, atau sekadar mendengarkan alunan lagu tradisional di ruang terbuka dapat menjadi langkah sederhana untuk memelihara jiwa. Kementerian Sosial pernah melaporkan bagaimana program art therapy di pusat rehabilitasi Bandung bukan hanya membantu pemulihan mental penerima layanan sosial, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan produktif seperti menjahit atau membuat mozaik. Seni, dengan begitu, menjadi jembatan antara penyembuhan dan pemberdayaan.
Semua kisah ini menyimpan pelajaran. Seni bukan milik seniman semata, melainkan milik siapa saja yang membutuhkan ruang lega di tengah kepadatan kota. Ia mampu menjembatani generasi, menyatukan profesi yang berbeda, dan membuka ruang bagi mereka yang kerap terpinggirkan. Di era urban stress yang kian meningkat, komunitas seni hadir bukan sekadar menjaga tradisi, tetapi juga menjaga kewarasan kita sebagai manusia.
Kita bisa bertanya apa artinya modernitas jika manusia di dalamnya kehilangan ruang untuk bernapas? Apa artinya gedung tinggi jika hati penghuninya semakin terhimpit? Melalui komunitas seni, kita diingatkan bahwa ada bentuk kemajuan yang lebih mendasar, kemampuan kota menyediakan ruang untuk manusia merasa damai. Maka mendukung komunitas seni, sekecil apa pun, sejatinya adalah mendukung kesehatan mental kota itu sendiri.