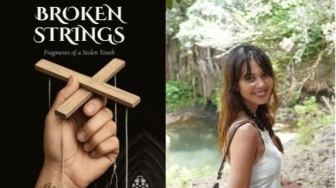Di era digital yang katanya tanpa batas, kita sering percaya bahwa semua orang punya kesempatan yang sama untuk bersuara. Siapa pun bisa mengunggah video, menulis cuitan, atau membuat petisi daring. Narasi besar tentang demokrasi digital bahkan kerap dijual dengan janji, semua orang punya panggung. Jika benar demikian, seharusnya tidak ada suara yang tercecer. Orang kota maupun desa, muda maupun tua, mereka yang terdampak langsung oleh kebijakan ataupun sekadar pengamat, semuanya bisa tampil di layar publik.
Namun, kenyataannya jauh dari ideal itu. Masih banyak kelompok yang tercecer dari percakapan digital, bahkan saat hidup mereka diguncang oleh peristiwa besar seperti penggusuran. Alih-alih menjadi pusat sorotan, mereka justru menjadi korban penggusuran digital, suara yang hilang karena tidak terkoneksi.
Melansir dari Kompas, tingkat akses internet rumah tangga di desa hanya 67 persen, jauh lebih rendah dibanding kota. Bahkan di Papua, angkanya hanya 33–38 persen. Artinya, hampir separuh rumah tangga desa masih berada di luar ruang digital. Ini menjelaskan kenapa ketika terjadi penggusuran di pelosok, jarang sekali ada dokumentasi atau cerita dari warga terdampak yang langsung muncul di media sosial.
Kesenjangan ini makin terasa bagi lansia. Dilansir dari Suara USU, banyak lansia kesulitan mengakses layanan daring seperti BPJS atau bantuan sosial karena keterbatasan perangkat dan kemampuan digital. Bahkan ada kasus seorang ibu 63 tahun di Medan yang bingung mengurus layanan kesehatan karena tidak punya smartphone. Sementara itu, penelitian di UGM juga menegaskan bahwa meski akses internet makin luas, tantangan utama lansia justru pada keterampilan penggunaan dan kualitas pemanfaatan teknologi.
Fenomena ini menunjukkan sesuatu yang lebih dalam tentang ketimpangan sosial yang ada di Indonesia. Kalau dulu, suara rakyat kecil sering kali tenggelam karena media utama memilih siapa yang layak mendapatkan perhatian. Sekarang, situasinya sudah berubah. Orang yang tidak punya gawai atau kuota internet otomatis tertutup dari dunia digital yang sedang berkembang pesat ini. Kita bisa melihat pola yang muncul dengan jelas. Berita atau isu yang cepat menyebar luas biasanya berasal dari mereka yang mampu merekam video, mengunggah, dan akhirnya menyebarkannya ke banyak orang.
Sebaliknya, mereka yang tak memiliki akses ini cukup pasrah dan hanya bisa menyaksikan. Akibatnya, masalah penggusuran yang harus menjadi perhatian publik, malah sering kali hanya menjadi angka di laporan resmi pemerintah. Mereka yang kehilangan rumah dan tanah, saja, merasa kehilangan hak mereka, tapi yang lebih menyedihkan lagi adalah mereka kehilangan narasi dan suara untuk memperjuangkan haknya. Padahal, cerita rakyat dan narasi publik itu sangat penting karena bisa memengaruhi bagaimana masyarakat dan pemerintah merespon. Dukungan dari solidaritas, tekanan dari masyarakat, hingga usaha untuk mengubah kebijakan, sering kali muncul berkat viralnya berita di media sosial.
Tanpa jejak digital yang jelas, korban penggusuran ini sangat rentan terlupakan dan tak mendapatkan perhatian yang mereka butuhkan selama ini. Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa digitalisasi bukan hanya soal teknologi semata, tapi juga soal keadilan sosial. Jika ruang digital ini tidak inklusif dan terbuka bagi semua orang, maka ada risiko besar bahwa digital bisa menjadi mesin penggusur kedua yang menghapus suara-suara mereka yang paling rentan dan membutuhkan perhatian lebih dari kita semua.
Lalu, apa langkah nyata yang bisa kita ambil? Pertama-tama, pemerintah dan berbagai lembaga sosial harus benar-benar memprioritaskan pembangunan literasi digital yang inklusif. Tidak cukup hanya fokus pada kota besar, tapi juga harus menyentuh desa-desa dan komunitas lansia yang selama ini sering terabaikan. Berdasarkan laporan dari Singkapnews, program Tular Nalar yang dirancang khusus untuk melatih ribuan lansia agar semakin peka terhadap teknologi digital telah menunjukkan hasil positif dalam membantu mereka beradaptasi di era digital ini.
Akan tetapi, sayangnya, program semacam ini masih belum tersebar secara merata dan terencana, sehingga manfaatnya tidak bisa dirasakan oleh banyak orang. Untuk itu, perlu adanya upaya sistematis dan konsisten agar program ini mampu menjangkau semua pihak yang membutuhkan, bukan hanya segelintir orang tertentu saja. Kedua, media dan aktivis harus lebih aktif dan inisiatif dalam menjembatani suara dari kelompok-kelompok yang rentan dan sering terlupakan. Jangan sampai situasi ini hanya bergantung pada mereka untuk “melek digital”, melainkan kita sebagai bagian dari masyarakat harus datang langsung ke lapangan, keluar dari zona nyaman, dan mendokumentasikan kisah nyata mereka.
Dengan cara ini, korban penggusuran dan orang-orang yang selama ini tertindas tidak hanya menjadi statistik belaka, melainkan juga manusia yang punya cerita, perjuangan, dan harapan yang layak didengar oleh banyak orang. Lebih dari sekadar angka, mereka perlu diwakili dan dipahami secara manusiawi. Ketiga, kita sebagai warga masyarakat juga memiliki peran penting. Jangan hanya mengikuti tren isu yang sedang viral di media sosial demi mengejar populartas atau sekadar cari perhatian.
Sebaliknya, kita harus belajar dan berusaha mencari suara-suara yang selama ini hilang dan tidak terdengar. Solidaritas digital seharusnya tidak berakhir di unggahan di timeline media sosial saja, tetapi juga mendorong agar cerita dan pengalaman kelompok rentan tetap hidup dan hadir di ruang-ruang publik. Dengan begitu, suara mereka tidak akan terpinggirkan dan perjuangan mereka tetap terlihat nyata di tengah-tengah keramaian informasi yang ada saat ini.
Digitalisasi memang membuka peluang besar bagi demokrasi, tapi sekaligus menciptakan jurang baru. Mereka yang terhubung dan mereka yang tercecer. Korban penggusuran sering kali menjadi korban ganda, kehilangan rumah secara fisik dan kehilangan suara secara digital. Jika kita tidak segera membenahi kesenjangan ini, maka ruang digital hanya akan jadi panggung bagi sebagian orang, sementara yang lain perlahan lenyap tanpa pernah tercatat dalam sejarah.