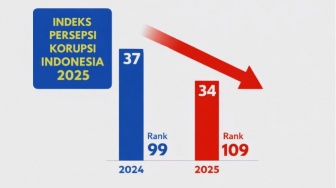Belakangan ini, di linimasa media sosial, terutama TikTok, muncul tren baru yang membuat banyak orang tiba-tiba terdiam setelah menontonnya. Bukan karena videonya menampilkan sesuatu yang mengejutkan, melainkan karena ia membuka ruang dalam hati yang selama ini sering kita kunci rapat-rapat. Tren itu sederhana saja: mempertemukan diri kita yang sekarang dengan diri kita di masa kecil, lewat sentuhan teknologi AI.
Di layar, tampak wajah kecil kita yang polos, dengan tatapan mata penuh tanya. Anak kecil itu—yang sesungguhnya adalah kita sendiri—akan menyapa versi dewasa kita dengan pertanyaan sederhana yang seringkali menohok. “Nanti kita bakal jadi dokter, kan?” atau “Kita masih suka main hujan-hujanan, ya?” atau bahkan sesederhana “Kita bahagia, kan?” Lalu di sisi lain, ada diri kita yang sekarang, dengan mata lelah, dengan tubuh yang sudah dipenuhi oleh kenyataan hidup, mencoba menjawab sejujur mungkin.
Sekilas, tren ini tampak seperti hiburan semata. Banyak yang menertawakan hasil suntingan AI itu, ada yang menjadikannya bahan bercanda dengan mengubah jawaban jadi kocak, ada yang menambah musik dramatis untuk efek. Namun, di balik gelak tawa, ada banyak orang yang diam-diam merasa matanya panas. Ada luka lama yang terbuka kembali. Ada mimpi-mimpi kecil yang ternyata tidak pernah sampai. Dan ada kenyataan pahit yang mau tidak mau harus diakui: hidup membawa kita jauh dari harapan masa kecil.
Saya jadi teringat, betapa polosnya kita dulu saat ditanya tentang cita-cita. Ada yang mantap menjawab ingin jadi guru, dokter, tentara, pilot, atau penyanyi terkenal. Ada pula yang lebih sederhana, ingin punya rumah besar, ingin bisa naik mobil sendiri, atau sekadar ingin selalu bahagia. Kita kecil tidak pernah tahu bahwa jalan menuju ke sana berliku, penuh batu, bahkan kadang tidak ada jalannya sama sekali. Kita hanya percaya, bahwa semua keinginan itu akan terwujud ketika kita dewasa. Karena bagi anak kecil, orang dewasa adalah jawaban atas segala pertanyaan.
Namun, ketika akhirnya kita sampai di usia dewasa, apa yang terjadi? Kita bekerja keras bukan untuk mengejar mimpi, melainkan untuk bertahan hidup. Kita tidak lagi menimbang-nimbang pekerjaan apa yang sesuai dengan passion, tetapi pekerjaan apa yang bisa membayar sewa rumah dan membeli beras bulan ini. Kita tidak lagi terlalu memikirkan ingin jadi apa, karena kenyataan sudah memilihkan kita berada di titik yang bahkan dulu tidak pernah kita bayangkan. Dan ketika diri kecil itu bertanya, “Nanti kita jadi guru, kan?” kita hanya bisa tersenyum kecut sambil menjawab, “Tidak bisa, Cil. Kita harus kerja yang lain, karena hidup tidak semudah itu.”
Momen inilah yang membuat tren AI ini terasa begitu menyayat. Bukan karena teknologinya canggih, tetapi karena ia menyodorkan cermin yang tidak pernah kita minta. Cermin yang mempertemukan dua diri: diri kecil yang penuh harap, dan diri dewasa yang penuh kompromi. Antara impian dan realita, antara kepolosan dan kelelahan.
Tetapi, mungkin ada hal yang lebih dalam lagi. Tren ini tanpa sadar memberi ruang kepada kita untuk berbicara dengan masa lalu, untuk meminta maaf, bahkan untuk berterima kasih. Tidak banyak dari kita yang pernah punya kesempatan untuk duduk diam dan berkata kepada diri kecil, “Maaf, hidup ternyata berat. Maaf kalau kita tidak jadi seperti yang kamu harapkan.” Dan sekaligus berkata, “Terima kasih karena kamu dulu berani bermimpi. Tanpa mimpi itu, mungkin kita tidak akan pernah sampai sejauh ini.”
Bertemu diri kecil lewat AI seperti sebuah dialog yang tak pernah kita siapkan, tetapi entah kenapa terasa sangat dibutuhkan. Kita seringkali keras kepada diri sendiri, merasa gagal, merasa tertinggal, merasa tidak berguna. Padahal, kalau diri kecil itu benar-benar ada di depan kita, mungkin ia tidak akan marah. Mungkin ia hanya akan menatap kita dengan senyum polosnya, lalu berkata, “Kamu sudah berusaha, kan? Aku bangga.”
Di titik ini, saya mulai berpikir: mungkin tren ini begitu viral karena ia menyentuh sisi terdalam dari kerinduan manusia. Bukan kerinduan pada orang lain, melainkan kerinduan pada diri sendiri. Kita rindu pada masa kecil yang sederhana, rindu pada mimpi-mimpi yang begitu besar, rindu pada versi diri yang belum mengenal kompromi. Dan ketika teknologi memberi jalan untuk seakan-akan bercakap dengan diri kecil, hati kita langsung merespons. Seakan ada pintu lama yang terbuka. Seakan ada percakapan yang tertunda puluhan tahun akhirnya bisa dimulai.
Tentu saja, kenyataan hidup tetaplah kenyataan. Tidak semua mimpi kecil bisa diwujudkan. Tidak semua jalan bisa ditempuh. Banyak di antara kita yang mungkin menatap diri kecilnya dan berkata, “Maaf, aku tidak jadi apa-apa.” Tetapi mungkin, justru di situlah nilai sesungguhnya dari tren ini. Ia mengingatkan kita bahwa hidup bukan sekadar tentang mencapai cita-cita, melainkan tentang bertahan. Tentang berjuang. Tentang tetap melangkah meskipun tidak sesuai peta.
Dan bukankah itu juga sebuah pencapaian? Bukankah diri kecil kita akan tetap bangga melihat bahwa kita masih berdiri hingga hari ini? Bahwa meski kita tidak jadi guru, dokter, atau pilot, kita tetap berusaha menjadi manusia yang baik, anak yang berbakti, orang tua yang penuh cinta, pasangan yang setia, atau bahkan sekadar individu yang berusaha tidak menyakiti orang lain. Hal-hal kecil itu, seringkali justru lebih besar dari sekadar profesi yang dulu kita cita-citakan.
Ketika menulis ini, saya membayangkan diri kecil saya sendiri. Saya ingin sekali menatap matanya dan berkata, “Maaf, aku tidak bisa mewujudkan semua mimpi kamu. Aku juga sering salah langkah, sering kalah, sering menyerah. Tapi aku selalu berusaha. Dan aku harap kamu bangga.” Saya percaya, kalau anak kecil itu benar-benar bisa menjawab, ia akan tersenyum sambil berkata, “Aku memang tidak minta kamu sempurna. Aku hanya minta kamu tetap berani.”
Dan bukankah itu sebenarnya inti dari hidup? Berani untuk tetap melangkah, meski jalannya berbeda. Berani untuk menerima diri sendiri, meski tidak sesuai ekspektasi. Berani untuk mencintai diri yang penuh luka, sekaligus tetap merawat harapan kecil di dalam hati.
Tren AI ini mungkin hanya akan viral sebentar. Besok atau lusa, ada tren baru lagi yang menggantikannya. Tetapi percakapan dengan diri kecil, percakapan yang menyayat namun membebaskan, akan selalu tinggal di hati. Karena pada akhirnya, kita semua butuh ruang untuk berdamai dengan masa lalu. Kita semua butuh kesempatan untuk menatap diri kecil dan berkata: terima kasih sudah pernah bermimpi, terima kasih sudah berani percaya, dan terima kasih sudah mengantarkan aku sampai di titik ini.
Mungkin kita tidak jadi apa yang dulu kita cita-citakan. Tetapi kita tetap berharga. Kita tetap pantas dicintai. Dan diri kecil itu, saya yakin, akan selalu bangga pada kita.