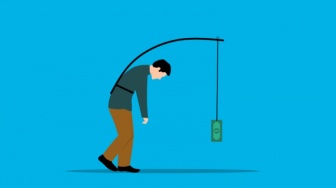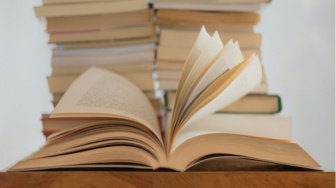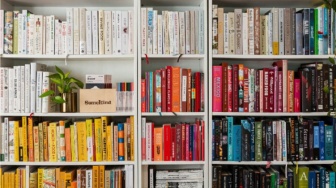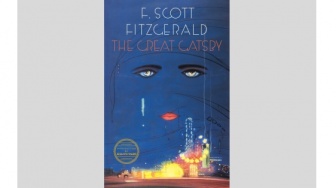Di tengah meningkatnya angka pengangguran terbuka di Indonesia, satu kelompok yang kerap menjadi sorotan adalah Generasi Z. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa lulusan baru, terutama dari kelompok usia 15–24 tahun, masih mendominasi pengangguran. Generasi ini kemudian sering dilabeli sebagai “picky”, alias pilih-pilih pekerjaan. Narasi itu cepat menyebar, seolah-olah akar masalah terletak pada karakter generasi yang dianggap manja, tidak tahan banting, dan terlalu idealis.
Namun, apakah tudingan itu benar? Atau justru cerminan dari masalah struktural di dunia kerja yang tidak memberi ruang memadai bagi Gen Z untuk tumbuh?
Realitas Lapangan yang Tidak Sesuai Ekspektasi
Generasi Z tumbuh di era digital dengan akses informasi yang lebih luas. Mereka tahu standar gaji, tahu tren kerja global, dan menyadari hak-hak pekerja lebih baik dibanding generasi sebelumnya. Wajar bila mereka memiliki ekspektasi. Namun sering kali ekspektasi itu berbenturan dengan kenyataan.
Upah minimum yang ditawarkan di banyak sektor masih berkutat pada angka pas-pasan, kadang bahkan di bawah biaya hidup layak di kota besar. Di sisi lain, tuntutan kerja semakin tinggi: jam kerja panjang, beban target menumpuk, hingga minimnya jaminan kesehatan dan keamanan kerja. Tidak sedikit perusahaan masih menormalisasi sistem kontrak jangka pendek atau bahkan outsourcing dengan kepastian masa depan yang nyaris nol.
Apakah dalam kondisi ini Gen Z bisa begitu saja disalahkan karena enggan menerima pekerjaan apa adanya? Rasanya kurang adil. Menolak pekerjaan dengan syarat eksploitatif bukanlah cerminan manja, melainkan kesadaran akan nilai diri.
Narasi "Pilih-Pilih" yang Menyederhanakan Masalah
Label pilih-pilih pekerjaan juga berbahaya karena menyederhanakan masalah struktural menjadi persoalan individu. Seolah-olah penyebab pengangguran hanyalah karena Gen Z terlalu banyak maunya. Padahal, mismatch antara keterampilan lulusan dengan kebutuhan industri masih menjadi masalah utama.
Lulusan perguruan tinggi, misalnya, didominasi jurusan sosial-humaniora. Sementara pasar kerja menuntut lebih banyak tenaga terampil di bidang teknologi, manufaktur, atau sains terapan. Akibatnya, banyak anak muda yang terjebak dalam lingkaran: sudah berpendidikan tinggi, tetapi sulit menemukan pekerjaan sesuai bidang. Ketika mereka menolak bekerja jauh dari kompetensi yang ditempuh bertahun-tahun, label pilih-pilih kembali dilekatkan.
Masalah ini bukan unik Indonesia. Studi di berbagai negara menunjukkan generasi muda memang lebih kritis dalam memilih pekerjaan, terutama soal work-life balance, fleksibilitas, dan makna kerja. Bedanya, di negara dengan sistem perlindungan sosial lebih baik, pilihan ini dipandang sebagai bagian dari dinamika pasar kerja. Di Indonesia, justru direduksi menjadi “kemanjaan generasi”.
Perspektif Gen Z tentang "Kerja Layak"
Jika menelusuri lebih dalam, Gen Z tidak sekadar menginginkan gaji besar atau kerja ringan. Mereka mendambakan kerja yang layak—sebuah konsep yang sudah lama diakui oleh International Labour Organization (ILO). Kerja layak mencakup gaji yang adil, kondisi kerja aman, kesempatan berkembang, serta jaminan sosial.
Generasi ini juga lebih terbuka terhadap pekerjaan non-tradisional. Freelancer, content creator, hingga gig worker menjadi pilihan yang dianggap memberi fleksibilitas. Sayangnya, sektor ini juga sering kali tidak terlindungi aturan ketenagakerjaan yang memadai. Ada ruang eksploitasi baru yang muncul: jam kerja tak terbatas, pembayaran tertunda, hingga hilangnya perlindungan hukum.
Fenomena ini menunjukkan Gen Z tidak menolak bekerja. Mereka hanya tidak mau terjebak dalam pekerjaan yang membuat masa depan gelap sejak awal.
Perlu Perubahan Cara Pandang
Menuding Gen Z sebagai penyumbang pengangguran terbesar karena pilih-pilih pekerjaan justru menutup ruang diskusi penting: bagaimana pemerintah, kampus, dan industri bisa menciptakan ekosistem kerja yang lebih sehat.
Pemerintah perlu memastikan pelatihan vokasi benar-benar menjawab kebutuhan industri. Perusahaan harus berhenti menggunakan narasi "kamu harus berjuang dulu, nanti akan sukses" sebagai justifikasi eksploitasi. Sementara itu, lembaga pendidikan perlu menyiapkan mahasiswa dengan keterampilan adaptif, bukan hanya teori.
Gen Z bukan generasi yang malas. Mereka adalah generasi yang tumbuh dengan kesadaran tinggi tentang nilai hidup dan kerja layak. Jika mereka enggan menerima pekerjaan yang tidak memberi kepastian, itu adalah tanda kewarasan, bukan kelemahan.
Penutup
Menyalahkan Gen Z karena pilih-pilih pekerjaan adalah jalan pintas yang keliru. Yang lebih mendesak adalah memperbaiki kualitas lapangan kerja dan memastikan transisi pendidikan ke dunia kerja berjalan mulus. Sebab, pada akhirnya, pengangguran bukan semata soal individu yang terlalu banyak maunya, melainkan soal struktur ekonomi yang gagal menyediakan ruang kerja yang manusiawi.