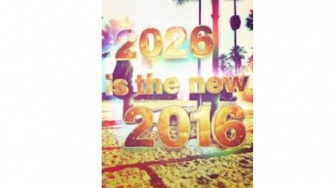Di lorong-lorong kampus, di ruang diskusi, bahkan di caption media sosial, kita sering disuguhi fenomena yang menjengkelkan yaitu jargon flexing. Ini adalah praktik menggunakan istilah-istilah akademik, teori rumit, atau kosakata asing yang njlimet secara berlebihan, bukan demi menjelaskan suatu konsep, melainkan semata-mata untuk pamer kepintaran.
Alih-alih mencerahkan, bahasa yang seharusnya menjadi jembatan komunikasi justru berubah menjadi tembok kesombongan yang dibangun dari tumpukan istilah asing.
Padahal, penggunaan bahasa yang efektif dan mudah dipahami adalah kunci kesuksesan seorang akademisi dan profesional, sebagaimana ditegaskan dalam jurnal "Pandangan Mahasiswa Terhadap Keefektifan Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Komunikasi pada Lingkungan Kampusoleh" oleh Djuria Suprato (2022) di Proceeding Seminar Nasional Bahasa, Seni, Sastra, dan Pengajarannya di Era Digital, yang menekankan bahwa bahasa yang baik akan mempermudah komunikasi di lingkungan kampus.
Logika dasar komunikasi adalah efektivitas dan efisiensi. Kita bicara agar orang lain paham, bukan agar mereka sibuk membuka Google untuk mencari arti kata-kata kita. Sayangnya, banyak mahasiswa yang terjebak dalam mindset keliru: semakin rumit bahasanya, semakin tinggi level pemikirannya.
Padahal, para ilmuwan dan filsuf besar dunia justru berusaha menyederhanakan konsep yang kompleks agar dapat diakses publik. Jika kita benar-benar menguasai ilmu, kita seharusnya mampu menyampaikannya dalam bahasa yang paling transparan dan mudah dicerna, bukan malah membuatnya semakin keruh dan berlapis.
Jargon sebagai Eksistensi Kelompok, Jargon sebagai Hambatan
Dalam kajian sosiolinguistik, jargon memang memiliki fungsi ganda. Di satu sisi, seperti diulas dalam jurnal "Studi Sosiolinguistik tentang Jargon di Lingkungan Galangan Kapal Batam" (Schnitzler et al., 2025), jargon berfungsi sebagai penanda eksistensi kelompok sosial tertentu.
Dalam konteks kampus, jargon menjadi "kode rahasia" yang memperkuat identitas jurusan (misalnya: hanya anak marketing yang paham istilah "metrik konversi").
Namun, para peneliti juga memperingatkan bahwa penggunaan jargon dapat menjadi kendala bagi orang yang tidak familiar. Di sinilah letak kritiknya: Ketika jargon akademik dibawa ke ranah publik atau diskusi interdisipliner, tujuannya bergeser dari membangun identitas internal menjadi menghalangi pemahaman pihak luar.
Jargon flexing sering terjadi karena mahasiswa gagal melakukan code-switching—gagal beralih dari bahasa akademik yang dituntut di skripsi ke bahasa komunikasi sehari-hari. Mahasiswa yang parno terlihat biasa atau bodoh merasa wajib "berbau" akademik di setiap forum, padahal konteksnya mungkin hanya diskusi ringan antar-jurusan.
Padahal, kemampuan mengkomunikasikan informasi dengan jelas adalah kunci membangun kolaborasi dan hubungan sosial yang baik. Jargon yang tidak relevan justru merusak potensi networking ini.
Secara sosial, jargon flexing menciptakan jarak otoriter. Ketika kita sengaja menggunakan istilah yang hanya kita dan segelintir orang yang mengerti, kita memaksa pendengar untuk berada di posisi inferior, merasa bodoh, atau terintimidasi.
Ini bukan lagi komunikasi yang memberdayakan, melainkan monolog yang berkedok diskusi. Jika tujuan utama pendidikan adalah menyebarkan ilmu, maka penggunaan bahasa yang eksklusif seperti ini justru bertentangan dengan semangat sharing dan inklusivitas ilmu pengetahuan, sebuah ironi yang sering terjadi di lingkungan yang seharusnya paling terbuka.
Skala Ukur Kebodohan Diri: Gagal Menerjemahkan, Gagal Memahami
Seorang dosen filsafat pernah bilang: "Jika kamu tidak bisa menjelaskan teorimu kepada nenekmu, berarti kamu belum benar-benar menguasainya." Jargon rumit seringkali hanyalah topeng untuk menutupi pemahaman yang dangkal.
Ketika mahasiswa hanya mampu mengulang definisi teoritis tanpa mampu menguraikannya ke dalam contoh nyata atau bahasa yang sederhana, itu adalah tanda bahwa ia hanya menghafal, bukan memahami esensi. Kemampuan menyederhanakan kompleksitas adalah bukti penguasaan materi tertinggi, sekaligus modal utama saat mahasiswa harus bernegosiasi atau berkolaborasi dengan pihak di luar circle mereka.
Dari Flexing ke Networking: Mengubah Bahasa Jadi Jembatan Karier
Lulus dari kampus, dunia profesional tidak peduli seberapa banyak istilah "diskursus hegemoni" yang kamu hafal. Mereka peduli seberapa cepat dan efektif kamu bisa memecahkan masalah dan menyampaikan solusi.
Komunikasi yang efektif, bebas jargon yang tidak relevan, justru akan membuka lebih banyak pintu networking dan karir. Kemampuan menjual ide kompleks dalam bahasa marketing yang crisp jauh lebih berharga daripada kemampuan menulis esai yang sarat footnote dan istilah Latin—kecuali jika Anda memang sedang menulis esai itu sendiri.
So, Stop Jargon Flexing! Saatnya kita buktikan bahwa mahasiswa Indonesia bukan hanya jago menghafal istilah, tetapi juga mahir menjadi jembatan ilmu ke masyarakat.
Buang jauh-jauh budaya pamer kata-kata yang tidak perlu. Mari kita gunakan bahasa sebagai alat yang tajam, efektif, dan edukatif. Karena kekuatan sejati sebuah gagasan terletak pada kejelasannya, bukan pada kerumitan labelnya.
Yuk, mulai sekarang, stop jargon flexing, dan mulailah makna flexing yang benar-benar bisa mengubah dunia!