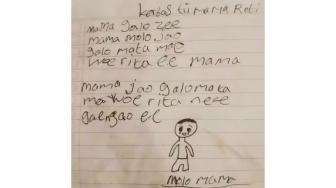Laut bukan sekadar air asin yang memisahkan pulau; bagi masyarakat Nusantara, laut adalah jalan raya, kitab suci, dan ibu sekaligus.
Di setiap kampung nelayan dari Sabang sampai Merauke, Cerita Dari Pesisir masih hidup dalam bentuk pantun, doa, tarian, dan perahu-perahu yang dibuat tanpa paku. Itulah budaya bahari Nusantara: peradaban besar yang lahir dan besar di atas ombak.
Leluhur kita bukan bangsa darat yang kebetulan memiliki pantai; kita adalah bangsa laut yang kebetulan memiliki daratan. Perahu pinisi Bugis-Makassar, jong Jawa, lis-álas Aceh, hingga padewakang Mandar adalah bukti teknologi maritim tertua dan termutakhir pada masanya.
Mereka berlayar hingga Madagaskar dan Australia ratusan tahun sebelum Columbus menemukan benua Amerika.
Pengetahuan navigasi bintang, ramalan cuaca lewat awan dan burung, serta seni membangun kapal tanpa gambar teknik diturunkan secara lisan dari bapak ke anak, dari nakhoda ke anak buah kapal. Semua itu bukan sekadar keterampilan; itulah identitas.
Di Lamalera, Lembata, masih ada suku pemburu paus tradisional yang menangkap leviathan dengan tombak bambu dari perahu tenun.
Di Kepulauan Kei, petuanan laut mengatur zona penangkapan ikan dengan hukum adat yang lebih ketat daripada undang-undang modern.
Di Riau, orang laut (suku Duano) hidup di atas rumah rakit dan mengenal setiap alur arus seperti kita mengenal jalan ke rumah tetangga.
Di Bawomataluo, Nias selatan, tarian perang moyo diakhiri lompat batu yang melambangkan keberanian melompati ombak besar. Semua itu adalah SuaraHijau yang sama: harmoni antara manusia dan laut.
Akan tetapi, warisan itu kini rapuh. Anak-anak di kampung pesisir lebih fasih berbahasa Inggris dari aplikasi daripada logat bahari leluhur mereka.
Perahu pinisi terakhir yang benar-benar dibuat tanpa paku hanya tinggal segelintir, sisanya sudah memakai besi dan mesin diesel.
Ritual sedekah laut banyak yang berubah menjadi pesta hiburan semata. Modernitas membawa kapal fiber, GPS, dan pasar global, tetapi juga membawa lupa.
Ketika generasi muda lebih mengenal influencer daripada nakhoda tua yang hafal rute rempah, maka hilanglah bukan hanya tradisi, melaingung seluruh cara pandang terhadap laut.
Di tengah ancaman itu, muncul geliat baru. Di Wakatobi, anak-anak sekolah diajak membangun perahu mini sederhana sambil mendengar cerita leluhur Bajo dari kakek mereka.
Di Banyuwangi, festival Gandrung Sewu mengajak ribuan penari menampilkan gerakan yang meniru ombak dan angin musim timur. Di Bulukumba, sekolah pinisi didirikan untuk mengajarkan kembali ilmu membuat kapal suci tanpa paku.
Di Pulau Messah, Flores, komunitas muda menghidupkan kembali tradisi menenun ikat dengan motif laut sambil mengkampanyekan pelestarian terumbu karang. Mereka semua adalah Suara Hijau yang menolak budaya bahari menjadi museum mati.
Cerita Dari Pesisir harus terus mengalir seperti pasang naik. Ia hidup ketika seorang anak kecil di Kepulauan Aru masih bisa membaca arah angin dari bau laut pagi.
Ia hidup ketika perempuan-perempuan di Aceh Selatan masih menyanyikan “hikayat prang sabi” untuk mengantar suami melaut. Ia hidup ketika seorang nakhoda pinisi di usia 70 tahun masih mau mengajari anak muda cara “membaca bintang” di tengah malam gelap tanpa lampu.
Budaya bahari bukan masa lalu yang romantik; ia adalah modal hidup bangsa kepulauan yang sedang menghadapi kenaikan air laut dan perubahan iklim.
Orang-orang yang mengenal laut secara turun-temurun adalah penjaga terbaik bagi 17.000 pulau kita. Merekalah yang tahu kapan harus menanam mangrove, kapan harus melarang menangkap ikan, dan kapan harus pindah kampung sebelum bencana datang.
Matahari terbenam di ufuk barat masih sama seperti yang dilihat leluhur kita seribu tahun silam. Selama masih ada anak-anak yang mau mendengar Cerita Dari Pesisir, selama masih ada tangan-tangan muda yang mau memegang kemudi kayu jati, maka budaya bahari Nusantara tidak akan pernah karam.
Ia hanya menunggu kita kembali menarik layar, mengikuti angin yang sama yang pernah membawa nenek moyang kita menaklukkan samudra.