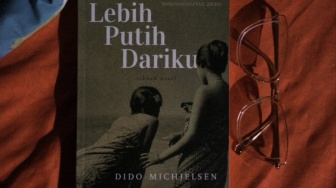Komunikasi pemerintah kepada publik dalam menjelaskan kondisi bencana di Sumatra masih berbeda-beda dan tidak terarah. Akibatnya, publik merasa waswas hingga kepercayaan terhadap para pejabat menurun drastis.
Menurut Konsultan Komunikasi dan Public Relation, Dr. Haililah Tri Gandhiwati, S.S., S.Si., M.M., solusi yang dapat ditawarkan adalah melalui “One Voice Policy” yang merupakan prinsip komunikasi yang seharusnya dilakukan pemerintah saat menghadapi bencana agar berjalan dengan cepat, tepat, dan empatik.
Survei Indeks Persepsi Komitmen Pemerintah yang dilakukan Litbang Kompas menunjukkan bahwa 56,4% publik memiliki komitmen kuat hingga sangat kuat. Hal ini disebabkan publik melihat kehadiran fisik aparat, seperti TNI dan Basarnas yang sedang menjalankan tugas di lapangan.
Sebaliknya, terdapat 41,6% publik berkomitmen lemah hingga sangat lemah karena merasa kecewa terhadap pemerintah yang lambat menetapkan status bencana dan gagal mencegah kejadian berulang.
Data tersebut menunjukkan bahwa pemerintah perlu bergegas memperbaiki kepercayaan publik. Angka kepuasan dan kekecewaan ini tergolong rawan dan menjadi sinyal serius potensi krisis legitimasi apabila terjadi kesalahan komunikasi.
Menurut analisis Gandhi, pemerintah harus mampu mengembalikan tingkat kepercayaan publik hingga mencapai 70% agar mayoritas masyarakat dapat merespons secara positif.
Berbagai sentimen di media sosial yang dilaporkan oleh Drone Emprit dan Goodstats menunjukkan sekitar 48% sentimen positif, sementara sentimen negatif di platform X berkisar antara 35–60%, serta 17% sentimen netral.
Contoh dari sentimen positif adalah apresiasi tertinggi diberikan kepada TNI dan Basarnas atas aksi heroik evakuasi menggunakan helikopter hingga solidaritas warga yang disertai oleh gerakan #PrayForSumatera.
Kemudian, contoh sentimen negatif yaitu kritik keras terhadap kegagalan ekologi (deforestasi dan tambang ilegal) yang dianggap sebagai akar masalah karena status bencana nasional tak kunjung ditetapkan.
Sentimen juga mengindikasikan bahwa apresiasi ditujukan secara spesifik kepada institusi TNI dan SAR, sementara institusi sipil mendapatkan sentimen negatif yang tinggi.
Oleh sebab itu, strategi yang dapat dilakukan pemerintah dalam menangani sentimen tersebut adalah menenangkan kegaduhan publik serta menyelaraskan respons untuk memulihkan kepercayaan publik.
Temuan sentimen tersebut menjadi semakin krusial ketika dikaitkan dengan fase awal penanganan bencana. Dalam situasi bencana, informasi yang salah dapat membunuh sama cepatnya dengan air bah.
Bahkan, koordinasi yang macet dapat menyebabkan kepercayaan publik anjlok. Fakta ini terlihat ketika 72 jam pertama yang seharusnya menjadi waktu emas penyelamatan justru diisi oleh konflik narasi antarlembaga, penurunan indeks kepercayaan publik, serta perbedaan data bantuan yang beredar.
Ego sektoral menjadi salah satu penyebab utama kegagalan komunikasi pemerintah saat ini. Setiap lembaga cenderung lebih sibuk mempertahankan citra, kewenangan, dan versinya masing-masing, alih-alih membangun satu suara yang terpadu dan berorientasi pada keselamatan publik.
Akibatnya, informasi yang disampaikan menjadi tumpang tindih, pengambilan keputusan berjalan lambat, dan publik kehilangan rujukan yang dapat dipercaya. Padahal, kejujuran yang pahit justru lebih dihargai daripada kebohongan yang terdengar manis.
Hal ini sejalan dengan pandangan Konsultan Komunikasi dan Strategi Litigasi, Retno Kusumastuti, yang menegaskan bahwa penerapan One Voice Policy sangat penting. Tanpa kebijakan tersebut, kepercayaan publik berisiko hilang.
Solusi lain yang disarankan adalah pembentukan juru bicara khusus dan tim manajemen krisis, sehingga pemimpin tidak perlu merangkap sebagai juru bicara.
Selain itu, penyusunan talking points juga diperlukan agar komunikasi lebih terstruktur dan membantu pembicara tetap fokus menyampaikan pesan kunci secara konsisten, baik dalam forum publik, rapat, maupun wawancara media.
Talking points berperan penting dalam membantu pembicara menyampaikan pesan secara langsung pada inti persoalan, menjaga nada bicara tetap tenang, menyesuaikan bahasa tubuh, serta merespons emosi publik dengan dukungan data yang akurat.
Pengelolaan visual juga tak kalah penting, karena publik membutuhkan bukti kehadiran negara yang nyata yaitu negara yang hadir dan “berkeringat” di lapangan, bukan sekadar fokus pada rapat dan perdebatan di dalam ruangan.
Wartawan senior, Teguh Setiawan, menegaskan bahwa insiden komunikasi yang terjadi saat ini mencerminkan kelemahan yang bersifat sistemik.
Jika berkaca pada masa lalu, Indonesia pernah memiliki juru bicara kebencanaan yang sangat mumpuni, seperti Sutopo Purwo Nugroho yang menjadi juru bicara saat Letusan Gunung Agung, Gempa Lombok, dan Tsunami Palu, serta Ahmad Yurianto yang memainkan peran penting pada fase awal wabah COVID-19.
Menurut Teguh, Indonesia kini kehilangan sosok juru bicara yang mampu menggunakan bahasa yang tidak melukai, membangkitkan harapan bagi warga terdampak, bersifat non-normatif, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam tata kelola kebencanaan.
Kondisi tersebut menjadi catatan penting bagi pemerintah dan pemangku kebijakan untuk meninjau kembali pola komunikasi dalam penanganan bencana.
Tanpa kehadiran juru bicara yang mampu merangkul emosi publik dan mendorong keterlibatan masyarakat, komunikasi kebencanaan berisiko kehilangan daya empatik dan legitimasi.
Oleh karena itu, penguatan One Voice Policy, penunjukan juru bicara khusus, serta komunikasi yang jujur dan manusiawi harus menjadi agenda mendesak dalam reformasi tata kelola kebencanaan di Indonesia.